oleh
Myrna A. Safitri
Pendiri dan anggota Perkumpulan HuMa, Direktur Eksekutif Epistema Institute, pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
Orasi disampaikan pada Pembukaan KTT Hukum Rakyat
Perkumpulan HuMa
Jakarta 8 Oktober 2013
Salam Nusantara!
Ibu/Bapak dan Saudara-saudara sekalian, izinkan saya mengawali ceramah ini dengan mengutip penggalan pengalaman saya setahun lalu. Pengalaman ini terjadi di sebuah desa, di pelosok Delta Mahakam, Kalimantan Timur. Warga desa itu harus berbagi lahan dengan sebuah perusahaan minyak dan gas alam asing. Ini berlangsung sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Kehidupan warga diisi harapan menetesnya ‘rezeki’ dari keberadaan perusahaan tersebut. Hal yang terjadi namun tidak pernah sebanding dengan hilangnya tanah sebagai sumber kesejahteraan utama dan lebih permanen bagi warga.
Tentu kisah seperti ini banyak terjadi di sekitar saudara-saudara, para Pendamping Hukum Rakyat. Namun, perlu saya tambahkan dari cerita ini adalah secara tiba-tiba masyarakat diberitahukan bahwa tanah-tanah mereka dijadikan hutan negara. Tidak ada lagi layanan administrasi pertanahan di desa dan kecamatan yang dapat diterima. Wargapun berucap: “Jika kami dianggap sebagai warga negara, mengapa kami tidak boleh memasuki tanah negara kami sedangkan perusahaan asing itu bebas melakukan pengeboran minyak dan gas di atas tanah negara kami?” Kita menyaksikan bahwa warga negara itu telah terasing dari kekayaan negaranya sendiri.
Pada cerita yang lain, saya ingin mengingatkan saudara-saudara sekalian pada peristiwa di tahun 1999. Itulah saat diselenggarakannya Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang pertama. Pernyataan heroik yang kemudian menjadi pengikat gerakan masyarakat adat adalah: “Jika negara tidak mengakui kami, kami tidak akan mengakui negara”.
Yang hendak saya sampaikan dengan dua cerita di atas adalah bahwa di mata sebagian besar warga masyarakat adat, masyarakat lokal lain, negara dalam berbagai wujudnya menunjukkan empat kecenderungan.
Pertama, negara yang abai terhadap pengakuan keberadaan masyarakat adat; Kedua, negara yang lalai memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga terhadap sumber kesejahteraan dari tanah dan kekayaan alam; Ketiga, negara yang absen terhadap tindak kekerasan yang terjadi saat konflik-konflik terjadi; Keempat, negara yang royal menjual kekayaan alam pada kelompok bisnis nasional dan asing tanpa diimbangi dengan alokasi kekayaan alam yang adil bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal lain. Terkait dengan hal ini saya ingin kutipkan pernyataan dari mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, yang menengarai sekitar 0,2% orang di Indonesia menguasai sekitar 56% aset nasional yang sebagiannya berupa tanah (Pernyataan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joto Winioto). Sementara itu, hal yang serupa dapat ditemukan pula di sektor kehutanan. Dari seluruh izin pemanfaatan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan, 99,7% diakses oleh perusahaan, dan dan hanya 0,3% diakses oleh masyarakat. Data dari Statistik Kehutanan 2011 menunjukkan sekitar tujuh juta hektar kawasan hutan digunakan untuk kepentingan perkebunan dan pertambangan. Jumlah ini sangat jauh dari angka 120 ribuan hektar izin-izin yang telah diberikan kepada masyarakat.
Pembaruan hukum yang digagas oleh kelompok masyarakat sipil dimana Perkumpulan HuMa adalah bagian yang aktif dari kelompok ini adalah pembaruan hukum negara. Perlu saya tegaskan di sini bahwa hukum perlu dipandang secara luas. Tidak hanya sistem norma yang berlaku karena paksaan kuasa negara, tetapi juga tatanan norma yang tumbuh, dijalankan dan dihormati oleh masyarakat. Inilah yang disebut hukum rakyat.
Pembaruan hukum negara bertujuan untuk memberikan koreksi terhadap keempat kecenderungan negara yang sebelumnya telah saya sampaikan. Tujuannya sangat sederhana, menjadikan negara kembali memenuhi amanat pembentukannya sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap tumpah darah, memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.
Lantas, bagaimana pembaruan hukum negara itu semestinya dilakukan?
Kita memerlukan alat ukur baru untuk menilai keberhasilan pembaruan hukum. Pembaruan hukum tidak (lagi) bisa diukur dari jumlah dan jenis legislasi yang dihasilkan (legal reform) dan pembentukan serta revitalisasi institusi-institusi hukum dan insitutsi negara lainnya (institutional reform).
Lebih dari itu, penilaian terhadap pembaruan hukum harus menukik pada pertanyaan:
Seberapa jauh perubahan-perubahan hukum dan kelembagaan yang dilakukan pemerintah dan penyelenggara negara lain benar-benar secara faktual menciptakan keadilan bagi masyarakat yang paling miskin, paling lemah posisi tawarnya, paling rentan di dalam kelompok masyarakat adat dan masyarakat lokal lain. Bagaimana pemerintah dan penyelenggara negara mampu melestarikan lingkungan dan sumber-sumber kekayaan alam yang ada?
Sistem hukum negara dan praktik penyelenggaraan hukum negara yang mampu mewujudkan keadilan inilah yang menjadi tujuan pembaruan hukum. Ironisnya, jalan menuju ke sini masih panjang. Saya mengakui ada perubahan yang terjadi pada legislasi dan pada institusi. Namun acap kali kita melihat banyak pula penelikungan dilakukan.
Walhasil, Indonesia baru berada pada derajat terendah dari negara hukum formal. Banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk membatasi kekuasaan pemerintah, namun kualitas peraturan masih banyak yang belum memenuhi syarat formal yang semestinya. Demikian pula banyak proses pembentukan hukum yang miskin partisipasi rakyat sehingga tidak mengadopsi elemen demokrasi dalam negara hukum formal.
Menurut saya, kita perlu gerak maju, bukan gerak yang involutif dalam melakukan pembaruan hukum. Partisipasi rakyat, kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat menjadi tujuan yang tak bisa ditawar dari pembaruan hukum negara tersebut.
Pembaruan hukum negara semestinya bertujuan mencapai NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN. Kita dapat melihatnya pada tujuh hal berikut ini (Gagasan Awal dikembangkang oleh Epistema Institute):
(1) Pembentukan hukum yang transparan, partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
(2) Substansi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengakui hak-hak kelompok miskin, masyarakat adat, perempuan dan kelompok minoritas;
(3) Birokrasi pemerintah yang konsisten melaksanakan kebijakan yang memberdayakan masyarakat;
(4) Lembaga-lembaga peradilan yang bersih, independen dan bermoral;
(5) Lembaga pengawal keadilan lainnya (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Yudisial, dan sebagainya) yang efektif mengawasi pelaksanaan kekuasaan negara serta melindungi hak-hak masyarakat di dalam dan di luar pengadilan.
(6) Masyarakat sipil– meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, jurnalis, jaringan sosial warga – yang kuat yang dapat menjalankan peran kontrol sosial yang efektif terhadap institusi negara.
(7) Masyarakat yang menghormati keragaman, mampu membangun struktur dan pranata sosial serta praktik relasi sosial yang adil bagi kelompok miskin, masyarakat adat, kaum perempuan dan kelompok minoritas serta menjalankan fungsi kontrol yang efektif terhadap seluruh komponen penyelenggaraan negara dan proses pembentukan hukum.
Dalam hal penguasaan tanah dan kekayaan alam, pembaruan hukum negara perlu diarahkan untuk mencapai keadilan agraria. Saya mendefinisikan keadilan agraria dimaksud sebagai situasi dimana sistem hukum negara dan tatanan hukum masyarakat, kelembagaan dan praktiknya mendukung tersedia dan menguatnya lima aspek berikut ini:
(1) Kerangka regulasi agraria yang harmonis, berkeadilan dan berperspektif hak asasi manusia;
(2) Kepastian hak dan akses atas tanah dan kekayaan alam bagi masyarakat hukum adat, buruh tani dan nelayan;
(3) Keadilan dalam alokasi ruang, tanah dan kekayaan alam dalam perencanaan ruang wilayah dan perencanaan pembangunan kehutanan, pertambangan dan pesisir;
(4) Keamanan dan perlindungan negara terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terutama terhadap perempuan, anak, dan warga miskin di wilayah konflik-konflik agraria, dan
(5) Kesejahteraan kelompok miskin dan perempuan dalam masyarakat hukum adat, buruh tani, buruh perkebunan dan nelayan yang bersumber dari lingkungan hidup yang lestari.
Demikianlah, pembaruan hukum negara adalah keniscayaan. Kita memerlukan alat ukur yang jelas sebagai pedoman membangun gerakan sosial yang efektif. Semoga KTT Hukum Rakyat ini mampu merumuskan alat-alat ukur yang dimaksud.


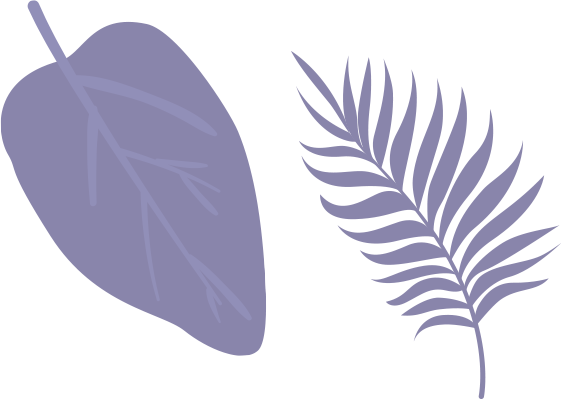
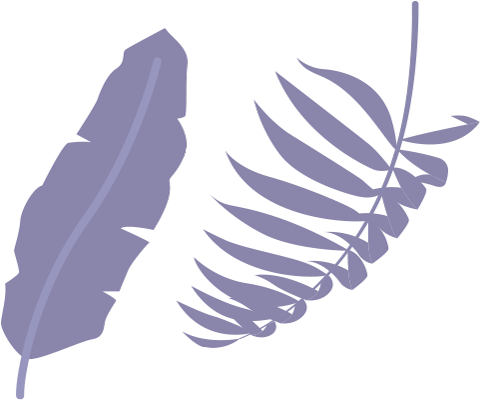
0 Comments
Leave a Reply