Penulis : firda amalia
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyelenggarakan diskusi bertajuk ‘’Pemetaan Awal Urgensi Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.’’ Diskusi yang diselenggarakan pada 2 Mei 2024 melalui zoom tersebut menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya dari Tenaga Ahli DPR RI, Aliansi Advokasi Masyarakat Hukum Adat, Persekutuan Perempuan Aliansi Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN), Aman Kalimantan Timur, PW AMAN Nusa Bunga, dan AMAN Bali.
Diskusi yang diselenggarakan oleh Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan tersebut bertujuan untuk mengetahui kebaruan informasi mengenai RUU Masyarakat Hukum Adat dan mengidentifikasi perkembangan advokasi bersama RUU Masyarakat Hukum Adat.
Penelusuran Komnas Perempuan mengungkapkan terdapat 185 komunitas adat yang tersebar di 150 desa dan kelurahan di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, hanya dua masyarakat hukum adat yang telah memperoleh pengakuan, yaitu masyarakat adat Dayak Paser Mului dan masyarakat adat Paring Sumpit, keduanya berlokasi di Kabupaten Paser. Dari dua kelompok tersebut, baru masyarakat adat Mului yang telah diakui hutan adatnya seluas 7.700 hektar di Desa Swan Slotung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sementara itu, masyarakat adat Paring Sumpit masih dalam proses pengurusan pengakuan hutan adatnya.
Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, hanya lima yang memiliki peraturan daerah mengenai tata cara pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Sebanyak 16 Masyarakat Hukum Adat (MHA) masih dalam tahap verifikasi dan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah, termasuk 10 MHA dari Kabupaten Kutai Timur, yaitu MHA Kayan Umaq Lekan Desa Miau Baru, Cluster MHA Wehea di enam desa Kecamatan Wahau, MHA Basap Tebangan Lembak di Kecamatan Bengalon, MHA Long Bentuk di Kecamatan Busang, dan MHA Basap di Karangan Dalam.
Penelusuran lain di Provinsi Bali misalnya, menunjukkan bahwa suku Bali, yang juga dikenal sebagai Wong Bali, Anak Bali, atau Krama Bali dalam bahasa Bali, merupakan etnis mayoritas di Pulau Bali. Berdasarkan Perda Desa Pakraman No. 3 Tahun 2001, masyarakat desa Bali menginginkan pengelolaan desa secara mandiri dan terpisah dari desa dinas. Pasal 1, ayat 4 Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 menyatakan bahwa: “Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang memiliki satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga, atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.”
Sementara itu, Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal memiliki keragaman suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda antar desa. Menurut jurnal “Pengukuran Gatra Sosial Budaya di Provinsi NTT,” terdapat 16 etnis asli di NTT, termasuk Helong, Tetun, Kemak, Marae, Rote, Sabu atau Rae Havu, Sumba, Manggarai Riung, Ngada, Ende Lio, Sikka-Krowe Muhang, Lamaholor, Labala, dan Alor. Namun, WALHI NTT mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir terjadi beberapa konflik agraria antara masyarakat adat dan pemerintah serta antara masyarakat dan pihak investor.
Kerentanan masyarakat adat terhadap ancaman dan pelanggaran hak-hak mereka menegaskan pentingnya RUU Masyarakat Adat sebagai langkah perlindungan terhadap segala bentuk pembangunan atau investasi yang dapat mengancam ruang hidup mereka. Tenaga Ahli DPR RI, Emmanuel J Tular mengungkapkan bahwa pemerintah belum begitu peduli dengan persoalan masyarakat adat, sehingga menyebabkan pembahasan RUU MHA menjadi stagnan.
‘’Di tingkat Bamus tidak ada masalah sebetulnya tapi di pimpinan DPR ini utamanya Ketua DPR ini masih belum ada niatan yang besar untuk melanjutkan RUU ini dan saya sangat miris ketika melihat bahwa keinginan untuk tema-tema besar termasuk masyarakat adat itu dilihat semacam formalitas saja, seharusnya bukan hanya bahan perdebatan saja tapi harus lanjut proses di legislasi karena memang masih panjang,’’ Ujar Emmanuel, Rabu, (2/05).
Emmanuel juga menekankan untuk bisa mewujudkan RUU MHA ini menjadi UU maka perlu ada advokasi yang mendalam tidak hanya di DPR, tetapi juga di setiap partai politik karena kemauan politik menjadi faktor penentu.
‘’ Jadi problematika RUU ini terhambat bukan hanya dari internal tapi juga internal. Dan waktunya juga mepet, jika pimpinan belum legowo memasukkan ini jadi Paripurna ini akan sulit. Menurut saya perlu ada identifikasi lain, perubahan judul, atau substansi yang dibuat regulasi baru atau tetap,’’ Kata Emmanuel.
Perwakilan Aliansi Advokasi Masyarakat Adat, Wahyubinatara Fernandes memberikan temuan koalisi yang mencatat ada 32 Undang-undang sektoral yang mengatur masyarakat adat dengan istilah yang sangat beragam dan hanya satu Kementerian yang memaknai istilah masyarakat adat yaitu Kemendikbud.
‘’Kalau kita lihat lagi draft sekarang yang ada di Baleg apa yang perlu diperkuat, dikurangi, dan dieksplisitkan, istilah masyarakat adat ini penting untuk menjembatani istilah yang berbeda dan istilah masyarakat adat diterima umum, sosial dan sosiologis. Kemudian tentu saja hak-hak masyarakat adat yang diperjuangkan dalam RUU ini harus dieksplisitkan lagi,’’ Utas Wahyu, Rabu (2/05).
Aliansi Advokasi Masyarakat Adat juga mendorong adanya prosedur yang terstruktur untuk pengakuan masyarakat adat, dengan identifikasi yang dilakukan oleh masyarakat adat sendiri terlebih dahulu, diikuti oleh verifikasi oleh komisi dan panitia sesuai tingkat administratif, karena terdapat masyarakat adat yang melintasi batas kabupaten dan provinsi.
‘’Kami pikir ada peluang juga menyusun RUU ini jadi omnibus agar bisa menjembatani. Lalu tantangan terakhir saya kira dukungan dari publik dan masyarakat sipil yang harus terus diperkuat. Kalau kita bicara publik, wacana masyarakat adat ini bukan wacana yang populer terutama di anak muda, memang banyak narasi yang muncul tapi sayangnya narasi yang negatif dan misleading yang mengaburkan masyarakat adat itu soal kesultanan dan istana yang bukan merupakan masyarakat adat yang tumbuh secara alami,’’ tegas Wahyu.
Ketimpangan Hak Perempuan Adat: Masalah yang Mendesak
Membicarakan masyarakat adat tentu tidak bisa lepas dengan persoalan perempuan adat. Devi Anggraini perwakilan dari PEREMPUAN AMAN mengungkapkan ada dua hal yang menjadi catatan PEREMPUAN AMAN terhadap RUU MHA. Pertama mengenai kompleksitas dari RUU MHA, kedua mengenai budaya patriarki dan feodalisme yang masih terjadi.
‘’Kami menyadari bahwa ada persimpangan identitas di perempuan adat itu sendiri, satu bagian dari warga negara dan di sisi lain ada ikatan komunal sehingga penting memahami proses-proses ini dan sayangnya ini sering hilang. Untuk perlindungan individu ada beberapa regulasi tapi untuk hak kolektif perempuan adat justru tidak ada sehingga kami melihat RUU MA ini bisa memastikan perlindungan hak kolektif perempuan adat terbunyikan,’’ Ujar Devi, Rabu, (2/05).
Devi juga menekankan tantangan lain dari RUU MHA adalah mengenai azas kesetaraan gender. Menurutnya, sampai dengan saat ini azas kesetaraan gender masih jadi perdebatan terutama dalam hak kolektif perempuan adat. ‘’Sebenarnya kalau kita lihat CEDAW jelas sudah meminta kepada Indonesia untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan secara eksplisit,’’ Kata Devi.
Pembangunan IKN: Bagaimana Nasib Hak Masyarakat Adat?
Rencana pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke IKN semakin mendekati kenyataan. Proses pembangunan infrastruktur negara dipercepat oleh pemerintah, mengakibatkan ancaman terhadap kehidupan masyarakat adat yang berpotensi kehilangan tempat tinggal mereka.. Menurut Saiduani Nyuk, perwakilan dari AMAN Kalimantan Timur terdapat sejumlah masalah yang dihadapi masyarakat adat di Kaltim khususnya adalah mengenai perizinan perusahaan yang dikeluarkan pemerintah tanpa ada partisipasi dan izin masyarakat adat, lalu proyek strategis nasional (PSN) ada bendungan yang tidak bisa diganggu oleh masyarakat adat padahal menurut pengakuan Saiduani Nyut bendungan tersebut diletakkan di wilayah masyarakat adat. Lalu soal Bank Tanah, di Kaltim khususnya di IKN saat ini mengalami hal yang parah, masyarakat diusir dari wilayah adatnya sendiri.
‘’Kita juga melihat ada patok-patok kepemilikan IKN yang sebelumnya tanah itu dikuasai masyarakat adat tapi dipatok seolah-olah tanah itu tidak ada pemiliknya. Masyarakat adat juga tidak jauh dari intimidasi, banyak di IKN dan kawasan perusahaan yang dulu tidak pernah dilarang untuk akses wilayah tapi sekarang sulit, dilarang untuk mengakses,’’ Ujar Saiduani, Rabu, (2/05).
Memperjuangkan Keadilan: Hak Masyarakat Adat di Tengah Pembangunan
Tidak hanya di Kaltim, masyarakat adat di Bali juga merasakan hal yang sama. Pengakuan bahwa Provinsi Bali adalah Desa Adat tidak serta merta menjadikan Bali aman. Saat ini, banyak wilayah di Bali yang belum memiliki peta wilayah yang pasti, sehingga sering menimbulkan konflik antara desa dengan desa, banjar dengan banjar, serta dengan pemerintah dan investor. Perwakilan AMAN Bali, Made Denik Puriati menjelaskan kebanyakan kasus yang terjadi di Bali adalah Bali dikembangkan jadi pusat kawasan strategis, banyak sekali pembangunan, pulau kecil yang rentan dengan daya dukung dan daya tampung dan dalam pembangunannya akan berimbas ke banyak desa seperti pembangunan tol.
‘’Kami ingin Majelis Desa Adat berbicara keluar bahwa desa itu tidak hanya ruang fisik, tidak hanya tanah, SDA, tapi ada juga sumber daya lain, kosmologi, yang dijaga baik-baik oleh Bali tapi ini tidak diperhatikan oleh pemerintah,’’ Kata Made, Rabu, (2/05).
Tidak jauh berbeda dengan Kaltim dan Bali, perwakilan AMAN Nusa Bunga, Hersan juga mengakui meskipun Di Nusa Bunga, yang mencakup Manggarai hingga Lembata, terdapat 9 kabupaten, dan dari jumlah tersebut, dua kabupaten telah memiliki perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, yaitu Kabupaten Ende dan Kabupaten Manggarai Timur. Di Manggarai Timur, perda yang berlaku adalah Perda No 1/2018, sedangkan di Ende adalah Perda Kab Ende No 2/2017. Namun, sejak 2017 hingga 2024, implementasinya tidak menunjukkan perkembangan. Meskipun perda telah ada dan Pokja telah dibentuk, kerja lapangan masih nol.
‘’Kalau dalam konteks daerah tantangannya yang kami amati ada 3 hal yang menjadi penyebab mandeknya proses kebijakan, pertama belum ada niat untuk pengakuan kepada masyarakat adat, belum ada kesamaan persepsi antar pihak, dan yang paling parah ada keraguan bahwa jika diakui maka masyarakat adat akan suka suka dalam mengelola kawasan adatnya,’’ Pungkas Hersan, Rabu, (2/05).
Pengusulan RUU Masyarakat Hukum Adat ini didasarkan pada kebutuhan mendesak dan ketiadaan pengakuan terhadap masyarakat adat, yang menyebabkan banyak dari mereka kehilangan lahan dan wilayahnya dirampas tanpa persetujuan atas nama pembangunan. Selain itu, terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat adat ketika mereka melawan perampasan wilayah adat. Ketika masyarakat adat berusaha mempertahankan hak-haknya, mereka sering dituduh menghalangi pembangunan. Bahkan, ada kasus di mana masyarakat adat yang membangun rumah di wilayah adatnya dituduh menduduki kawasan hutan dan akhirnya dipenjara. Dampak lainnya termasuk hilangnya banyak kearifan lokal, peradilan adat, dan lembaga adat yang fungsinya perlahan memudar.


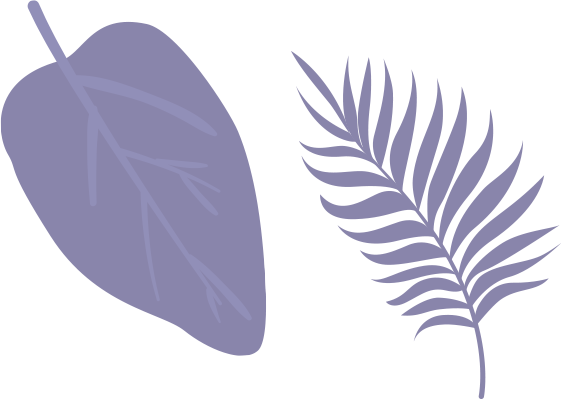
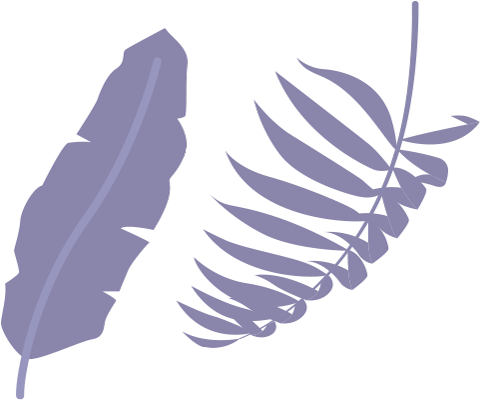
0 Komentar
Tinggalkan Balasan