Jakarta, 5 Maret 2015 – Agenda perubahan iklim dan komitmen Indonesia dalam melindungi hutan perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Indonesia. Demikian diserukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global dalam pernyataannya kepada Pers. Hal ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 tentang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang menggabungkan dua kementerian sekaligus 2 K/L setingkat kementerian, yakni Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+).
Secara umum, Koalisi mengapresiasi niat baik Presiden untuk mengefisienkan birokrasi dengan menyatukan beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dan fungsi yang saling terkait. Akan tetapi, terkait perubahan iklim, hal ini menciptakan peluang dan tantangan tersendiri yang menyangkut karakter dari isu perubahan iklim, baik di tingkat nasional maupun internasional. Karakter yang dimaksud antara lain, perubahan iklim sebagai dampak akumulatif, fungsi lintas sektor, mendesak dan bertenggat waktu, serta tidak boleh melangkah mundur (no-backsliding).
Untuk membangun dan merehabilitasi ketahanan sosial masyarakat dari dampak perubahan iklim, Koalisi mengusulkan agar Pemerintah menjalankan agenda adaptasi sama kuatnya dengan mitigasi, tanpa meninggalkan inisiatif-inisiatif yang telah dimulai sebelumnya. Koalisi juga mendesak Pemerintah agar melimpahkan fungsi koordinasi, pengawasan, dan evaluasi kepada Kementerian Koordinasi Perekonomian, dan jika memungkinkan, Kantor Kepresidenan, sehingga memiliki kewenangan lintas sektor lebih kuat.
“Perubahan iklim merupakan dampak akumulatif dari pembangunan yang tidak berkelanjutan. Akar utama persoalan harus ditinjau dari pola produksi dan konsumsi, yang hanya mementingkan keuntungan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam yang sangat eksploitatif, ditambah ketidakpekaan sistem ekonomi terhadap permasalahan ketidakadilan penguasaan sumber daya alam dan pembangunan,” tandas Mida Saragih dari Civil Society Forum.
Sudah bukan rahasia bahwa perubahan iklim yang disebabkan oleh pelepasan emisi berdampak besar pada ketahanan nasional. “Banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan seolah-olah menjadi menu wajib setiap tahun. Lahan kritis di dalam kawasan hutan telah mencapai lebih dari 27 juta hektare. Kondisi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil juga terancam karena naiknya permukaan air laut. Keanekaragaman hayati yang merupakan kekayaan Indonesia kini dalam kondisi rentan. Sementara di laut, ukuran ikan semakin menyusut karena berkurangnya kadar oksigen dalam laut akibat pemanasan global,” ujar Muhammad Djauhari dari Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK).
Koalisi menilai bahwa penanganan iklim yang berubah dengan demikian membutuhkan peran berbagai sektor, tidak hanya KLHK saja. Sebagaimana diungkapkan oleh Sisilia Nurmala Dewi dari Perkumpulan HuMa, “Kerangka kerja perubahan iklim tidak hanya bicara soal mitigasi, melainkan juga upaya adaptasi terhadap dampak yang sudah termanifestasi. Perubahan mendasar terhadap model pembangunan ekonomi juga menjadi kunci. Oleh karena itu, setidaknya ada 6 rumpun K/L yang perlu saling bersinergi, yaitu Kantor Kepresidenan, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Politik Hukum dan HAM, serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau Lembaga Non Struktural lainnya.” Fungsi lintas sektor ini juga timbul demi melaksanakan berbagai prasyarat keberhasilan penanganan perubahan iklim yang inisiatifnya telah dimulai dalam pemerintahan sebelumnya, yakni Kebijakan Satu Peta, Pemetaan Partisipatif, Moratorium Izin, Penyelesaian Konflik dan Hak Masyarakat Hukum Adat/Komunitas Lokal, serta Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melalui Henky Satrio menekankan bahwa Kebijakan Satu Peta harus menjadi prioritas karena menjadi dasar dari berbagai konflik tenurial yang berdampak pada diingkarinya pengakuan atas hak-hak masyarakat adat/lokal. Peta wilayah adat di kawasan hutan seluas 4,8 juta ha telah diserahkan AMAN kepada BP REDD+ sebelum pembubarannya selaku wali data sementara. Masyarakat adat membutuhkan kepastian bahwa inisiatif ini tetap berjalan, meski BP REDD+ sudah dihapuskan.
Sementara itu, Pengkampanye Politik Hutan Greenpeace, Yuyun Indradi, memberikan penekanan soal pentingnya melanjutkan dan memperkuat agenda moratorium izin di dalam kawasan hutan dan lahan gambut demi tata kelola yang lebih laik. “Namun dengan catatan pemerintah harus menutup berbagai celah hukum yang melegalkan konversi hutan alam dan gambut, memperketat pengawasan dan penegakan hukum, serta meninjau ulang berbagai kebijakan pembangunan yang justru mengancam lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat.” Hal senada juga diungkapkan oleh Muhamad Kosar dari Forest Watch Indonesia, “Laju deforestasi di Indonesia saat ini masih tinggi. Hal ini diakibatkan oleh kegiatan konversi dan alih fungsi, rendahnya kinerja usaha kehutanan, maupun konflik hutan dan lahan. Tidak kunjung redanya persoalan ini didorong oleh kebijakan kehutanan yang bersifat responsif, dan tidak secara kuat menyentuh masalah pokok di sektor kehutanan, yakni lemahnya tata kelola hutan.”
Edo Rakhman dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa, “Kebijakan energi nasional juga perlu menjadi pusat perhatian. Kebijakan energi nasional selama ini berorientasi kepada penggunaan bahan bakar fosil sebagai penyebab emisi karbon yang sebagian berasal dari praktik penambangan yang memiliki daya rusak tinggi. Tingkat ketergantungan akan bahan bakar fosil tersebut sangat tinggi, sementara upaya mendorong energi terbarukan (renewable energy) sangatlah kecil. Padahal persediaan sumber daya energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan sangat melimpah di Indonesia.”
Keseriusan pemerintah dalam menangani perubahan iklim juga harus ditunjukkan melalui reformasi kebijakan anggaran yang selama ini tidak mumpuni. “Yang dimaksudkan tidak mumpuni, bukanlah hanya menyangkut besaran nominal, melainkan juga mekanisme pendanaan melalui sistem APBN. Perubahan iklim berjangka panjang (multi-years), berdampak akumulatif, tidak kasat mata serta tidak terukur. Sementara APBN bersifat tahunan, dan hanya bisa mengakomodir aktivitas yang dapat disentuh dan kasat mata,” jelas Arimbi Heroepoetri, Koordinator Debtwach Indonesia.
Raynaldo Sembiring dari Indonesian Center of Environmental Law (ICEL) menyatakan bahwa, “Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus diikuti dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis, mulai dari aspek perencanaan sampai dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan harus menjadi dasar pelaksanaan tugas KLHK, terutama untuk “mengerem” pemberian izin eksploitasi yang selama ini masif dilakukan oleh KLHK. Hal paling mendesak yang dilakukan saat ini adalah penuntasan mandat penyelesaian Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) demi memberikan arahan yang jelas tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.”


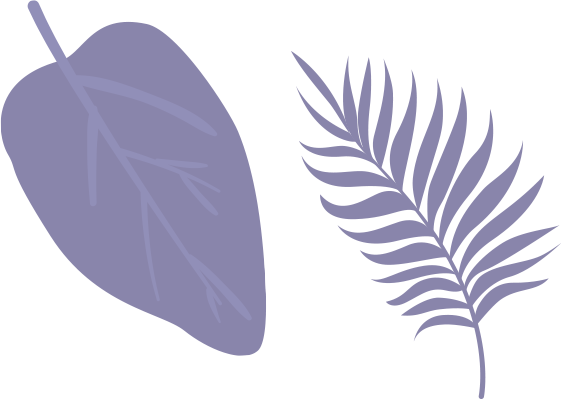
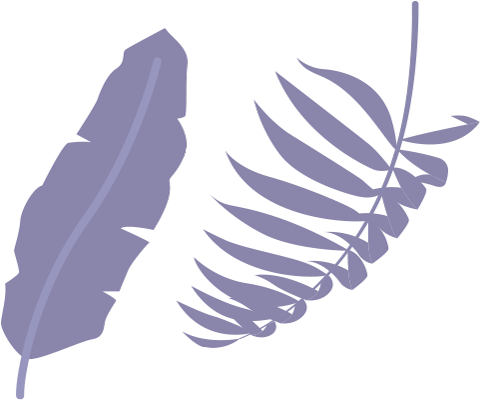
0 Komentar
Tinggalkan Balasan