Cilaka, Dampak Tidak Dipenuhinya FPIC.
Senin lalu (21/9) HuMa mengirimkan amicus curiae brief ke PTUN Jakarta atas gugatan perkara Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT. Dalam gugatan ini beberapa perwakilan masyarakat sipil mendalilkan bahwa penyusunan RUU Cipta Kerja tertutup, tidak partisipatif, dan diskriminatif karena hanya membuka akses ke KADIN dan asosiasi pengusaha. Atas gugatan itu, HuMa menambahkan pendapat hukum dalam amicus curiae brief khusus mengenai masyarakat adat. Bahwa dengan tidak melibatkan masyarakat adat dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, pemerintah telah melanggar prinsip free, prior, informed consent (FPIC) yang diatur dalam standar internasional terkait hak-hak masyarakat adat. Singkatnya, FPIC mensyaratkan pemerintah untuk melibatkan dan meminta persetujuan masyarakat adat sebelum menetapkan suatu keputusan yang berdampak terhadap masyarakat adat. FPIC ini tidak terbatas untuk penyusunan undang-undang, melainkan semua keputusan dan kebijakan, termasuk pemberian konsesi, proyek pembangunan, aktivitas perusahaan.
Tulisan ini tidak akan panjang-panjang membahas justifikasi konstitusional dan legal dari FPIC. Tidak butuh ahli hukum untuk mengatakan bahwa prinsip ini perlu, dan justifikasinya masuk akal. Kita lihat undang-undang yang selama ini lahir tanpa memenuhi prinsip FPIC dalam penyusunannya, sebut saja UU Minerba. Aturan-aturan dalam UU yang disusun tanpa FPIC sudah pasti tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat adat sama sekali. Yang ada, tiap aturan baru malah menambah beban masyarakat adat tanpa menyelesaikan masalah barang sejumput.
Wajar saja, tanpa mendengar masyarakat adat langsung, bagaimana mungkin kita mengharapkan anggota DPR yang tinggal dan berkantor di Jakarta Selatan wara-wiri dengan Land Cruiser bisa secara ajaib tau realitas yang dihadapi masyarakat adat di kawasan hutan, lebih-lebih merumuskan norma yang mengakomodasi kepentingan mereka. Mana bisa; realitas menentukan kesadaran manusia. Solusinya adalah pemenuhan FPIC dalam penyusunan undang-undang: melibatkan masyarakat adat sendiri dalam perencanaan sampai pengesahannya. Ke depan, ada banyak agenda legislasi terdekat yang membutuhkan pemenuhan FPIC: RKUHP, RUU Masyarakat Adat, dan tentunya RUU Cipta Kerja. Jangan sampai mengulang trauma UU Minerba.
Namun, Bagaimana Benar-Benar Memenuhi FPIC?
Setelah kita bersepakat bahwa FPIC diperlukan dalam penyusunan rancangan undang-undang, muncul pertanyaan, bagaimana prosedur meminta persetujuan masyarakat adat dalam penyusunan undang-undang? Masyarakat adat di Indonesia terdiri dari ribuan komunitas, yang memiliki sistem hukum, kelembagaan, sistem kemasyarakatan, dan tentunya kebutuhan yang berbeda-beda. Mengundang satu perwakilan komunitas adat tentu tidak bisa dianggap merepresentasikan kepentingan ribuan komunitas adat di Indonesia.
Emil Ola Kleden pernah menulis makalah untuk Simposium Masyarakat Adat tahun 2012 mempertanyakan masalah yang ditemui di lapangan dalam pemenuhan FPIC.1 Di lapangan, dalam konteks pemenuhan FPIC oleh perusahaan, perusahaan sering kali meminta persetujuan beberapa individu perwakilan masyarakat, atau meminta persetujuan wakil dari satu unit sosial masyarakat adat. Namun ternyata kelompok masyarakat yang lain merasa individu yang dimintai persetujuan dianggap tidak representatif, atau unit sosial komunitas lain merasa unit sosial yang dimintai persetujuan tidak memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan. Dalam hal ini Emil Kleden mengemukakan 2 (dua) pertanyaan yang belum terjawab untuk menentukan apakah FPIC telah terpenuhi. Pertama, apa unit sosial yang dianggap representatif untuk memberikan persetujuan. Kedua, bagaimana batas ambang atau proporsi jumlah individu yang dianggap sudah representatif untuk memberi persetujuan.
Dari masalah di atas kita bisa menyimpulkan bahwa di tingkat komunitas saja indikator pelaksanaan FPIC tidak sesederhana itu. Apalagi di tingkat nasional, seperti dalam penyusunan undang-undang. Menentukan sudah atau belumnya FPIC terpenuhi tidak mudah. Belum lagi, kita tidak bisa abai bahwa di beberapa komunitas, mekanisme pengambilan keputusannya sama sekali tidak memberi penghargaan kepada perempuan adat untuk berpartisipasi. Tanpa perlu menyebutkan kasus spesifik, tentu kita tau beberapa contoh kasus perampasan lahan oleh perusahaan, dimana bapak-bapak di komunitas memberi persetujuan kepada perusahaan untuk beroperasi tanpa meminta pendapat perempuan adat. Padahal perempuan adat memangku pengetahuan mengenai pentingnya wilayah adat dan bagaimana mengelola dan melestarikan wilayah adat. Apakah dalam kasus-kasus seperti ini FPIC dikatakan sudah terpenuhi?
Di tingkat internasional sendiri, perumusan standar seteknis ini belum selesai. FPIC sebagai prinsip memang sudah dilindungi oleh berbagai dokumen internasional, yang paling sering disebut adalah Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Tapi penjabaran prinsip tersebut belum secara jelas menjawab masalah-masalah di atas.
Tidak Semuanya Masih Abu-Abu, Ada Yang Sudah Pasti Melanggar.
Kalau ada buzzer politik yang membaca tulisan ini, kalau ada, semoga tidak buru-buru berkesimpulan “tidak perlu berisik menuntut FPIC kalau secara konsep saja FPIC belum dirumuskan dengan jelas”. Seperti semua diskursus tentang hak asasi manusia, unsur-unsur dan indikator pemenuhannya selalu berkembang, ke arah yang semoga lebih baik.
Hanya karena indikator pelanggaran suatu hak terus berkembang, tidak menjadikan pelanggaran yang sudah jelas-jelas, menjadi bukan pelanggaran. Hanya karena definisi ill-treatment terus berkembang, kita semua yakin kekerasan oleh polisi terhadap massa aksi termasuk ill-treatment. Hanya karena kita masih bertanya-tanya apakah Joe Biden dan Kamala Harris akan menjadi pemimpin yang baik, kita semua yakin Donald Trump bukan presiden yang baik. Dan seterusnya, dan seterusnya.
Bagaimana melibatkan masyarakat adat dalam penyusunan undang-undang memang belum ada standar baku-nya. Tapi yang sudah jelas adalah: tidak melibatkan masyarakat adat sama sekali, seperti dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, jelas-jelas melanggar FPIC.
Selain itu, satu lagi yang sudah jelas: dalam FPIC, persetujuan harus diberikan oleh masyarakat adat sendiri; bukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pendamping. Peran LSM memang bermanfaat misalnya untuk mengadakan penelitian tentang situasi masyarakat adat, membantu masyarakat adat menempuh jalur advokasi tertentu, atau membuat pendapat hukum contohnya amicus brief ini. Tapi tentu kita perlu mengingatkan pemerintah berkali-kali bahwa FPIC mensyaratkan masyarakat adat sendirilah yang berkuasa memberi pendapat dan persetujuan atas rancangan suatu kebijakan. Nanti kita cerita tentang Arundhati Roy dan tulisannya soal LSM-isasi perlawanan. Hari ini kita cukup mengingatkan pemerintah bahwa dalam penyusunan undang-undang ke depan, pemerintah tidak bisa mendalilkan telah memenuhi FPIC hanya karena sudah mengundang beberapa perwakilan LSM untuk FGD seharian dijeda coffee break dan ishoma. Karena bukan hanya anggota DPR yang tinggal, berkantor, dan wara wiri di Jakarta; anak LSM juga.
—
1 Emil Ola Kleden, “Urgensi Kejelasan Unit Sosial dalam Pelaksanaan Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)”, Prosiding Simposium Masyarakat Adat: Masyarakat Adat Sebagai Subjek Hukum, (Jakarta: Perkumpulan HuMa dan Epistema Institute, 2014), hal. 233-237.
Format pdf silahkan unduh di sini.
Publikasi lainnya dapat diakses di portal publikasi HuMa.


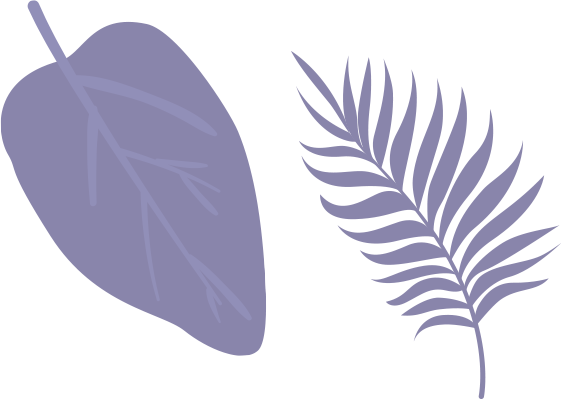
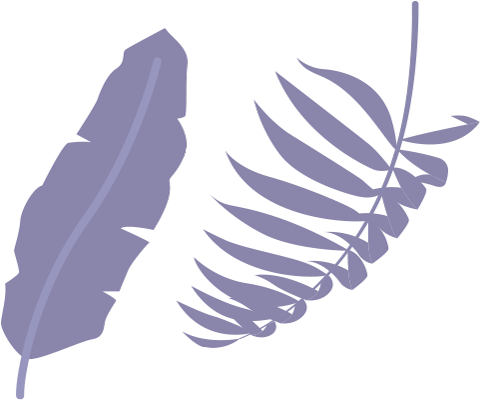
0 Komentar
Tinggalkan Balasan