27 Desember 2011
Mc: Selamat pagi, selamat datang, para pembicara dalam diskusi “Kembalinya TAP MPR ke dalam Tata Urutan Perundang-Undangan RI dan Konsekuensinya Terhadap Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir.
Dalam kerangka acuan yang diberikan panitia, acara ini bertujuan untuk Melakukan refleksi terhadap implementasi TAP MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Mengetahui konsekuensi penempatan kembali TAP MPR dalam tata urutan perundang-undangan terhadap TAP MPR No. IX tahun 2001.
Saya akan sampaikan susunan acara sampai siang. Pembukaan disampaikan oleh direktur HuMa, dilanjutkan dengan presentasi data konflik yang disampaikan oleh Widiyanto dari HuMa. Setelah itu, , kita diskusi publik refleksi perjalanan TAP MPR no. IX Tahun 2001 dengan narasumber Bapak Yuliandri dari Universitas Andalas, Bapak Budiman Sudjatmiko, dan Noer Fauzi. Untuk mempersingkat waktu, Saya persilakan kepada Bapak Andiko untuk memberi sambutan. Kepada Bapak Diko, Saya persilakan.
Pembukaan
Andiko St. Mancayo: Assalamu’alaikum. Mungkin 3 minggu terakhir kita dengar berita tentang pelbagai konflik. Itu hal biasa yang terjadi di Indonesia. Hanya, kebetulan, diliput media. Selama 5 tahun terakhir, desa-desa mulai berguguran dengan cepat. Itu berbuah konflik. Ada transformasi paksa dan tanpa skenario untuk desa-desa di beberapa pulau di Indonesia. Dalam peta eksploitasi, Jawa sudah masa lalu. Sumatera sudah seperti orang tua yang mengurus sakit pinggang dsb. Maka, itu bukan konflik hari ini. Tapi, itu puncak dari konflik yang telah berlangsung beberapa tahun. Sekarang, ekalasi eksploitasi, konflik bergeser ke Kalimantan dan Papua di masa depan.
Sebenarnya, Kita sudah sadar sejak 2001. Ada point penting di TAP MPR ini, pernyataan politik bangsa yang menyatakan bahwa Indonesia telah gagal mengelola sumber daya alam sehingga berbuah kerusakan lingkungan dan konflik. Untuk itu diperlukan satu langkah penting, perlu reformasi agraria dan sumber daya alam. Tapi, kemudian TAP ini tenggelam dalam konstilasi politik dan banyak sekali perdebatan. Tapi, dengan terbitnya UU no. 12/2011 tentang Hirarki Perundangan, sepertinya ada titik cerah yang bisa lagi kita gunakan untuk bicara TAP ini.
Dalam posisi ini, HuMa dalam 2 tahun mencoba mempertahankan TAP ini -paling tidak- secara substansi dibicarakan. Kita sudah bicara dengan DPD, karena waktu itu DPR tidak berpikir hal begini. Sepertinya, ini terlalu berat untuk DPR. DPD membuka pintu, menggulirkan berbagai diskusi yang melibatkan nama DPD. Sehingga, kita dapat peluang ketika TAP ini dicantumkan menjadi sumber hukum di Indonesia. Dalam konteks itu, harusnya kita bisa mentransformasikan konflik yang muncul di media sebagai energi untuk mengimpelementasikan TAP ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan agraria dan sumber daya alam di Indonesia.
Kita tidak berharap konflik-konflik ini diselesaikan secara politis sebagaimana biasanya. Itu hanya menjadi energi ketegangan eksekutif dan legislatis. Kita ini sesuatu yang lebih. Sehingga, Kita berharap kehadiran Pak Budiman di sini bisa mewacanakan ini di lingkungan legislatif. Diskusi ini mungkin diskusi awal yang harapannya ini bisa bergulir di depan. Dan, karena itulah diskusi ini dibuat. Kami mengundang banyak orang. Saya belum tahu kenapa mereka tidak datang, mungkin cuti akhir tahun. Untuk itu mari kita dengar paparan beberapa narasumber, mungkin bisa membuat sesuatu yang lebih baik di tahun depan. Dengan demikian, selamat diskusi. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Mc: terima kasih kepada Bapak Andiko selaku direktur Perkumpulan HuMa. selanjutnya, presentasi data konflik oleh Bapak Widiyanto yang dikumpulkan dari beberapa wilayah. Kepada Bapak Widiyanto, Kami persilakan.
Presentasi Data Konflik
Widiyanto [HuMa]: Assalamu’alaikum. Tadi Andiko menjelaskan perjalanan konflik. Sekarang, giliran Saya mempresentasikan pendokumentasian konflik itu sendiri.
Di HuMa ada sistem pendokumentasian yang selama beberapa tahun dikembangkan HuMa dan mitranya untuk mendokumentasikan konflik lahan, sumber daya alam, di Indonesia. Saat ini, HuMa bersama sekitar 5-6 mitra, ada Kibar di Padang, LBH Semarang, Palopo di Sulawesi Selatan, Bantayah-Sulawesi Tengah, di Pontianak ada LBBT. HuMa Win ini sebagai alat advokasi atau setidaknya dokumentasi untuk HuMa dan mitra-mitranya untuk mendata dan mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan tenurial.
Dalam sistem HuMaWin ini ada beberapa hal yang bisa didokumentasikan: (1) para pihak yang terlibat, bisa masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan negara, dengan taman nasional, KemenHut, atau sebaliknya; Kemudian, alas hak masing-masing pihak; kronologi konflik, ada satu sistematika yang bisa mendokumentasikan catatan-catatan peristiwa di dalam konflik itu sendiri; Kami sedang mengembangkan item terakhir, Kami berpikir perlu ada site pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik seperti kriminalisasi, pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa dll.
Sampai Desember 2011, kami mencatat setidaknya ada, 2.759.254 hektar lahan yang menjadi areal sengketa di 4 sektor dalam 110 kasus, sektor Pertanahan, perkebunan, pertambangan, kehutanan. Kita lihat sektor perkebunan menjadi sektor yang paling luas areal sengketanya. Kemudian, kehutanan, pertambangan, pertanahan. Ini tidak mencerminkan semua kasus yang terjadi di Indonesia. Tapi, ini data yang kami punya. Data pertambangan sedikit yang didokumentasikan karena pertimbangan faktor teknis. Meskipun sedikit, dampak ekskalasi pertambangan sangat besar dan Saya kira ke depan pasti akan bertambah.
Dari konflik pertanahan, kita bis melihat ada 3 aktor atau pelaku utama yang terlibat: perusahaan dalam hal ini swasta, pemerintah, dan masyarakat. Besar kecilnya ini mencerminkan dominasi aktor yang terlibat. Sementara di sektor perkebunan, masih tetap didominasi oleh perusahaan sebagai pelaku utama. Kita melihat bahwa masyarakat lokal, petani penggarap, dan masyarakat adat terlibat tapi posisinya beda dengan perusahaan, karena secara politik dan sumber daya mereka tidak seekspesisf perusahaan. Dari data tersebut, menunjukkan perusahaan paling sering terlibat dalam konflik perkebunan dan –dengan catatan- selalu menjadi pelaku utama. Ini yang menjadi tugas ke depan supaya ada semacam audit perijinan atau lainnya untuk solusi.
Lainnya, dari sektor kehutanan, ini menunjukkan fakta yang menarik, bahwa Perhutani tinggi keterlibatannya dalam konflik. Ini menjadi catatan juga. Ini merupakan cermin atau gambaran situasi konflik sumber daya yang berhasil kami rekam dan presentasikan. Terima kasih. jika ada informasi, silakan menghubungi Kami. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Mc: terima kasih, Bapak Widiyanto dari HuMa. Selanjutnya, diskusi publik refleksi perjalanan TAP MPR No.9 Tahun 2001 yang dimoderatori Bapak Asep Yunan Firdaus. Selanjutnya, sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Asep. Kami persilakan.
Diskusi publik refleksi
Asep Yunan Firdaus [moderator]: selamat pagi, Assalamu’alaikum Wr. Wb. salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk HuMa yang memberi kesempatan kepada Saya untuk memoderatori diskusi pagi ini sampai siang nanti. Sebelumnya Saya minta semua narasumber untuk menempati posisi di depan. Budiman, Noer Fauzi dan Prof. Yuliandri, Kami persilakan.
Senang semua narasumber yang kita harapkan sudah hadir dan ada di depan kita semua. Kita punya waktu sampai 12.30. Jadi, ada waktu sekitar dua setengah jam. Nanti, kita bagi-bagi ke semua narasumber untuk menyampaikan materinya secara precise, topik krusial dan pembahasannya. Sehingga, pada sesi tanya jawab kita bisa lebih dalam.
Tadi sempat disinggung oleh direktur HuMa, bahwa saat ini ada meomentum UU 12/2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya, dia menetapkan kembali TAP MPR menjadi bagian dari jenis peraturan perundangan. Detailnya, nanti Prof. Yuliandri akan memberikan perspektif aspek-aspek positif keberadaan tap MPR dalam tata negaraan kita. Dalam penjelasan UU 12/2011 ini, “Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, ….” Ini memberikan maksud bahwa semua ketetapan MPR sampai 2002, yang telah -salah satunya yang telah ditetapkan oleh TAP MPR 1/2003 masih berlaku, termasuk TAP MPR no. IX Tahun 2001. Nanti, kita ingin tahu, sebenarnya tafsir otentik dari DPR, sebenarnya maunya apa. Kita tahu sudah 10 tahun, TAP ini ada dan tiada. Ada secara formal tapi tidak ada secara pelaksanaan.
Kita ingat saat seminar nasional di DPD, seperti yang disinggung direktur HuMa, 7 kementerian kita undang untuk menyampaikan refleksikan pelaksanaan TAP ini. kalau boleh Saya katakan, Mereka seperti tidak mengerti maksud dari TAP MPR ini. Misalnya, Dirjen ESDM menjelaskan tentang UU migas, UU mineral. Dia tidak membayangkan bahwa TAP itu memberikan mandat penbaharuan. Kemudian, Kementerian Kehutanan menjelaskan tentang penanaman pohon. Jelas, dua sektor dari tujuh Kementerian yang kita undang, tidak mengerti maksud dari TAP MPR tersebut. Tapi, ketidakmengertian ini juga ada sebabnya. Kita melihat DPR juga minim sekali untuk melakukan pengawasan. Karena, TAP MPR IX mengatakan DPR bersama Presiden bertugas untuk mengawal. Bahkan, mencabut peraturan yang tidak sesuai. Ini tugas legislasi. Presiden diminta membuat laporan setiap tahun kepada DPR. Tapi setidaknya sampai sekarang, tidak ada satupun event yang merefleksikan dijalankannya tugas TAP MPR itu.
Kemudian, kita tahu sekarang konflik sumber daya alam dan agraria mencuat. Walaupun, sebenarnya kasus ini bukan terjadi sekarang, tapi cerita bertahun-tahun lalu. Kita tahu, isu ini menguat karena media dan jumlah korban, serta besarnya kerusakan sehingga menarik untuk dikaji. Terlepas dari itu, momentum ini mestinya bisa dimanfaatkan untuk mengangkat kembali isu TAP MPR menjadi isu publik, walaupun sebenarnya sudah produk publik. Tapi, tidak menjadi isu karena tidak ada yang mengangkat isu ini. Seminar ini adalah salah satu saja cara untuk mengingatkan kembali dan mendorong topik ini menjadi topik bersama di ruang publik.
Nanti, ketiga narasumber sesuai posisi masing-masing diberi kesempatan menyampaikan pemikirannya. Pertama, Prof Yuliandri akan menyampaikan keberadaan TAP MPR IX/2001 berkaitan dengan UU 12/2011. Kemudian, Bang Oji yang akan menyampaikan topik birokrasi agraria sebagai pewujud keadilan sosial, refleksi perjalanan “Reforma Agraria” 2005-2009. Kemudian yang ketiga, Budiman Sujatmiko yang menyampaikan topik implementasi TAP MPR no. IX/2001 dalam ranah legislasi. Saya kira cukup lengkap dibahas dari berbagai aspek. Nanti, kita akan punya sesi tanya jawab kurang lebih satu sampai satu setengah jam setelah narasumber menyampaikan materinya. Karena materi sudah digandakan, tentu nanti narasumber bisa memberikan rangkuman sehingga waktu efektif untuk digunakan berdialog.
Pertama, silakan Prof. Yuliandri. Sebelumnya, Saya bacakan dulu CV-nya. Sekarang, Profesor Yuliandri adalah dekan di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Beliau lahir di Sungai Tarak, 18 Juni 62. Kabupaten Tanah Datar. Alamat, Kampus Unan. Pendidikan terakhir, S3 ilmu hukum di Unair. Silakan.
Apakah Lahirnya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan Membuat tap MPR No. IX Tahun 2001 Tetap Berlaku?
Prof. Yuliandri [Univ. Andalas Padang]: Assalamu’alaikum Wr. Wb. Tanpa mengurangi rasa hormat ke mas Noer Fauzi dan Budiman, serta adinda Asep yang kadang-kadang sering jumpa dimana-mana, dan kepada semua hadirin dan peserta diskusi publik hari ini. Sudah tentu, bagaimana pun, Kita senantiasi memberikan puji syukur kepada Tuhan bisa hadir di sini memenuhi undangan HuMa dengan agenda pokok diskusi publik tentang bagaimana TAP MPR no. IX tahun 2001 dikaitkan dengan berlakunya UU no. 12 tahun 2011.
Bapak Ibu, pertama, Saya ingin sampaikan bahwa apa yang dimintakan ke Saya adalah khusus membahas bagaimana posisi TAP MPR no. 9 tahun 2001 dengan berlakunya UU 12/2011. Saya minta waktu juga. Karena terlepas dari inti kajian kita, Saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang undang-undang ini dan bagaimana penempatan TAP itu. kebetulan, Budiman ada di sini sehingga menjadi kesempatan kita untuk menyampaikan kontribusi. Pertama, UU no. 12 ini boleh dikatakan termasuk UU yang tidak banyak menjadi fokus atau diskursus di publik ketika muncul. Walaupun, Kita tahu UU ini termasuk UU yang mengganti UU no. 10/2004. Sebelum kita melihat atau menganalisis TAP no. IX/2001, Saya ingin memberikan gambaran bagaimana kita memahami UU 12. Ini sebagai pintu masuk, bahwa UU ini hanya sebagai kamuflase atau tidak.
Pertama, Saya melihat, sebetulnya dalam UU ini banyak sekali isu krusial yang bisa kita lihat. Pertama, kalau kita baca secara utuh UU ini, dalam pertimbangannya ada alasan yang -kalau boleh Saya katakan- mengeneralisir. Ada pertimbangnan yang eksplisit mengatakan UU lama tidak sesuai lagi. Kedua, dalam kaitan ini, kita bisa lihat misalnya dalam konsideran huruf c UU tersebut, kita lihat “…masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan…;”. Kemudian, kenapa mengganti menjadi pilihan? ini termasuk bagian yang Saya pikir konsisten. Kalau kita mau konsisten, Pasal 22 UU ini mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan lain, termasuk tentang hirarki. Kemudian, kalau pilihannya ganti, tentu pertanyaan kita adalah- apakah -biasanya- sebelum kita mengganti suatu UU ada kajian-kajian yang kalau diprosentasi belum mencapai 60% maka pilihannya adalah mengubah. Ini tidak, mengganti.
Berikutnya, Saya melihat dari materi UU, banyak yang diatur. Khusus berkaitan dengan hirarki, UU 12/2001 mengatur kembali jenis hirarki perundang-undangan sesuai Pasal 7 ayat 1. Ada beberapa hal yang bisa dijelaskan. Pertama, tap MPR menjadi bagian dari hirarki. Tentu, dari segi substansi tidak problem. Tapi, dari segi hirarki penamaan bisa dikaji. Kedua, membeda dalam hirarki perda propinsi dan perda kabupaten/kota. Ini mungkin bisa menjadi pintu dalam konteks pengaturan sumber daya alam. Pertanyaannya apakah problem ketika perda propinsi/kabupaten tidak mengacu pada perda propinsi? Apalagi, dikaitkan dengan titik berat ekonomi. Sekarang, kita masih ambigu apakah di Propinsi atau kabupaten, termasuk dalam mengatur sumber daya alam. Maka, ini juga kajian yang nanti bisa teliti bila membandingkan antara perda Propinsi dan perda kabupaten/kota. Ketiga, diakuinya keberadaan jenis perundangan lain. Selain yang dalam hirakir ini, yang sebelumnya dicantumkan dalam penjelasan. Sementara, dalam UU ini dimasukkan dalam Pasal 7 ayat 3 –kalau tidak salah.
Kalau kita rujuk, beberapa landasan pikiran yang dijadikan dasar, memang yang pertama itu betul, hirarki itu penting. kenapa Saya katakan penting? Karena, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus punya landasan yuridis yang jelas, titik tolak atau connecting. Tapi, tidak setiap peraturan perundangan bisa dijadikan landasan yuridis. karena, hanya peraturan perundang-undangan sederajat atau lebih tinggi yang bisa dijadikan landasan yuridis. Kemudian, dalam problem hukum yang terjadi, bagaimana mengaitkan, ada asas hukum, seperti lex posterior derogate priori, dan lex specialis derogate lex generali, serta lex superior derogat lex inferior, dan sebagainya. Ini problem kita hari ini. Kasusnya banyak di sumber daya alam. Kita tidak bisa meng-connecting-kan antara satu UU, baik yang mengatur secara umum maupun secara khusus yang berkaitan dengan sumber daya alam. Contohnya, bagaimana menghubungkan UU Lingkungan dengan UU Kehutanan, UU Pertambangan? Mana yang umum, mana yang khusus? ada kasus di Mentawai yang mencoba melihat illegal logging dikaitkan dengan korupsi. Ini problem hukum yang ketika kita bicara di tataran legislasi akan sulit sekali meng-connecting-kannya. Maka, ini juga merupakan kritik terhadap UU ini yang tidak menjelaskan secara utuh bagaimana prinsip keterkaitan itu. Sehingga, kemudian problem itu akan timbul kalau kita mensinkronkan dalam kasus tertentu tidak bisa kita masuk ke sini.
Kemudian, soal ketetapan. Saya minta maaf dulu kalau di segi tataran perundangan-undangannya, Saya akan lihat dulu isinya, baru kemudian ketetapannya. Ketentuan Pasal 7 yang memasukkan TAP itu sebagai salah satu jenis hirarki perundang-undangan, yang sebelumnya sudah dihilangkan, dapat dikatakan ada juga tendensius berlebihan. Kenapa Saya katakan demikian? Apa alasan TAP ini dimasukkan? Adalah untuk menjemput, memberikan keberadaan TAP no. 1 tahun 2003 khususnya. kenapa? karena, di sana ada 3 kategori perintah. (1) TAP itu memberikan evaluasi terhadap tap-tap yang memang setelah berlaku tidak lagi valid. Setelah dia berlaku, sesuai kekuatan hukum yang diaturnya, selesai. (2) Ada TAP yang tetap berlaku. Kategorinya, setelah ada ketentuan lebih lanjut, yang memberikan pengaturan peraturan lebih lanjut di UU maupun legislasi, dia selesai. Kemudian, (3) TAP yang berkaitan dengan menentukan keberadaan TAP sebelumnya. itu hanya 60 sampai dengan 2000. Pertanyaannya, kenapa kemudian, kalau hanya TAP yang kita akomodasi, kita tanggung? Ada ketentuan lain yang sebenarnya juga berlaku hari ini, tapi produk Belanda seperti ordonansi. Kenapa? Karena banyak ordonansi yang sampai hari ini berlaku, hampir 200-an, kalau boleh dikatakan, ada yang belum diutak atik. Ordonansi itu selevel dengan undang-undang. Contohnya, Ordonansi, UU gangguan. Itu berkaitan dengan periijinan, yang masih berubah-ubah. Ordonansi itu tahun 20-an. Kenapa itu tidak kita tampung? Kalau kita mau konsisten? Kenapa hanya TAP saja, sementara ordonansi tidak dimasukkan? itu perlu disampaikan. Kenapa Saya sampaikan itu? Sebenarnya, di tataran konstitusi sudah jelas dan sampai sekarang masih berlaku. Misalnya, kita baca Pasal 1 perubahan keempat UUD 1945, dikatakan MPR memang ditugaskan untuk melakukan peninjauan. Tapi, dalam arti ini, bila MPR melakukan peninjauan, kalau boleh Saya katakan, berarti memberikan keberadaan. Problem bagi kita, sukar kita memilah. Karena tidak semua TAP MPR itu memberi pengaturan. Substansinya belum tentu eksplisit. Ini kritik kita terhadap –kenapa kemudian muncul kembali TAP? Dikaitkan lagi nanti dengan prinsip-prinsip bagaimana suatu aturan hukum berlaku. Kedua, UUD 1945 sebetulnya, baik sebelum maupun sesudah perubahan, tidak menyebut secara tugas bentuk hukum perundang-undangan. Karena, secara kerangka teori juga ada –halaman 4 makalah. Itu point Saya.
Berikutnya adalah khusus TAP no. IX/2001. pertama, berlakunya UU no. 12 tahun 2011 berkaitan dengan TAP ini, secara formal dapat dikatakan tentu diperkuat. Itu jelas. Karena memang dalam penjelasan Pasal 7, yang dimaksud dengan TAP dalam UU itu adalah ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 dan Pasal 4 TAP no. I tahun 2003 tentang peninjauan kembali. Formal ok, dia memperkuat. Saya katakan tadi, ini sebenarnya sudah double. Tapi, substansinya, mesti kita pertegas. Kenapa? karena, perlu ada pemaknaan yang bisa dijadikan pegangan. Kalau kita baca TAP no. IX/2001, secara eksplisit merumuskan 2 hal: kebijakan tentang pembaharuan agraria dan pembaharuan sumber daya alam. (2) ada perintah kepada presiden dan DPR dan kemudian wajib melaporkan. Seperti tadi sudah disampaikan Linda, itu adalah kewajiban kita. Tapi, tidak semua begitu atau belum pernah mungkin secara eksplisit, presiden memberikan laporan berkaitan dengan penetapan. Maka, menurut Saya, inilah pintu masuk kita hari ini untuk lebih memperkuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam secara substansi, terlepas dari berbagai berbagai problem hukum dari sistem yang dibangun oleh UU no. 12/2011. karena, problem hukum hari ini, menurut Saya, lebih banyak – kita lihat sampai TAP no. IX/2001 merupakan jembatan yang -menurut Saya- inilah yang harus selalu jadi pegangan. Kita ambil contoh, Mana yang lebih dahulu, UU no. 12/2011 dikaitkan dengan yang kemarin disahkan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nanti kita lihat, secara teknis perundang-undangan, naskah UU itu menyebutkan tentang TAP MPR atau tidak? Kalau menyebutkan, berarti role-nya ada, paling tidak mencantumkan TAP no. IX/2001. kalau tidak ada, berarti tidak ada artinya. Ini satu uji formil terhadap mengacunya. Coba nanti lihat. Saya tidak tahu, Saya kemarin dapat draft terakhir. Coba lihat saja. Saya hanya menganalisis itu saja. Kalau itu tidak dicantumkan secara eksplisit, itu tidak ada artinya. UU ini mengacunya ke mana? karena di dalam Pasal 5 atau mungkin Pasal 6 TAP itu menyebutkan pengaturan dalam hal pertanahan mesti diharmonisasikan. Ini contoh yang paling terakhir. Di sini tidak dimasukkan, tapi Saya ingat semalam RUU tentang Pengadaan Tanah itu nanti apakah sudah mengacu pada TAP ini, atau minimal memasukkan itu. kalau sudah, itu bisa menjadi pintu masuk, apakah ini yang dimaknai oleh TAP no. IX tahun 2001 itu.
Berikutnya, sebetulnya kewajiban kita hari ini untuk lebih mengelaborasi substansi-substansi yang ada dalam TAP itu menjadi ukuran bagi kita untuk mendorong ke depan, bagaimana kebijakan pemerintah. kalau ini tidak dilakukan, percuma. Sumber daya alam hari ini akan bergerak atau stagnan atau orientasinya kemana. Saya tidak melakukan kajian utuh. Tapi, mesti jelas, karena itu menjadi ukuran. Kewajiban kita, secara khusus tentu ini. Contohnya, UU mana yang nanti bisa kita katakan bahwa yang ulang yang dilakukan terhadap pelbagai aktor natural yang berkaitan dengan agraria dalam kebijakan antar sektor? HuMa melakukan kajian secara substansi. Tapi, menunjuk secara tegas mengatur mana dan di level mana. karena problem kita dalam pengaturan sekarang, ok di level UU sudah, tapi dia akan terdistorsi ketika dibuat aturan berikutnya. Misalnya, PP atau di menteri. Itulah problem kita. itu banyak terjadi di UU sumber daya. itu satu.
Kedua, bagi kita di daerah, ini tentu jadi catatan. Contoh, Pemda adalah pintu masuk terhadap semua kebijakan daerah walaupun hanya mengatur tata atau penyelenggara pemerintah. Indikasinya, itu kepada semua. Pertanyaan kita adalah apakah semua UU yang mengatur sumber daya alam itu sudah menjadikan UU itu sebagaian bagian yang mesti dikoneksikan. Kalau itu tidak dilakukan, berarti otomatis, -kalau boleh Saya katakan- kasihan juga, tidak akan tercipta connecting antar sektor. Yang jelas, formal, bagi kita yang penggiat sumber daya alam, UU ini tentu dapat kita katakan lebih memperkuat. Sebenarnya, TAP ini sudah memperkuat, tinggal UU-nya. Kalau ini sudah masuk di level peraturan maka yang harus kita waspadai, apakah dia benar-benar menjadi ukuran kita. Kalau tidak, tentu ini menjadi tidak bermakna. Catatan Saya adalah kebeijakan legislasi ke depan mesti jelas dan menguraikan secara rinci apa makna yang diatur oleh TAP no. IX tahun 2001. kalau itu tidak dilakukan, walaupun masuk dalam hirarki itu tidak ada artinya. Itu bahan awal untuk diskusi. Terima kasih. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Moderator: terima kasih Prof. Yuliandri. Dari yang disampaikan, setidaknya tantangan untuk kita: formulasi ok, hirarki jelas menempatkan tap MPR sebagai satu jenis hirarki, normatifnya sudah jelas, formulasinya memperkuat. Tapi, tantangannya apakah ini bisa diimpelementasikan dengan sejumlah problematika tadi. Saya berpikir, jangan sampai ketika TAP MPR ini diterbitkan tahun 2001 yang kemudian faktanya tidak bisa dijalankan atau setidaknya dihambat untuk dijalankan. Lalu, ketika ini diperkuat, sama. TAP ini ada sebelum UU 10/2004. artinya, dia mengacu pada produk hirarki yang sebelumnya, tahun 2000. Artinya, di situ TAP jelas, tapi juga tidak bisa berjalan. ditambah munculnya UU 10/2004 yang membuat semakin tidak berjalan lagi. lalu, ada yang baru yang menempatakan itu kembali.
Tadi Profesor menyampaikan, dengan problematika yang ada, ada kemungkinan juga ini tidak berjalan. akhirnya, problem tidak dideliverasi. Salah satu yang menjadi contoh terkini, apakah UU PTUP, pengambilan tanah untuk kepentingan umum yang hadir setelah UU 12/2011 ini sudah menggunakan Tap MPR ini sebagai konsideran. Itu rumus gampang saja. Mestinya masuk, karena ini urusannya dengan agraria. Nanti kita periksa. Mungkin, nanti mas Budiman bisa menyampaikan informasi atau kita periksa di dokumen sidang paripurna kemarin. Nanti, teman-teman bisa berdasarkan informasi yang ada memberi komentar.
Saya juga menangkap ada semacam, setelah terbitnya UU 12/2011, bolanya ada di DPR. Karena, dia yang harus menjalankan TAP IX/2001, dengan menetapkan kembali dalam hirarki. Bolanya ada di DPR, misalnya mengagendakan bagaimana supaya laporan presiden itu ada sidang tahunan. Kemudian, Saya sempat bisik-bisik, uji materiil. Kelihatannya sudah ada inisiatif untuk uji materi. Tapi, mungkin uji formil menjadi penting. mestinya, kan bisa uji formil itu. tidak ada larangan di MK untuk uji formil. Misalnya, seperti UU PTUP kalau tidak mencantumkan TAP MPR di uji formil seharusnya batal karena TAP MPR sudah ada di atas UU. Ini nanti menjadi tantangan ke depan. Nanti, mungkin mas Budiman dalam dialog bisa mengelaborasi lebih jauh.
Kedua, kita minta Bang Oji dulu untuk menyampaikan makalahnya yang berjudul “Birokrasi agraria sebagai pewujud keadilan sosial: refleksi perjalanan “Reforma Agraria” 2005-2009”. Sekilas Saya sampaikan CV dari Bang Oji. Sekarang, statusnya adalah sebagai dosen di departemen community development and community of human ecology IPD dan peneliti di Science Insitute. Lainnya, susah disebutkan. Tahun 2011 Beliau mendapatkan PhD enviromental science, policy and management dari Universitas Berkeley, USA. Saya kira, itu secara singkat profil dari Bang Oji. Cukup tulisan, jurnal, makalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang kalau butuh bisa menghubungi langsung yang bersangkutan. Saya kira, kita minta, waktunya 10 menit untuk menyampaikan materi.
Refleksi Pembaruan Agraria Pasca Reformasi
Noer Fauzi Rachman, PhD [HuMa]: terima kasih atas pengantar yang diberikan. Pagi ini, Saya akan secara cepat menyajikan review bagaimana land reform bangkit kembali sebagai satu bagian dari kebijakan nasional. Saya akan bagi 4 periodisasi dari uraian Saya ini.
Mari kita lihat yang pertama. Tahun 67 itu suatu momentum yang sangat penting dimana rejim otoritarian Soeharto mengganti secara drastis agraria nasional, dari sosialisme Indonesia ke kapitalisme. Saya ingin mengatakan, selama 20 tahun, ada satu jeda dari proses perjalanan kolonialisme. Tahun 1967, balik menjadi neo-kolonialisme. Tapi, jeda 20 tahun ini punya arti penting karena di situ ada pembentukan negara bangsa yang didalamnya ada sedimen-sedimen nasionalisme sebagai paham yang revolusioner. Ini yang sering dilupakan orang. Nasionalisme itu adalah paham yang revolusioner, bukan hanya membentuk negara bangsa tapi membentuk mereka dalam rangka menciptakan keadilan nasional menghadapi kapitalisme kolonial sejak 1600-an sampai 1945. Tahun 67, sebagian literatur menyebut itu sebagai rejim kontra revolusi terhadap revolusi 45 yang meletakkan negara bangsa sebagai kekuatan untuk menandingi kolonialisme. Itu sangat jelas pada politik agraria. Itu dibalikkan sedemikian rupa sehingga kita lihat, proses ekstraksi kekayaan alam melalui UU Pertambangan, UU Kehutanan, yang kemudian menjadi dasar pembentukan kapitalisme baru yang sangat ekstraktif sifatnya.
Ada banyak rentetan kebijakan setelah itu, ada revolusi hijau sebagai upaya untuk meningkatkan produksi beras agar masyarakat relatif mendapat makanan setelah dumping besar-besaran melalui –yang disebut sebagai- supply makanan dari Amerika dengan gandum dan lain-lain. Kita produksi beras dengan hutang luar negeri. IMF punya paket pertama-tama pada pemerintah Indonesia untuk memproduksi beras. Bank Dunia masuk, kemudian revolusi hijau menjadi tak terpisahkan dari pembangunan.
Kemudian, kebijakan agraria berbalik menjadi kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan. Setelah periode land reform, tahun 1962-1965, dibekukan, maka yang terjadi adalah yang dikenal waktu itu adalah pembebasan tanah. ajaib! Pembebasan tanah. dibebaskannya ikatan penduduk atas tanah dan dibebaskannya penduduk menjadi tenaga kerja yang sebagian besar terikat pada pertanian. Proses-proses pengadaan tanah untuk proyek pemerintah melalui permendagri 15/75 dan 2/76. Bagi yang ingat, 15/75 ini adalah permendagri untuk pengadaan tanah untuk proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. sedangkan, permendagri no. 2 tahun 76 adalah penggunaan permendagri 15/75 untuk kepentingan swasta. Jadi, jelas sekali, betapa sebenarnya fasilitas publik dan infrastruktur negara digunakan untuk pengembangan kapitalisme dalam jangka yang lebih besar. Akibatnya, praktek-praktek dalam pengadaan proyek-proyek seperti pembangunan kawasan industri, pembangunan waduk, pembangunan jalan selalu dipakai cara-cara membebaskan yang menggunakan kekerasan oleh aparatur birokrasi. Akibatnya, kasus tanah meletup di mana-mana.
YLBHI mulai buat laporan penelitian. Saya dan Rahma meneliti bagaimana laporan Hak Asasi Manusia (HAM) YLBHI mulai ada tahun 78-an sampai 2001 ada kasus tanah. Kemudian, aktifis mulai bekerja: Saya di Bandung, Budiman di Yogyakarta, Dedi di Lampung, teman-teman Sumatera Utara, semua melakukan kegiatan yang relatif sama, yaitu turba –turun ke bawah. Semua menyelidiki kasus-kasus itu, bekerja bersama pimpinan-pimpinan kampung yang tanah penduduknya diambil. Lalu, membuat komite mahasiswa dan mengartikaulasikannya ke kantor pemerintah melalui protes, mobilisasi. Itu mulai menjadi topik pembicaraan. LSM mulai masuk ke dalam sebagai faktor utama dalam membuat studi. Sehingga, tahun 95 studi-studi yang dibuat LSM itu bermuara pada perlunya perubahan politik agraria dan perlunya pemerintah mengadopsi kembali gagasan yang diperluas, diperbaharui dari land reform. Land reform kembali menjadi kata kerja yang dipromosikan dengan berbagai macam cara oleh para aktifis. Land reform kemudian mejd vocabulary gerakan yang nanti pada gilirannya tap MPR no. IX masuk menjadi bagian resmi pemerintah.
Tahun 95, Bank Dunia mulai merancang proses perubahan kebijakan manajemen dan administrasi pertanahan yang pro-pasar. Jadi, ada satu proyek yang namanya Land Administration Project, dimulai tahun 1995, yang dijalankan dengan cara yang sama sekali baru, yang berbeda dengan PP no.10 tahun 61 tentang pendaftaran tanah. dia buat suatu proses pendaftaran tanah melalui cara dimana kantor-kantor tanah pindah ke tempat yang akan disertifikat. Kemudian, pemimpin dari kantor –yang namanya- kantor Ajudikasi berhak menandatangani sertifikatnya. Ribuan sertifikat langsung dibuat dalam 6 bulan di tempat itu. sehingga, proses penggandaan sertifikat terjadi secara cepat. Karena, mereka ingin transaksi tanah tidak melalui intervensi negara melalui pembebasan tanah tapi melalui transaksi atas kepemilikan yang sah. Bankable. Dengan demikian, kalau orang punya sertifikat, sertifikat diagunkan ke bank, bank bisa menyalurkan kreditnya. Sehingga, yang disebut sebagai debt capital bisa hidup dalam perekonomian.
Tahun 1998, kita tahu Soeharto jatuh, kesempatan politik terbuka, tradisi berubah sampai terpilihanya Megawati dan Gus Dur sebagai presiden dan wakil presiden. Saya ingin katakan bahwa 98 itu begitu penting karena di sinilah momentum dimana topik yang hendak kita bicarakan dimungkinkan terjadi, dipromosikannya agenda land reform masuk dalam kebijakan pemerintah. Di pihak lain, Saya mau mengatakan golongan aktifis lain bicara kerusakan lingkungan, karena proses deforestasi, pengadaan kayu melalui perusahaan raksasa. Tahun 78, Dirjen kehutanan dinaikkan menjadi Departemen Kehutanan. Kemudian, dilakukan proses yang disebut sebagai teritorialisasi melalui apa yang mereka katakan tata guna hutan kesepatan (TGHK), ditetapkanlah bahwa seluruh wilayah teritori Indonesia dibagi 2: ada yang non-hutan dan wilayah hutan. Wilayah hutan jumlahnya 126 juta hektar. Di dalam wilayah hutan, mereka berikan konsensi besar-besaran, 64 juta hektar. Jadi, lebih dari 50% ditetapkan sebagai wilayah untuk perusahaan raksasa yang rata-rata ada di dalam 20 pengusaha besar dengan kepemilikan 20 hektar per lahan Perusahaan ini bisa merupakan holding satu sama lain dan tidak ada batas maksimum. Ternyata, satu holding setelah dikalkulasi menguasai 4,6 juta hektar. Proses bagaimana rusaknya hutan mengakibatkan aktifis-aktifis yang kerja di wilayah-wilayah melihat percepatan -1,2 juta hektar per tahun- tegakan kayu di hutan tropis hilang. Ini mengakibatkan deforestasi. Deforestasi mengakibatkan kerusakan ekologi yang nyata. Itu istilah TAP MPR yang nanti akan menjadi suatu hal yang masuk dalam TAP MPR itu selain konflik agraria.
Analisa yang berkembng dari 2 kelompok (kelompok agraria dan aktifis) ini menghasilkan kesepakatan yang sama bahwa perundang-undangan mengenai agraria dan/ sumber daya alam bertentangan satu sama lain dan tumpang tindih. Itu butir 3 dalam TAP MPR. Jadi, point itu masuk bersamaan ke dalam proses MPR sehingga sampai muncul TAP MPR tahun 2001. Ada proses panjang, jatuh bangun, bagaimana ini bisa berhasil masuk ke proses advokasi kebijakan. Dimana, mulai dari 2 kelompok terpisah, kemudian menjadi satu dalam pokja pembaharuan agraria &/ sumber daya alam. Lalu, lebih dari itu, dalam panitia ad hoc terpisah antara TAP MPR pembaharuan agraria dan TAP MPR pengelolaan sumber daya alam. Satu waktu, sebelum disatukan, mereka membuat workshop bersama-sama dan menghasilkan keperluan disatukan. Maka, TAP MPR ini agak janggal, 2 hal disatukan sebenarnya tumpang tindih satu sama lain. ada 3 butir yang diakui dalam TAP MPR tersebut: (1) pembangunan agraria, pengelolaan sumber daya alam selama ini menimbulkan konflik berkepanjangan. (2). pembangunan agraria dan pengelolaan sumber daya alam selama ini menghasilkan kerusakan lingkungan. (3) peraturannya tumpang tindih. Para aktifits mulai kerja di Departemen sektoral: Kehutanan, pertambangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tapi, tiap-tiap tempat itu, birokrasi-birokrasi itu sendiri menyusun agendanya. Seperti, BPN menyusun agenda RUU PA. Padahal, dalam gagasan awalnya, UU PA adalah rujukan resmi dan satu-satunya yang memandatkan land reform dijalankan. Tapi kok begitu jadi agenda reformasi di BPN, dia mengagendakan revisi UU PA yang bukan amandemen, tapi diganti keseluruhnya dengan perundang-undangan baru. Maka, terjadi penolakan besar-besaran, sedemikian rupa, bergelombang. Krnt erjadi penolakan, draft baru, ditolak, draft baru, ada 3 draft untuk mengganti UU PA. Di departemen Kehutanan, mereka revisi UU 41 tahun 99. dengan datangnya TAP MPR, mereka enggan, mereka tahu TAP MPR akan menganggu eksistensi UU 41 ini. mereka tidak melakukan apapun terhadap itu. mereka berusaha memblokade kelompok yang mempromosikan. Kemudian, di dalam Departemen Kehutanan sendiri terbentuk working group tenur yang mempromosikan, mengajak unsur-unsur progressive dalam Departemen Kehutanan untuk memikirkan kepastian penguasaan tanah dari penduduk-penduduk yang ada di dalam 127 juta hektar hutan. Intinya, sekarang sudah diakui 33.000 lebih desa di kawasan hutan dan status hukumnya tidak jelas. Bahwa mereka dikrirminalisasi itu adalah bagian dari pelaksanaan UU 41. Di Departemen Pertambangan juga menolak TAP MPR ini dijalankan. Tidak ada suatu tim di dalam presiden yang membuat koordinasi supaya TAP MPR dapat dijadikan pegangan yang mengevaluasi perundang-undangan yang sektoral dan dan praktek kelembagaan sektoral. Sehingga, sektoralisme ini menjadi problem besar dalam menerapkan ini. Musuhnya adalah sektoralisme. Setiap badan mengembangkan kepentingan sendiri untuk memfasilitasi kepentingan modal berkembang masing-masing, yang pada gilirannya sektoralisme ini makin lama makin menguat. Nanti Saya akan tunjukkan dalam penerapan land reform oleh BPN, betapa sektoralisme menjadi hambatan utama.
Hingga pada Presiden Yudhonoyo terpilih, ada perubahan. Presiden Yudhoyono mengangkat Joyo Winoto sebagai Kepala BPN. Jadi yang Joyo Winoto lakukan adalah mengagendakan reforma agraria, yang Saya sebut birokrasi otoriatrian yang memburu rente. Itu harus diubah menjadi birokrasi yang pro keadilan sosial. Saya tidak pernah bertemu dengan satu pun pejabat pemerintahan yang tegas-tegas menyatakan mengagendakan badan pemerintahannya, departemennya, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti BPN dibawah pimpinan Joyo Winoto. Saya mau mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang bisa berhasil. Nanti Saya tunjukkan kejadiannya bagaimana. Ketika Joyo Winoto mulai, dia sadar bahwa birokrasi ini birokrasi yang pemburu rente. Maka, dia akan melayani modal kemana uang bergerak. Ketika dapat masukan dari badan-badan usaha untuk memberikan konsensi, berupa ijin lokasi, HGU, ada pemasukan resmi dan yang lebih penting adalah pemasukan yang bersifat korupsi. Ini juga berlangsung pada departemen Kehutanan melalui HPH.
Kita tahu bahwa bahwa mengagendakan keadilan sosial dalam kebijakan pertanahan adalah Land reform. Jadi, kekayaan yang terkonsentrasi berupa tanah diredistirbusi. Sekarang, pertanyaannya tanah yang mana yang mau di-redistribusi? Tanah yang diredistribusi adalah tanah yang tergolong dalam 3 kategori: (1) 8,15 juta hektar dari tahan hutan kawasan konversi dibawah jurisdiksi departemen Kehutanan. Angka 8, 15 juta hektar ini adalah ada 26 juta ha yang ditetapkan Departemen Kehutanan adalah wilayahh yang akan dijadikan kawasan non hutan melalui keptuusan menteri. Maka, BPN membuat identifikasi, ada 8,15 juta hektar yang sebagian besar sudah dihuni penduduk. Ini harus diredistribusi, dikeluarkan dari kawasan hutan. Karena di kawasan hutan, definisinya adalah pendudukan di dalam kawasan hutan tidak punya hak atas tanah. Hutan negara adalah hutan yang berdiri di atas tanah negara yang ditunjuk oleh menteri Kehutanan, dan dikukuhan – itu ada proses yang relatif panjang, tapi pada tingkat pertama di departemen Kehutanan. Kalau berada dalam kawasan konservasi, hak penguasaan hutan, atau Hak penguasaan hutan tanaman industri, mereka dapat dengan mudah dikriminalisasi. Kita melihat kasus-kasus konflik agraria di Kehutanan jumlahnya melimpah. Seperti yang secara kronis berlanjut sedemikian rupa pada kasus –salah satunya- kasus Mesuji. Sekarang, diakui 33.000 desa hutan berada di kawasan hutan negara yang statusnya harus diperjelas. (2) berbagai tipe tanah negara yang secara langsung berada di bawah jurisdiksi BPN, 1,1 juta. Banyak tanah yang sudah dinikmati rakyat. Karena sejak jaman Jepang, 1942, perkebunan-perkebunan ini sudah diduduki oleh rakyat. Jepang memaksa Belanda pergi. Kemudian, rakyat didorong untuk menggarap perkebunan itu. lalu, rakyat menikmati. Terus saja berlangsung sampai saat mereka sebagian diusir karena penerapan KMB 1949, dimana ada rehabilitasi perkebunan Belanda, ada nasionalisasi perkebunan. Kemudian, mereka tersingkir. Untuk pertama kalinya, militer kemudian kerja, terutama TNI AD sebagai bagian dari ekonomi produksi.
Konflik-konflik agraria antara petani dan perkebunan berarti berhadapan militer. Karena panglima angkatan perang, dalam proses nasionalisasi itu berwenang untuk menempatkan wakil direktur PTN adalah perwira militer. Pada saat itulah, setiap kantor kodim mempunyai berbagai kategori strategis untuk dilindungi. Setiap petanya, perkebunan diletakkan sebagai strategis. Tahun 67, berkembang berimbas pada pertambangan. Ini yang mengakibatkan para komandan punya semacam kewajiban- karena dianggap sebagai aset negara. padahal, itu aset bisnis. Penggunaan militer –polisi sebagai sarana keamanan- dimulai dari ketetapan dia sebagai wilayah strategi yang harus dilindungi.
Wilayah 1,1 juta hektar adalah wilayah-wilayah yang tidak disingkirkan tapi sudah dinikmati rakyat tapi belum disertifikasi status tanahnya secara legal kepada negara. Karena itu, mereka dengan mudah melakukan sertifikasi. Itulah yang dilakukan sejak 2007-2011. itulah yang disertifikasi.
Kemudian, (3) ada 7,3 juta ha tanah terlantar, yaitu tanah yang digunakan badan usaha secara luas tidak sesuai peruntukannya, baik itu status ijin lokasi, status hak pengelolaan, maupun status hak guna usaha. Dalam paper Saya dijelaskan detailnya, angkanya dan dimana saja itu berada. Saya dapat data dari BPN dimana setiap Propinsi diidentifikasi. Sekarang, dengan peta tanah terlantar yang baru, tahun 2010-2011, akan ada penetapan wilayah-wilayah tanah terlantar. Tahun 2012, mereka punya proyek percontohan, wilayah mana yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar. Dan, dengan PP Reforma Agraria yang akan terbit pada bulan Januari yang akan datang, maka dia akan diredistribusi pada mereka yang menuntut hak atas tanah itu.
Ada mekanisme yang rumit dalam BPN mengenai model redistribusi tanahnya. Intinya, mereka bergeser dari land reform yang sifatnya distribusif menjadi legalisasi tanah. ini yang terjadi. Problemnya, kalau bergeser ke legalisasi tanah, sifat redistributifnya hilang. Padahal, keadilan sosial itu dapat tercipta mana kala penguasaan tanah yang luas pada badan-badan usaha itu diredistribusikan, dibagikan. Kalau perlu ditiadakan sistem agraria yang besar. Ada banyak dalam berbagai macam gerakan land reform dunia, termasuk Indonesia sendiri, dimana sistem agraria yang besar itu punah. Seperti, yang disebut sebagai tanah partikelir. Tahun 1948, keluar Keputusan Presiden no. 1 tahun 1948 yang menghapuskan tanah partikelir dari bumi Indonesia. Jumlah tanah partikelir hanya 1,4 juta hektar. Semua didistribusi begitu saja. Tanah partikelir yaitu suatu kawasan yang sangat luas dimana dimiliki oleh keluarga yang memiliki hak kenegaraan, bisa membentuk sistem pemerintah sendiri dalam kawasan tanah itu. Apabila kawan-kawan akrab dengan buku Max Havelaar karangan Multatuli, itu adalah cerita tanah partikelir itu ditunjukkan kejamnya. Termasuk, ada cerita Saijah-Adinda dimana kerbaunya itu terpaksa diseret oleh si demang, karena Bapak Ibu tidak bisa bayar pajak tanah partikelir. Hilang setelah Keppres 1 tahun 48.
Indonesia punya pengalaman itu tapi tidak dijalankan untuk perkebunan. Karena, proses KMB mewajibkan pemerintah Indonesia merehabilitasi kekayaan-kekayaan Belanda, dalam rangka mendapatkan pengakuan Belanda. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda begitu penting untuk pengakuan PBB terhadap eksistensi kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta tanda tangan setuju di Den Haag, setuju permintaan bayar hutang perang yang dikeluarkan Belanda untuk memerangi Indonesia. Setuju, Pak, Bu! Setuju! Konsekuensinya besar. Karena untuk pertama kalinya, Indonesia membuat UU, peraturan pelaksanaan, yang melarang orang masuk wilayah perkebunan. Peraturan itu membuat antara negara Republik Indonesia dengan petani-petani konflik dalam hal penguasaan tanah perkebunan. Tadinya, Negara Republik Indonesia adalah negara yang budiman. Pembuat UU Pokok Agraria tidak membayangkan bahwa penguasa negara Republik Indonesia yang menguasai melalui hak menguasai negara yang sifatnya kewenangan adalah penjahat. Pasti dia turunan malaikat, tidak pernah berbuat salah. tidak ada klausula dalam UU Pokok Agraria mensinyalir penguasa negara dapat berbuat salah. semua bersih. Karena asumsinya budiman, maka kewenangan dikasih begitu besar daripada domein verklaring. Hak milik individu dapat diinterupsi oleh penguasa Republik Indonesia melalui hak menguasai negara. Kalau domein verklaring, dia tidak bisa masuk ke hak hegendom, hak pribadi, hak private properti. Karena kekuasaan yang demikian besar dalam (a) mengalokasikan rencana penggunaan tanah, (b) menentukan hubungan hukum antara tanah dengan orang-orang di atasnya, apakah kriminal atau bukan dengan perbuatan hukum yang ada di tanah itu; (c) membuat perbuatan hukum atas tanah itu, kriminal atau tidak. Jadi, sifat kewanangan besar. Sifat kewenangan ini yang digunakan oleh rejim kontra revolusioner. Dan, melenggang kankung dengan kewenangan yang sangat besar. Karena itu, UUPA tidak dihapus. Karena UUPA memberikan landasan bagi kewenangan yang besar. Sifat etik disimpan dulu, kemudian sifat kewenangan yang besar itu yang muncul.
Saya ingin sampaikan bahwa mengubah birokrasi yang sifatnya otoritarian rente dengan menciptakan ide birokrasi kedilan sosial, mengalami kesulitan yang nyata untuk diterapkan. Kesulitan itu sekarang dihadapi oleh BPN. Ketika dia menetapkan akan redistribusi tanah-tanah yang berasal dari ijin sebelumnya –ijin lokasi, badan usaha, pengelolaan-, maka dia akan dapat tantangan. Perusahaan skala luas sedang melakukan proses review UU terhadap PP 10/2011. Di dalam birokrasi BPN terjadi pertentangan antara yang pro dan anti reforma agraria. Departemen kehutanan memblok ini. jadi, penetapan tanah-tanah yang ditetapkan untuk diredistribusi itu tidak disetujui oleh Menteri Kehutanan. Pada mulanya, ketika SBY memimpin rapat bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, BPN, mereka pertama-tama bersetuju. Tapi, setelah keluar dari situ, buat konferensi pers. Birokrasi Departemen Kehutanan punya manuver sendiri yang membuat menteri tidak bisa mengikuti komitmennya dengan Joyo Winoto, Menterinya waktu itu adalah KS Kaban. Sehingga, dia mengatakan tidak akan ada reforma agraria dalam departemen kehutanan. Alhasil reforma agraria diblok oleh sektoralisme yang kuat. Departemen lain tidak jalan. Pergerakan-pergerakan dalam Departemen Kehutanan hingga sekarang sanggup mengubah kebijakan.
Masyarakat sipil tidak berhenti. Sampai bulan lalu, ada konferensi tenur di Lombok. Kita merasa mendapat sedikit angin. Unit Kerja Percepatan Pembangunan, dimana Bapak Kuntjoro, yang mengevalusi menteri-menteri yang lain, menyatakan bahwa seharusnya hak masyarakat diakui dalam suatu kawasan hutan; seharusnya peta-peta yang digunakan oleh badan-badan pemerintah itu tunggal, tidak beragam; sektoralisme itu seharusnya tidak ada dalam urusan pengelolaan sumber daya alam yang terintegrasi. Dengan begitu, Departemen Kehutanan mendapat tekanan. Berbagai unsur progresif di Departemen Kehutanan mulai mengadvokasi di dalam berkait dengan gerakan-gerakan di masyarakat yang talenta. Kalau kita mulai dengan status hukum dari 33.000 desa di kawasan hutan negara, itu talenta, bukan land reform.
Kalau saja segala proses itu bisa berlangsung, hendak dibuat bisa berlangsung, maka ada 3 urusan yang harus diselesaikan. Pertama, sektoralisme. Harus ada keputusan Presiden yang menyatakan bahwa sektoralisme diakhiri dan dijalankan kerjasama antara Departemen Kehutanan dengan badan tenur. Kalau itu dilakukan, apa lagi dengan suatu pembentukan pelembagaan yang satu payung, misalnya pada presiden yang akan datang, 2014, dinyatakan 2 ini bersatu menjadi satu Departemen tersendiri, maka integrasi itu bisa dilakukan. Kedua, koneksi antara Departemen Kehutanan, BPN dan Departemen Pertanian harus berhubungan langsung. Karena, begitu dia distribusi tanah, seharusnya Departemen Pertanian bekerja untuk memberdayakan, sebagai tindak lanjut. Ada hal lain, Saya tidak tahu jawabannya, yaitu status Departemen Pertambangan yang sangat merusak dan ekstraktif ini. Posisi-posisi pertambangan Ini bagaimana diurusnya dalam konteks land reform. Ini belum ada jawaban sama sekali dan masyarakat sipil belum bekerja cukup memadai untuk wilayah ini.
Terakhir, ide tentang keadilan sosial, dan yang dijadikan prinsip dalam birokrasi reforma agraria, seharusnya dikumandangkan terus sehingga tiap-tiap badan birokrasi agraria punya jalur transformasinya. Jalur transformasi itu yang kita cari dan belum kita temukan. Terima kasih atas perhatiannya.
Moderator: terima kasih atas presentasinya. Saya kira, Bapak Ibu sudah dengar detailnya. Kalau kita dengarkan rangkaian cerita tadi, ini semacam analisis historis terhadap rejim agraria dari waktu ke waktu. Kelihatannya, lebih banyak lompat-lompat, dari sosialisme ke kapitalisme lalu sekarang balik lagi –mudah-mudahan, ini masih tanda tanya lompat kemana. Setidaknya, UU PA arahnya ke sini.
Analisis historis ini menarik. Kita melihat per periode muncul satu rejim kebijakan agraria sumber daya alam yang demikian. Kemudian, pada periode berikutnya, berubah, kebijakannya berubah juga. Analisis ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalau kita mau memberikan sesuatu yang baru, yang lebih baik, ke depan. Bisa jadi, pendekatan resolusi institusionalisme bisa menjadi tawaran. Tapi, tentu saja, kita jangan menghilangkan substansinya.
Saya kira, tantangan yang tadi disinggung oleh Oji. Kalau untuk BPN, Departemen Pertanian, dan Departemen Kehutanan, ada tawarannya, rekomendasi langkah yang harus dilakukan. Tapi, tantangan untuk pertambangan sebagai industri yang ektraktif. Di sini ada Begi dari pertambangan, nanti bisa diundang untuk menyampaikan masukannya.
Saya kira, itu untuk materi kedua dari Bang Oji. Materi ketiga, Budiman Sujatmiko akan menyampaikan makalah implementasi tap MPR. CV-nya, singkat saja, anggota DPR. Karena informasi di sini singkat, anggota DPR. Lahir di Cilacap 10 Maret 70. sekarang, anggota DPR menempati gedung nusantara. Silakan mas Budiman, tidak harus terpaku pada materi yang sudah disiapkan. Saya kira, lontaran dari pemateri sebelumnya bisa memperkaya materi kita untuk sesi tanya jawab. Silakan. Kurang lebih 20 menit.
Implementasi tap MPR No. IX Tahun 2001 Dalam Ranah Legislasi
Budiman Sujatmiko [DPR RI]: terima kasih. Assalamu’alaikum Wr. Wb. salam sejahtera untuk kita semua. Saya sengaja minta komentar yang terakhir. Karena, penyampaian Noer Fauzi merepresentasikan 2 hal yang dibutuhkan dalam legislasi. Paparan Noer Fauzi bicara mengenai aspek kesejahraan masyarakat, dan substansi dari persoalan-persoalan agraria-land reform. Jadi, kita sudah diberikan pemahaman soal ekonomi politik dari masing-masing rejim yang pernah berkuasa di Nusantara. Dari era Hindia Belanda, munculnya agrari Smith tahun 1870, diperkenalkannya agraris praktik yang diorganisir secara modern. Kemudian, yang tadi disebut, jeda, 20 tahun pertama Republik. Periode 70 adalah kapitalisme kolonial berdasaran pernyerapan ekstraksi.
Tahun 1945 – 1965 rejim yang berorientasi sosialistik. Saya suka menyebutnya, rejim ekonomi politik yang berorietasi sosialisme kerakyatan yang bertujuan mencapai sosialisme Indonesia oleh bung Karno. Mahkamah Agung katakan, cirinya seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, “…yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. Itulah ciri sosialisme Indonesia. Oji kurang lebih mengatakan dalam analisa historisnya adalah produk-produk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan juga manajemen politiknya diarahkan untuk mencapai tujuan itu. Dengan segala konsekuensinya dari sikap yang dimunculkan, kemudian impelementasinya di lapangan politik dan lapangan sosial.
Tahun 65 terjadi pembalikan proses menuju proses developmentalis. Mulainya dibuka ekspansi modal asing tahun 67 dalam bentuk undang-undang. Undang-undang pada masa Orde Baru, baik itu UU politiknya, ekonominya, sosial budayanya, menopang sebuah rejim korporatis cross, rejim birokratis, kapitalistik. Dari segi ekonomi kembali membagikan modal; dari segi politik ada korporatisme, kooptasi terhadap partai politik dan organisasi sosial. konservatif dari segi politik tapi tidak dalam segi ekonomi.
Kemudian, tahun 1998 terjadi reformasi. Terjadi peralihan, akselerasi dari rejim konservatif, birokratis menjadi rejim yang liberal, multi partai, ekonomi dari developmentasi menuju kapitalisme pasar bebas, liberalisme yang berintegrasi pada pasar global. Produk-produk legislasinya juga menawarkan seperti itu, mulai dari UU politik seperti UU Pemilu, pemisahan Polri dari TNI, independensi Bank Indonesia, UU 18/2004 tentang Perkebunan, UU Kehutanan, sampai ada UU tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Dimana soal hirarki perundang-undangannya tadi sudah diuraikan, mulai dari tap MPR no. 9/2001, UU no. 10/2004 dan kemudian diganti dengan UU 12/2011.
Pengalaman Saya hampir 24 bulan di parlemen era reformasi, Saya melihat dari sisi prosedur sebenarnya ini adalah era yang sangat baik. artinya, dalam rangka prosedur, Kami mengalami masa keemasan dimana apapun ideologimu, pandangan politikmu, sangat dimungkinkan bagi DPR sebagai fraksi, komisi, bahkan individu memajukan program legislasinya sendiri. Sekarang, dimungkinkan seorang anggota DPR secara individu, didukung oleh 13 anggota DPR dan 4 fraksi mengajukan undang-undang sendiri. Itu adalah satu hak anggota DPR yang sampai sekarang belum ada satupun anggota DPR yang memanfaatkannya. Saya tadi pikir, ketika menjadi anggota DPR, Saya manfaatkannya. Tapi, dalam momentum undang-undang apa? Jadi, itu kesempatan yang harus dimanfaatkan dan harus menang bukan hanya wacana. Setelah masuk DPR, Saya melihat ada beberapa UU yang punya berpotensi bagus. Salah satunya diadvokasi oleh Parade Nusantara –kebetulan Saya menjadi Dewan pembinanya, sebuah undang-undang yang sudah diusulkan DPR yaitu UU Masyarakat Adat dan Perlindungan Petani. Ini sudah masuk dalam agenda prolegnas 2012. jadi, dia diajukan oleh komisi.
Saya pikir, agenda-agenda yang menarik dalam penataan agraria ini: UU Pemerintahan Desa, UU Masyarakat Adat yang sudah masuk prolegnas, UU Desa juga sudah yang menjadi persoalan di pemerintah, UU Sumber Daya Alam. Menurut Saya, tiga undang-undang ini dikawal baik oleh masyarakat sipil, baik LSM, peneliti, maupun gerakan sosial. Saya pikir, salah satu undang-undang itu akan menjadi inisiatif Saya. tapi, karena sudah masuk, tidak apa-apa. problemnya sekarang, bagaimana menggolkan prolegnas itu. karena, kalau menyangkut isu agraria, peta Komisi II DPR cukup bagus. Apapun Fraksinya, relatif pro reforma agraria. Komisi II ini isinya hanya 2 jenis: eks birokrat dan eks aktifis. Karena, komisi II membidangi Politik dalam negeri, UU pemilu, reformasi birokrasi, pertanahan, dan kependudukan. Biasanya, kalau mengenai reformasi birokrasi, kependudukan, yang banyak bicara adalah eks birokrat, mantan Gubernur, sekda. Kalau urusan pertanahan, pemilu, biasanya teman-teman eks aktifis banyak bicara. Saya fokus pada 2 tema, reformasi birokrasi dan reforma agraria. Saya menetapkan bahwa 2 isu itulah yang menjadi fokus Saya sampai 2014.
Bagaimana hubungan soal TAP MPR no. IX sebagaimana diamanatkan dengan UU 12/2011? Prof. Yuliandri sudah membisikkan kepada Saya, bahwa setelah diperiksa, UU Pengadaan Lahan, UU 12/2011 tidak menjadi bagian konsideran. Tidak hanya UU 12/2011, TAP MPR no.IX tidak menjadi bagian dari konsiderasi. Itu sudah menunjukkan ada ignorance, ketidakpedulian, teledor, atau memang dalam politik legislasi yang banyak muncul bukan belum berpikir tapi ditentukan oleh transaksi-transaksi politik. Bagi Saya yang boleh dikatakan sebagai pihak yang dikalahkan oleh proses legislasi ini –Saya menganggap diri Saya sebagai yang kalah dari undang-undang ini- Saya melihat ini sebagai peluang untuk bagaimana masyarakat sipil melakukan pengajuan judicial review kepada MK bahwa pembuatan undang-undang ini tidak sesuai dengan UU no. 12/ 2011 dimana berkaitan agraria tidak mengikut sertakan pada TAP MPR No. 9 tahun 2001. bagi Saya, ini adalah peluang. Ketika Saya bicara “Saya”, Saya sebagai penggiat agraria yang masuk dalam DPR dengan tujuan melakukan reforma agraria melalui politik legislasi. Itu menarik.
Saya harus mengakui bahwa dari 13 UU yang berkaitan dengan sumber daya alam, pertanahan, pedesaan, UU Pokok Agraria masih menjadi satu-satunya undang-undang yang berpihak secara jelas kepada rakyat, petani penggarap dan pekerja. Sekarang, ketika seluruh produk undang-undang yang lahir di masa Orde Baru dan masa reformasi cenderung menjauh dari kepentingan petani, kepentingan masyarakat adat, kepentingan masyarakat pekerja di sektor pertanian, maka -seperti dikatakan Noer Fauzi- proses legislasi kita mengalami kemunduran dari sektor agraria. Hal yang tadi disebut jeda itu, benar-benar jeda. Jeda itu belum muncul lagi. masih meneruskan politik lama agraria yang bersifat kapitalistik. Ketika tadi Saya mengadakan peta komisi II sebenarnya pro-reforma agraria, Saya hanya bicara peta hari ini. sementara, banyak undang-undang yang berkaitan dengan agraria lahir di masa pra anggota legislasi 2009.
Karena itu, munculnya gagasan UU Masyarakat Adat dan Perlindungan Petani serta –mudah-mudahan akan golnya- UU Desa, sebenarnya adalah kesempatan pada legislasi yang diharapkan akan bisa membayangi undang-undang yang selama ini banyak memihak pada modal besar atau negara. UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU pengakuan masyarakat adat, dan UU desa –ini sebenarnya kalau dalam pengertian Saya, Saya bicara Saya- karena memang 3 undang-undang ini masih kosong. Ketika kita masukkan tulisan UU tentang perlindungan petani, sebenarnya gagasannya apa? Saya tidak tahu pemerintah akan menyodorkan apa. tapi, setidaknya, Saya sebagai legislator yang tentunya tidak sendiri, ketiga undang-undang ini seharusnya memberikan kewenangan dan hak kepada desa maupun masyarakat adat, petani, untuk melakukan proses pemberdayaan –pertama-tama- politik, kemudian ekonomi dan budaya.
Maksud Saya dengan pemberdayaan politik dalam UU Desa, desa mengelola. Di situ dimungkinkan terjadi partisipatory budgeting dan partisipatory planning pembangunan desa. Anggaran tidak harus ditaruh di kas desa tapi bisa saja di kas kabupaten. Desa sebagai unit paling dasar dari tata negara Indonesia bisa dimungkinkan mengelola pembangunan. Tentu saja, problem keagraria –yang tadi sudah disebutkan- ini akan bisa memangkas birokrasi negara. Contohnya, di UU Desa adalah untuk menghancurkan atau setidaknya menimalisir sektoralisme dengan mengadakan pendekatan teritori. Desa menjadi unit karena desa adalah sebuah unit dimana unsur negara dan masyarakat menjadi satu. Inilah tantangan kita untuk menjadikan pengikisan sektoralisme di tingkat nasional, kita lebur di teritorialisme untuk pembangunan desa dan wilayah perdesaan, Village and rural areas. Dengan menjadikan desa sebagai unit dimana dimungkinkan terjadi proses partisipatory budgeting, partisipatory planning. Nanti, bahkan dalam UU Adat, yang Saya dialogkan dengan teman-teman AMAN, akan Saya perjuangkan agar dimungkinkan terjadinya partispatory mapping sumber daya alam. Maka, sebenarnya, ini adalah proses untuk merebut kembali inisiatif dari pelaksanaan TAP MPR no. IX tahun 2001. Dalam undang-undang ini akan kita cantumkan TAP MPR ini dibawah UUD 1945 sehingga ada legitimasi kuat. Hanya dengan otonomi desa, otonomi masyarakat adat, ada partisipatory mapping, partisipatory planning, partisipatory budgeting akan dimungkinkan terjadinya reforma agraria. Unit desa berdiri di depan. Di situlah kita akan berhadap-hadapan dengan departemen Keuangan. Kenapa desa bisa menyusun anggaran? Anggaran diperlukan agar desa bisa mengelolanya dalam perencanaan setahun. Anggaran itu dipakai untuk mengelola atau membeli tanah-tanah milik perkebunan, bahkan bisa menuntut kalau tidak ada penyertaan saham bagi desa. Desa melalui BUMDes, kita menuntut agar desa punya penyertaan saham BUMDes dalam pengelolaan perkebunan. Artinya, secara ekonomi tidak dipecah, tetap berorientasi industri. Tapi, kepemilikannya bisa dibagi bersama dengan perusahaan-perusahaan yang ada dengan beberapa hal yang bisa kita tawarkan. Sahamnya sebagian diambil oleh desa atau masyarakat adat atau kemudian dibeli seluruhnya. Intinya, bahwa ketika desa memiliki kuasa untuk mengelola anggaran, dimungkinkan terjadi- pertama, melalui penguatan BUMDes.
Saya sedikit cerita. Ini tidak ada hubungannya dengan TAP MPR. Kami di PARADE NUSANTARA, kumpulan desa, sedang meneliti proses pemberian ijin Alfamart dan Indomart. Di depan pasar tradisional banyak sekali Alfamart dan Indomart. Setelah terkumpul, kita akan minta mereka tutup atau mereka berubah dari retail menjadi grosir atau sebagian harus memberikan saham kepada BUMDes, penyertaan saham. Kalau perlu diambil alih oleh BUMDes. Bagian dari proyek redistribusi aset yang tidak ada hubungan dengan tanah. tapi, ini penting. kelihatannya itu akan menjadi pola gerakan desa dan masyarakat adat ke depan. Saya sudah menawarkannya ke AMAN. Di legislasinya, banyak undang-undang terjadi ketika agen-agennya di bawah tidak efektif juga. pun, jaminan misalnya ketika ada UU Desa, UU Masyarakat adat ada, UU perlindungan petani ada, akan menjadi efektif? Itu semua tergantung pada kerja teman-teman di luar parlemen. Saya sebagai anggota DPR dan teman-teman yang lain adalah bagaimana membuatnya.
Sekarang, Saya mau menceritakan bagaimana terjadi peluang perubahan konstitusional. Inilah sistem yang ada sekarang. Proses lewat undang-undang. Jadi, sebuah undang-undang bisa muncul dari usulan anggota DPR, baik itu dalam kerangka Fraksi seperti Saya PDIP atau Komisi II, Saya sudah mengajukan usul dan Saya masuk dalam Panja-nya, UU Aparatur Sipil Negara. Itu undang-undang yang akan merevolusi birokrasi kita. Badan Pemberdayaan Aparatur Negara memang luar biasa. Rancangan undang-undang yang kita ajukan semuanya dimasukkan dalam Daftar Isian Masalah pemerintah. 90% pemerintah keberatan dengan ajuan RUU Aparatur Sipil Negara. Pemerintah mengajukan keberatan. Ini berkaitan dengan birokrasi. Birokrasi independen, tidak lagi dibawah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, tapi kita akan buat Komisi Aparatur Sipil Negara yang mengawal, up grading terhadap birokrasi. Birokrasi hanya tunduk pada undang-undang. Birokasi tuannya adalah negara, undang-undang. Maka, harus segera melaksanakan pada hari itu juga undang-undang yang ditetapkan. Asumsinya, setiap undang-undang lahir, tidak perlu lagi ada PP. Sehingga, pembicaraan dalam undang-undang semakin detail karena sudah bicara pelaksanaan. UU detail tidak butuh PP. Ini ada presedennya, seperti UU politik. Karena detail, dia langsung jalan. Kita ingin ke depan setiap produk undang-undang baik yang berkaitan dengan petani, sumber daya alam, masyarakat adat itu detail sehingga hari itu juga mengacu ke sana. Masyarakat punya hak untuk membangkang terhadap pemerintah pusat maupun daerah, ketika policy-nya bertentangan dengan undang-undang yang sudah secara detail. Kita usahakan ke sana. Jadi seperti merevolusi dan memprofesionalkan birokrasi. Penolakannya luar biasa dari MenPAN sebelumnya. Kemudian, resuffle, Profesor Eko menjadi wakil menteri. Kebetulan, Beliau juga menjadi konsultan kita ketika menyusun RUU ini. Maka, terjadilah proses RUU dari DPR dengan wakil Kementerian, Prof. Eko Prasojo, menemukan banyak titik temu. Walaupun tidak seprogresif sebelumnya, tapi jauh lebih prosgresif daripada undang-undang sebelumnya. Ini penting karena ini merupakan kesempatan untuk membuat UU Desa, UU Masyarakat Adat, dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, jauh lebih detail, sehingga tidak perlu PP. Walaupun, mungkin larut dalam pembahasannya. Tapi, itu penting untuk menentukan efektifitas dari implementasi undang-undangnya di lapangan segera. Sama halnya dengan UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), UU 40/2004, belum ada PP-nya sampai sekarang. Belum ada PP-nya, belum dilaksanakan, beberapa pihak sudah meminta merevisi beberapa pasal. UU BPJS, menunggu 2014-2016, kesepakatan. Itu terjadi memenuhi aspek birokrasi. Nanti, menuntut legislasi yang detail. Untuk itu, Teman-teman juga harus aktif.
Jadi, usul dari anggota DPR, fraksi, komisi, atau DPD, atau masyarakat. Masyarakat juga bisa mengajukan usul, misalnya HuMa, rancangan undang-undang. Kemudian, akibat keputusan MK, kumulatif terbuka. Jadi, setiap prolegnas setiap tahun bisa diubah. Ini menjadikan rancangan undang-undang yang masuk prolegnas, prioritas, itu perjuangan politik. Pertama, perjuangan memasukkan rancangan undang-undang itu dalam prolegnas. Kemudian, dari puluhan itu, untuk bisa segera dibahas, menempatkan di atas dan di bawah, menengah itu juga perjuangan politik. Itu butuh, butuh lobi, tekanan, opini.
Skema usulan inisiatif. Contohnya, Saya anggota DPR. Budiman Sujatmiko mengusulkan UU –Saya sedang berpikir 2013 karena beberapa undang-undang yang berkaitan dengan agraria sudah bagus- Kinerja Pemerintah. Undang-undang ini mengatur agar setiap janji visi dan misi presiden yang menang menjadi UU secara detail. Sehingga, tidak lagi visi dan misi seorang presiden itu sifatnya normatif, daftar keinginan dan tidak visibel. Kita ingin ada yang mengharuskan visi misi presiden dituangkan –minimal- seperti naskah akademik sebuah undang-undang. Sehingga, ketika menjadi presiden, visi dan misinya menjadi undang-undang yang mengikat presiden itu. Sehingga, setiap kampanye presiden harus kuantitatif, ada ukurannya. Sehingga, presiden bisa di-review dalam perjalanannya. Selama ini, seluruh calon presiden bicara ekonomi kerakyatan. Seluruh calon presiden ketika menjadi calon semua menjadi kiri, pro-kerakyatan, progresif. Tapi, ketika jadi presiden, jadi kanan, liberalistik semua. karena, tidak ada pengikatnya.
Dari pengusul, baik dari Badan Legislasi, Komisi, maupun anggota DPR, baleg melakukan verifikasi. Apakah usulan itu –dalam bentuk RUU, tidak sekadar usul saja, yang dibuat sendiri- diharmonisasi secara vertikal dengan UUD 1945 dan TAP MPR menurut UU 12/2011. Misalnya, RUU usulan Budiman Sujatmiko tentang Pemberdayaan Petani cocok atau tidak dengan TAP MPR no. IX tahun 2001. Kalau tidak cocok, tidak diterima di Baleg. Kalau cocok secara vertikal, dicocok lagi dengan undang-undang lain, tumpang tindih atau tidak? Kalau tidak, baru dibicarakan. Kemudian, dibawa ke paripurna DPR. Budiman Sujatmiko, RUU Perlindungan Petani, sudah diharmonisasi secara vertikal dan horisontal, dibawa ke paripurna DPR, DPR sepakat atau tidak menjadi ini sebagai inisiatif DPR? Kemudian, kita mengajukan ke Presiden dan Wapres. Kemudian, dibicarakan di Badan Musyawarah. Badan Musyawarah menentukan apakah RUU ini dibicarakan oleh satu panja kecil saja atau panja besar –lintas komisi. Biasanya, ini perdebatan. Apakah UU petani itu hanya dibahas di komisi II saja, tekanannya pada soal agraria, atau akan dibicarakan dalam panja besar sehingga mengikut sertakan komisi IV yang berkiatan dengan perkebunan dan pertemuan. Setelah itu disepakati, baru itu dibahas di pansus. Di pansus itu dibicarakan. Kemudian, di tingkat paripurna, UU. Prosesnya cepat atau lambat –sekali lagi- tergantung dari politic interest legislator dan tekanan masyarakat, pemangku kepentingan undang-undang ini. Tekanan itu bisa dalam bentuk lobi, aksi massa, seminar, survey atau apapun.
Dari pembicaraan ini, Saya mau menceritakan bahwa proses DPR penuh labirin. Tapi, ini yang paling mungkin disepakati mengingat banyaknya kepentingan. Bagaimana lahirnya undang-undang yang pro-modal relatif lancar, UU Penanaman Modal, UU Pelabuhan, UU Perkebunan, karena ada pelumasnya. Saya harus akui bahwa permainan-permainan itu ada. Tapi, kalau UU Desa, UU Masyarakat Adat, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasti tidak ada pelumasnya. Paling, rakyat hanya bisa mengancam, kalau kau tidak setuju-.
Noer Fauzi: yang ada banyak remnya.
Budiman Sujatmiko: tapi, masyarakat seperti UU Desa, kita mencoba menekan. Kita mengancam. Kepala desa punya data anggota DPR dari dapilnya. Kemudian, disurati, “kalau Anda tidak setuju undang-undang ini Saya jamin Anda tidak ada yang mendukung 2014.” Memang tidak ada uang, yang ada ancaman. Cari anggota DPR dari masing-masing dapilmu, surati, “kalau Anda tidak mendukung undang-undang ini, Anda menghalangi ini, ini, ini, Anda tidak akan dipilih lagi.” Ini pentingnya masyarakat sipil bertindak seperti itu, entah HuMa, AMAN, SPP apapun untuk menggunakan ketika tidak bisa memberikan pelumas dalam arti uang yang tidak benar juga. kita bisa melakukan ancaman untuk memboikot, bahwa Anda tidak boleh -kalau kau nanti kampanye di desa Saya- partai Anda diharamkan membuat ranting kampanye di desa Saya. itu serius sudah.
Teman-teman perlu paham untuk prolegnas 2012 ada 64 RUU yang perlu dibahas. Ada beberapa RUU inisatif DPR yang krusial. Ada RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar. Ini berpotensi mengkriminalisasi dan menyingkirkan akses petani/masyarakat sekitar hutan. Saya tidak tahu komisi mana yang mengajukan. Kemudian, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ini undang-undang yang bisa kita buat secara progresif. Kemudian, RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat. Ini penting dan harus menjadi cerminan. Harus ada tekanan agar UU ini tidak hanya formal masuk prolegnas tapi dibahas. Inisiatif pemerintah, yang krusial adalah RUU perdagangan, UU perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; UU Pemerintah daerah, kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan ijin terhadap modal asing secara langsung. RUU tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; berpotensi penguatan kewenangan daerah untuk memberi perijinan terhadap modal asing secara langsung. UU 32 dipecah menjadi UU Pemerintah Daerah, UU Pemilihan Kepala Daerah, dan UU Desa. UU Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan untuk memberikan ijin kepada penanaman modal asing secara langsung, pemerintah kabupaten. Ini penting untuk diperhatikan. Ini Komisi II, komisi Saya, berkiatan dengan pemerintahan.
Perlu dipahami oleh teman-teman, bahwa ruang legislasi kita adalah ruang terbuka, yang sudah dioptimalkan kalangan modal secara maksimal selama era reformasi. Gerakan-gerakan sipil meskipun ada kemenangan-kemenangan kecil seperti TAP MPR no. IX, UU BPJS, Saya pikir, itu belum cukup karena masih ada agenda lain seperti UU Desa, UU Perlindungan Petani dan UU Pengakuan Masyarakat Adat. Itu menjadi PR kita semua. Kami di DPR dan teman-teman tidak bisa lepas dari situ. teman-teman juga bisa mengajukan RUU melalui DPR. Terima kasih. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Moderator: terima kasih ketiga narasumber sudah menyampaikan materinya. Saya kira, cukup banyak varian dengan detail di sana-sini dari masing-masing aspek. Saya kira, ini memperkaya informasi untuk kita melihat kembali ke tema, bagaimana kebutuhan TAP MPR no. IX/2001 ketika kembali masuk dalam hirarki.
Tadi banyak singgungan di berbagai aspek. Terakhir, Budiman melihat peluang menempatkan TAP MPR dimasukkan dalam berbagai RUU. Ini perlu dicermati ke depan dan dikawal, demikian sarannya. Sekarang, sudah jam 12. Di awal tadi, Saya mengusulkan, kita selesai jam 12.30. jadi, hanya ada 30 menit. Saya menawarkan, semua yang mau komentar, bertanya, langsung ada 5 atau 6, lalu ditanggapi langsung oleh setiap narasumber. Jadi, satu kali sesi saja. Selesainya jam berapa, ya-
Budiman Sujatmiko: Saya ijin jam 1, karena ada acara partai.
Moderator: ya. Kita pertimbangkan. Semoga tidak jauh melewati jam 1. ini sesi tanya jawab. Jadi satu sesi saja dengan jawaban langsung dari narasumber. Lalu, kita tutup seminar ini. Silakan yang ingin berkomentar, menyangkal, atau bertanya. Saya pilih sayap kiri, sayap tengah, kanan, 5 orang. Mohon sebutkan identitas singkat.
Tanya Jawab
Andi Nur [Komnas HAM]: selamat siang, Assalamu’alaikum Wr. Wb. Saya, Andi, dari Komnas HAM. Pertama-tama, Saya tadi bertanya ke panitia, acara ini dibuat karena ada kasus yang muncul di media atau bukan? Jawabannya, bukan. Saya salut dengan kegiatan ini karena konsistensi HuMa untuk terus memperhatikan persoalan agraria di Indonesia.
Kedua, Saya mencatat yang disampaikan Mas Budiman yang sudah di DPR, kelompok yang eks-aktifis. Saya kira, mas Budiman di DPR itu masih aktifis. Karena, aktifis itu kan bebas bersuara dan lebih ekspresif. Tapi, mungkin karena eks-aktifis jadi sekarang agak sedikit mengikuti prosedur di DPR. Saya tanya ke Budiman. Kita tahu sekarang persoalan agraria menjadi persoalan yang terus terjadi. Ekskalasinya, karena banyak pengungkapan oleh media, menjadi terus menerus, belum selesai. Karena ada insiden yang menimbulkan korban jiwa jadi terlihat begitu mengerikan. Kita tahu, persoalan reforma agraria menyimpan bara yang sewaktu-waktu bisa meledak seperti ini. Klarifikasi, di DPR sekarang, apakah sudah ada kegiatan yang terus menerus mengawal reforma agraria baik pendekatan legislatif maupun aktifisme di kalangan parlemen? Atau, memang reforma agraria, Kita tahu dari pengalaman, reforma agraria ini menjadi tarik menarik kesejahteraan sosial dan modal itu sendiri.
Saya sampai juga, bahwa di Komnas HAM –dari data pengaduan yang diterima, reforma agraria memang kasus yang paling tinggi yang dimediasi Komnas HAM. kita tahu, Komnas HAM juga punya kegiatan untuk melakukan mediasi. Dalam tahun 2010 tercatat kasus agraria adalah kasus yang paling tinggi dan kompleks. Oleh karena itu, Saya kira sangat penting pendekatan struktural, bukan pendekatan kasus. Saya kira, DPR menggunakan pendekatan kasus. Kita belum melihat adanya pendekatan menyeluruh seperti yang diproyeksikan salah satunya oleh Mas Noer Fauzi. Saya kira, itu. terima kasih, Assalamu’alaikum Wr. Wb..
Moderator: terima kasih, Andi dari Komnas HAM. Selanjutnya?
Reza [Depkumham]: terima kasih. Assalamu’alaikum Wr. Wb. selamat siang, salam sejahtera. Saya Reza dari Kementerian Hukum dan HAM. pertama, terkait dengan keberadaan TAP MPR dalam hirarki perundang-undangan. Kalau Kami boleh berbagi cerita, mungkin tidak resmi dari Kementerian Hukum dan HAM. Awalnya, RUU yang mengganti UU 10/2004 itu inisiatif DPR. Pemerintah tidak mencantumkan usulan dimasukkannya kembali TAP MPR. Kemudian, dalam dinamika pembahasan, muncul usulan dari DPR –dari catatan Kami- memasukkan TAP MPR. Itu ada surat resminya dari MPR untuk memasukkan kembali. Itu dijadikan proses bargain pemerintah dan DPR. Pemerintah juga punya kepentingan untuk memasukkan/mempertahankan peraturan presiden. Memang dinamika itu yang muncul dalam pembahasan. Memang, kemudian, pada akhirnya, TAP MPR pasca UU 11/2011 tidak kaku lagi kalau memang mau dijadikan sebagai dasar hukum UU. Mengingat, dalam suatu undang-undang. Meskipun, dalam RUU Pengadaan Tanah yang sudah disetujui bersama ini, nampaknya luput. Itu sedikit kisah terkait TAP MPR ini.
Tap MPR no. 9/2001, menarik dalam makalah Noer Fauzi, apakah ini berbahaya sebagai pintu masuk neolib atau kapitalis, atau justru bermanfaat sebagai mobilisasi hukum di bidang pertanahan. Kalau Kami boleh berpendapat, memang dalam tap MPR ini memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Kita harus maju ke depan. Kita tidak produktif kalau lalu balik ke 1960. Karena, di Indonesia ini, nampaknya ada sebagian kalangan yang mengagungkan UU 5/60. tapi, yang perlu diingat, pada tahun 1960, UUD kita masih UUD lama, dan belum ada otonomi daerah. Ini satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, tahun 60, pengaruh PKI pada parlemen sangat besar. Ini perlu juga menjadi catatan. artinya, nilai produk legislasi di dekade itu perlu mendapatkan catatan, ini bom waktu atau apa yang memang disiapkan.
Terakhir untuk Mas Budiman. Karena ini sedang masa reses, masa dimana para anggota dewan dari banyak masukan, aspirasi, dan sebagainya, mungkin terkait dengan UU Aparat Sipil Negara, walaupun mungkin bukan dari kalangan birokrasi, kita perlu hati-hati agar tidak terjadi –yang dikuatirkan- privatisasi birokrasi. Kita harus akui, UU Kepegawaian itu belum pernah di judicial review. Ini perlu menjadi catatan bahwa ternyata memang UU di bidang kepegawaian ini, bagi pengawai nampaknya memang tidak terlalu bermasalah dari segi aturannya tapi dari segi penerapannya mungkin perlu perbaikan. Solusinya tidak selalu harus solusinya adalah pengganti suatu rejim perundang-undangan. Mudah-mudahan yang Kami sampaikan bermanfaat bagi forum ini. selamat siang Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Moderator: terima kasih dari Kemenhukham. Selanjutnya, dari tengah.
Mardi [DPR RI]: Assalamu’alaikum Wr. Wb. Saya, Mardi. Saya dari Sekjen DPR RI. Saya juga akan sharing. Kebetulan, Saya, legal drafter RUU DPR. Saya terlibat dalam tim asistensi penyusunan UU 12/2011. terlihat sekali UU ini memakai judul yang sama tapi dengan nomor yang baru. Pergantian karena UU no. 10/2004 diberikan celah bahwa setelah 50% perubahan subbstansi dan format bisa diganti. Kemudian, untuk memudahkan pembaca. Kalau kiita tambahkan insert beberapa pasal, mungkin akan membingungkan pembaca. Sehingga, untuk memudahkan masyarakat secara umum dan bagi orang hukum juga akan mudah. Beda dengan pasal baru dengan melihat UU yang lalu itu membingungkan.
Ada hal lain, soal adanya perda yang dibedakan: perda propinsi dan perda kabupaten/kota. memang, sebelumnya hanya 1 perda untuk mencakup kedua. Pada akhirnya, itu dibagi 2 karena dipandangan perda kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan perda Propinsi.
Kemudian, terkait dengan TAP MPR yang muncul. Sebenarnya, bukan inisiatif tim asistensi atau tim pemerintah. Tapi, dalam proses pembahasan. Biasanya, pembahasan itu melibatkan para akademisi dan pimpinan-pimpinan MPR. Mereka secara umum ingin TAP MPR dimasukkan dalam draft. Tapi, TAP MPR hanya terkait dengan TAP MPR no. I tahun 2003, dan hanya terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 4. karena, jaminan kepastian hukum terhadap Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR no. 1 tahun 2003, karena selama ini tidak ada kepastian hukum di UU 10/2004. itulah secara historis kenapa TAP MPR muncul dalam hirarki peraturan UU 12/2011.
Saya juga ikut dalam tim asistensi RUU ASN, yang tadi disebutkan budiman sujatmiko termasuk profesor. Kalau sebelumnya menteri yang lama menolak mentah-mentah RUU yang diajukan Komisi II, terkait dengan pergantian menteri, sepertinya akan mulus. Terima kasih. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Moderator: bertambah, sekarang. Sebentar, yang sudah diurut dulu. Nanti, kita tampung semua. pertanyaan dan komentar boleh banyak, jawaban serahkan kepada narasumber. Silakan.
Xxx: terima kasih. Berkaitan dengan TAP MPR ini semacam prinsip-
Moderator: sebutkan nama.
Arizona: Arizona dari Azis. TAP MPR itu kan sama dengan prinsip-prinsip of state atau prinsip pemandu kebijakan negara. karena itu, gbhn ditetapkan dalam bentuk TAP MPR. TAP MPR no. IX itu sebenarnya hampir sama dengan gbhn. Kita tahu ketika 98 banyak sekali TAP MPR yang jadi pemandu. Ada tata pemerintah bersih dan bebas kkn yang kemudian menjadi undang-undang. Kemudian, tentang otonomi daerah yang juga menjadi undang-undang. Kemudian ada tentang pembaharuan ekonomi, soal demokrasi ekonomi, dll. Ada juga soal HAM yang menjadi UU HAM. UU HAM ini hampir semua diambil dari TAP HAM. tapi, TAP IX ini agak aneh, tidak jadi UU sendiri. Kemudian, juga ada berkaitan dengan struktur kenegaraan. MPR dulu lembaga tertinggi negara. produk yang dihasilkan bisa mengikat semua lembaga. Presiden dulu mandataris MPR. Lembaga-lembaga tinggi negara, dulu menyampaikan laporan. DPR menyampaikan laporan. Tapi, kemudian terjadi perubahan struktur. Di situlah letak TAP MPR tidak punya gigi lagi karena tidak ada kewajiban untuk lapor ke MPR.
Lalu dengan situasi seperti itu, bagaimana? Bagi Saya, yang pertama dibutuhkan, TAP MPR IX mau diposisikan sebagai apa? kalau dia diposisikan sebagai penjelasan terhadap konstitusi Pasal 23, maka dia bisa jadi suplemen jadi MK bila menguji UU sumber daya alam. Kita tahu, dia tidak pernah dijalankan. kemudian semakin tersektoralisasi. Saya ingat, dulu, meskipun PDIP yang memenangkan pemilu tahun 99, banyak sekali sektoralisasi di bidang agraria yang lain, seperti migas, sumber daya air.
Kenapa dulu pilihannya melakukan perubahan melalui TAP MPR. itu ada proses amandemen undang-undang. Kenapa tidak mendorong dalam perubahan konstitusi. Beberapa negara dari otoritarian ke demokrasi melakukan konsitusionalisasi agraria. Kita lihat sebelumnya: Philipina, Brazil. Bahkan ada satu komisi tertentu berkaitan dengan agraria reform di Philipine dan Brazil. Waktu itu, ada perdebatan kuat. Kenapa tidak ada yang lain, misalnya ketentuan baru dalam materi konstitusi yang berkaitan dengan agraria reform. Saya pikir sampai sekarang, cantolan kita masih Pasal 33, terutama ayat 3. Kita punya cantolan nasional yang langsung. Terima kasih.
Moderator: selanjutnya.
Rahma: Saya, Rahma dari HuMa. TAP MPR no. IX tahun 2001 memandatkan adanya harmonisasi terhadap semua peraturan perundang-undangan yang ada. Pertanyaan Saya sederhana, bagaimana melakukan harmonisasi semua peraturan yang jumlahnya ratusan? Beberapa Departemen pernah mencoba melakukan upay a perbaikan perundang-undangan itu sendiri tapi ternyata itu juga tidak sesuai dengan perundangan yang lain.
Kedua, untuk mas Budiman. Saya ingin tahu, apa yang terjadi di pembahasan RUU sampai jadi UU, mengingat beberapa peraturan di bagian awal, seperti RUU Pengadaan Tanah, ada TAP MPR yang tidak dicantumkan. Kemudian, Peraturan no. 10 tahun 61 tentang pencabutan hak atas tanah yang ternyata sampai sekarang belum dicabut tapi tidak pernah dibahas dalam RUU Pengadaan Tanah. Sebetulnya, dalam proses pembuatan, para anggota DPR tidak meneliti secara benar-benar, undang-undang apa yang sudah keluar, apa yang bisa dijadikan pertimbangan dan mengingat, sehingga ketika sudah keluar banyak yang lolos tidak dicantumkan. Terima kasih.
Moderator: tambah lagi, 1-2.
Steni [HuMa]: Saya, Steni dari HuMa. Melanjutkan yang disampaikan Kang Oji soal situasi di sekitar kebijakan pertambangan. Saya kira, ada perubahan di lapangan walaupuan tidak by design melalui peraturan. Pra pengumuman moratorium dirjen hutan dan presiden, ada sejumlah bupati yang melakukan langkah sendiri untuk moratorium tambang. Saya mencatat ada 4 Bupati. Bupati Lembata, September 2011. Mei 2011 itu Sumba barat; Agustus 2011 Manggarai Barat; Februari 2011 Bupati Malawi -Kalimantan Barat mengeluarkan moratorium tambang dan perkebunan. Gerakan dari bawah sudah mulai muncul. Saya tidak tahu apakah Bupati-Bupati itu dari PDIP. Nampaknya, mereka melakukannya berdasarkan inisiatif sendiri dengan berbagai alasan. Umumnya, ada 2 alasan paling serius, desakan massa dan kerusakan lingkungan. Kedua alasan ini sebetulnya menjadi ketika presiden mengumumkan moratorium meskipun secara parsial dan setengah hati. Hanya, Saya kira, pada saat yang bersamaan, itu secara politik tidak didukung DPR. Karena, isu itu begitu menarik sebetulnya untuk merujuk kembali ke pasal 5 huruf (a) TAP MPR IX tahun 2001 soal review seluruh kebijakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan agraria. Sebetulnya, itu bisa menjadi pintu masuk. Tapi, sayang dukungan DPR tidak begitu maksimal. Bahkan, ada pertanyaan serius waktu itu dari DPR terhadap kebijakan ini dikaitkan dengan kebutuhan dalam negeri. Saya ingin tanya ke Budiman, sebenarnya pertimbangan di DPR terhadap TAP ini seperti apa? secara politik, dia upaya untuk meneruskan TAP IX, tidak kelihatan relasinya. Tapi, secara substansi jelas relasinya, terutama pada Pasal 5 huruf (a) review terhadap seluruh peraturan.
Dengan demikian menanggapi Kang Oji, perkembangan di bidang pertambangan belum ada yang menyentuh secara serius. Saya kira sudah mulai. Tidak banyak juga artikel atau kajian teoritik yang berkaitan dengan perkembangan terkini soal moratorium. Saya kira perlu juga melihat ke sana untuk melihat sejauhmana peluang. Kita perlu juga mendorong kebijakan seperti ini sebagai ruang jeda untuk menenggok permasalahan dan menata ulang –bukan hanya karena alasan lingkungan tapi juga penguasaan dan struktur agraria. Terima kasih.
Moderator: terima kasih. masih ada 2, singkat pertanyaannya.
Zaenal Mutakim [KPA]: Zaenal Mutakim dari KPA. Analisis kembalinya TAP ini juga menjadi pertanyaan. Karena, selama proses kelahiran TAP 2001 sampai dicabutnya unsur dari undang-undang juga tidak ada tindak lanjut.
Kedua, paparan Kang Oji tadi jelas bahwa rejim birokrasi rente ini sangat binal. Kemudian, apakah ini bisa menjadi faktor yang bisa jadi menguntungkan rakyat juga jadi pertanyaan. Karena, dominasi birokrasi itu go politic. Kalau politik pro-investasi modal asing, hukum juga mengikuti itu. Dari situ, kita melihat bagaimana –contoh kasus di DPR- proses pengesahan undang-undang. Juga, terlihat tidak banyak penolakan-penolakan dari kawan yang pro rakyat. Pertanyaannya, kemana saja selama ini?
Dari situ terlihat bahwa secara politik, negara tidak berbuat banyak. karena itu, Saya tidak melihat potensi kembalinya TAP MPR no. IX berdampak untuk rakyat. Saya lihat bahwa perubahan utama dari proses negara ini bukan pada proses kebijakan struktural tapi bagaimana kekuatan rakyat di bawah secara kuat mengkonsolidasi dirinya kemudian melakukan tekanan terus menerus. Karena, kalau menyerahkan perubahan struktural itu ke kelompok-kelompok politik dan elit tidak akan banyak. Ini yang masih menjadi pertanyaan besar. Karena di kalangan NGO juga terlihat bagaimana proses pendekatan struktural, proses pendekatan negara digunakan untuk melakukan perubahan negara. artinya, kekuatan asing juga lebih kuat dalam menguasai cara berpikir, politik, punya kekuatan uang, kekuatan militer, dan lain-lain. Kemenangan hukum juga tidak terlalu berdampak. Proses kemenangan hukum tidak terjadi di lapangan. artinya, di lapangan, eksploitasi tetap tinggi, pembunuhan pada petani tetap terjadi, kemudian pelepasan pejabat terjadi. Tidak ada satu pun pelanggar hukum ditembak. Ini menjadi sebuah ketidakadilan. Secara hukum, istilah semua orang sama di depan hukum tidak berlaku. Karena, kalau ada pengusaha yang melanggar tidak pernah ditindak. Saya pikir, bagaimana diskusi kita memacu pada suatu tindakan yang lebih tepat, mengubah negara ini menjadi lebih baik, negara yang berkeadilan.
Moderator: terima kasih. yang terakhir.
Priyadi [xxx]: Saya mau ke Prof Yuliandri. Tadi Bapak menyinggung UU terkait sumber daya alam. Kita tahu bahwa perundang-undangan di Indonesia selalu nanti kita akan perang di lapangan dengan pengkotakan, tentang rukun tangga, dan sebagainya. Kemudian, kita dihadapkan juga dengan ketakutan ekseksutif di daerah untuk membatalkan sebuah perundangan yang kabupaten ini pakai. Dengan berlakunya TAP ini dimungkinkankah suatu proses TAP ini yang setingkat di atas UU dalam doktrinnya dilangkahi dengan ada TAP MPR di sistem hukum Indonesia.
Kedua, lex specialist. Kalau kita bicara sistem perundang-undangna, lalu bagaimana sitstematikan intervensi MPR terhadap lex specialist AK ini? Kita tahu UUD 1945 itu sangat berevolusi. Mungkin, karena posisinya di bawah, TAP MPR bisa lebih dinamis, dinamikanya akan lebih cepat daripada sebuah UUD 1945 dalam mengintervensi KK di seluruh Indonesia ini.
Dalam doktrin hukum, tentang hukum adat. Semua Fakultar hukum di Indonesia ada yang namanya pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, dan sebagainya yang menyatakan bahwa dasar hukum Indonesia adalah norma-norma dan pranata yang hidup dalam masyarakat, dalam bentuk hukum adat yang diakui. Itu tidak pernah menjadi suatu penilaian-penilaian untuk mencapai keadilan atau penyelesaian hukum. Saya tidak melihat dalam konsideran menyatakan menyangkut masalah- ada Hukum tentang masyarakat adat tapi bukan tentang hukum adat. Hal yang berbeda. Sebenarnya, doktrin itu sudah mati di Indonesia. Jadi, Saya rasa, kurikulum itu perlu kita tinjau kalau dalam sistem hukum kita sudah tidak diakui.
Budiman, UU itu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menguji berbagai sisi. Sehingga, kita tidak perlu mengeluarkan PP. Artinya, lebih rigid. Bukankah itu akan membuat penggemukan? UU di Indonesia sangat gemuk. Setiap sisi, setiap bidang kita atur dalam kata-kata dalam berbagai hal. Pengemukan yang terjadi. Sementara, balik ke pertanyaan Saya tadi, tentang controling, pengawasan dari UU itu sendiri. intinya di sana. Kita tidak perlu buat UU yang gemuk. Saya mau mengomentari bahwa sebuah UU itu dari norma dan pranata yang hidup dalam masyarakat. Kalau DPR bicara UU, berarti DPR hanya bicara produksi tapi tidak cari kualitasnya. Memproduksi atau kuantitatif. Terima kasih.
Moderator: terima kasih kepada para penanya dan komentator atas masukan dan pertanyaannya. Cukup banyak. Dari 8 narasumber, tidak ada yang menyampaikan satu point. Semua kombinasi pernyataan dan komentar. Supaya nanti mengarah ke pertanyaan yang diajukan, yang menarik dari Menkumham, karena terlibat dalam pembahasan UU 12/2011, usulan mengenai masukan TAP MPR bukan dari pemerintah dan juga tidak secara langsung jadi anggota DPR. Karena, ada dalam pembahasan. Sebenarnya, niat memasukkan TAP MPR ini maksudnya apa? karena keduanya tidak diusulkan, tapi masuk ke tengah-tengahnya. Mungkin Budiman bisa memberikan gambaran.
Kemudian, yang dari Komnas HAM – tapi, yang penting terkait dengan topik ini. mungkin, yang pertama karena Budiman mau pergi, Budiman lebih dulu. Kemudian, Prof Yuliandri bisa menanggapi.
Budiman Sujatmiko: terima kasih. Ada beberapa hal yang mungkin bisa Saya jawab dan Saya catatan. Saya coba merangkum. Pertanyaan Andi dari Komnas HAM, mengenai bagaimana DPR mengawal dan mengawasi isu yang berkaitan dengan reforma agraria. Saya perlu sedikit cerita bahwa fungsi DPR ada 3: pengawasan, budgeting dan legislasi. Artinya, yang bisa dilakukan DPR dalam pengawasan, mau tidak mau, diawali bicara kasus per kasus. Fungsi representasi DPR bisa diwakilkan atau diterjemahkan dalam proses fungsi pengawasan. Contoh, Saya sebagai anggota Komisi II dimana bersama BPN, ada mekanisme rapat, baik sebagai komisi maupun sebagai tim. Di Komisi II Kami membentuk sebuah tim, Tim Kerja Pertanahan yang mengumpulkan kasus-kasus pengaduan, baik dari daerah sendiri maupun pengaduan yang hadir entah itu fisik, delegasi, aksi massa maupun dokumen. Itu kita kumpulkan di staf komisi. Kita akan selalu memanggil BPN terutama deputi penyelesaian kasus. Jadi, mau tidak mau, kita bicara kasus per kasus. Tentang reforma agraria, kita mengawasi dari 2 hal: legislasi dan budget. Dari segi legislasi, kita bicara soal inisiatif atau pengawalan terhadap pihak-pihak yang berkompeten yang berkaitan dengan komisi. Saya harus akui, seluruh kaitan dengan pertanahan, tidak semuanya hanya komisi II. Bahkan, tidak semua dari pengawasan, karena berkaitan dengan Komisi IV untuk kehutanan, kelautan, perkebunan, dan juga Komisi VI untuk infrastruktur dan beberapa lagi yang berkaitan dengan pertanahan tapi tidak berada di bawah pengawasan Komisi II.
Berkaitan dengan kerja soal UU Pengadaan Tanah. Terus terang, terjadi tarik menarik dengan pemerintah dan juga dalam partai atau faksi sendiri, antara pihak yang ingin memberikan kewenangan luas dengan yang tidak. Akhirnya, kompromi. Dalam UU Pengadaan Tanah, Saya tidak masuk pansusnya. Memang di situ kita berhasil mendorong konsensi bahwa swasta tidak lagi berwenang –kekuatiran kita- melakukan pembebasan tanah. kedua, Ganti rugi tanah untuk infrastruktur diberikan bukan kepada pemegang hak tapi yang berhak. Karena, sering kali apa yang disebut sebagai pemegang hak secara formal sebenarnya tidak berhak atas tanah itu karena memang dulu mendapatkan proses pemegang hak melalui proses-proses di masa dulu. Sehingga, kata-katanya “yang mendapatkan ganti rugi bukan lagi pemegang hak yang secara formal memegang surat tapi yang berhak sesungguhnya atas kepemilikan tanah. Juga, ditekankan bahwa kalau dalam proses pembangunan infrastruktur pemerintah bersama swasta karena modal, seperti jalan tol, maka selama fungsi komersial, masyarakat setempat harus diikut sertakan sebagai pemegang saham jika jalan tol masih dijalankan oleh swasta komersil. Tapi ketika dikembalikan kepada negara, tidak lagi dikelola swasta, maka saham rakyat tidak lagi berlaku. Kita kompromi di sana. Satu sisi, infrastruktur tetap terbangun. Tapi di sisi lain, masyarakat juga tidak dicampakkan karena pemegang saham. Ganti ruginya pun tidak lagi semata berdasarkan hitam di atas putih tapi harus ada prosesnya. Itu achivement yang kita desakkan dalam UU Pengadaan tanah. Artinya, proses-proses itu kita coba mulai dari kasus per kasus untuk kita kaji terutama proses legislasi baik yang inisiatif pemerintah maupun DPR.
Kemudian, soal reforma agraria pada konstitusi. Saya tertarik sekali dengan usulan itu. mungkin suatu saat perlu kita bicarakan, bagaimana itu menjadi konstitusi. Karena biasanya konstitusi di berbagai negara secara detail juga membahas soal bentuk-bentuk ekonomi untuk mengakomodasi aspek kerakyatan yang dipilih.
Tadi, dari Rahma soal UU Pengadaan Tanah sudah Saya singgung sedikit. memang selama ini, para pengusaha sangat berkepentingan sekali. Saya harus akui di dalam fraksi PDIP ada proses tarik menarik. Ada orang-orang dari fraksi yang ditugaskan untuk memimpin di sana, tidak memberikan laporan secara rutin ke Fraksi. Tidak memberi laporan kepada Fraksi Kami tapi mungkin pada Fraksi yang lain. Serius! Kita ada evaluasi. Ternyata, setelah perkembangan seperti ini, kita tegur, kita evaluasi pimpinannya yang juga dari Kami karena tidak ada laporan rutin kepada pimpinan fraksi atas perjalanan RUU ini. Seperti kita ketahui, banyak kebobolan. Kemudian, pemerintah ditekan untuk mengikutsertakan rakyat dalam saham ketika infrastruktur dikelola oleh swasta. Itu perjuangan fraksi Kami untuk meminimalisir dampak negatifnya. Kalau tadi Prof. Yuliandri menyatakan kita bawa secara formail tidak mencantumkan TAP MPR No. IX/2001, mungkin ini masih terbuka untuk teman-teman.
Tadi, pertanyaannya, sebenarnya bagaimana proses gagasan RUU menjadi UU. Harus diakui bahwa ini semuanya proses politik, proses lobi, penekanan, apapun. Untuk memasukkan RUU ke prolegnas bisa dari cara yang canggih, pembentukan opini, konferensi, survey, lobi, atau sekadar mencegat kepala baleg ketika keluar dari toilet. Itu tergantung mood-nya. serius! Bisa seperti itu. Kita sudah menggagas aksi massa, membangun opini, survey, dan sebagainya. Tapi, akhirnya banyak, bisa terlupa begitu saja. Orang tidak selalu membaca media. Sehingga, ketika rapat tidak muncul. Keluar toilet, ajak makanlah. Memang sangat tricky, mulai dari gagasan besar sampai teknik yang tidak wajar, keluar dari toilet, ngopi, tolong prioritas ini dimasukkan, kemarin lupa. Saya ingatkan kemarin tim ini pernah bicara ini. ya, masukkan.
Noer Fauzi: operator saja.
Budiman Sujatmiko: ini soal operator. Ini politik real, baik DPR maupun partai politik. Politik ada ditentukan map ada diletakkan dimana. serius seperti itu! calon legislatif anggota DPR bisa hilang, karena mapnya hlang. Dampaknya sangat besar tapi prosesnya bisa sangat teknis. Kekuasaan itu bisa menjadi penting, karena politik itu jalan cepat menuju surga atau neraka. Itulah prosesnya, sangat teknis, tidak ada teorinya. Tidak tahu soal birokratik, soal promosi jabatan. Di politik seperti itu, makan keluar, lobi, naikkan sekian. Atau, terakhir, rapat terakhir, sudah masuk, revisi UU 13 tentang ketenagakerjaan. Saya baca. Tapi, teman-teman advokasi dari komisi IX, teman-teman lain buruh jadi komisi balkon dan yang di luar aksi besar. Akhirnya, tidak ada lagi, revisi UU 13/93 dicabut. Itu dalam sidang terakhir.
Proses undang-undang yang lain, misalnya BPJS. kita bisa menunda berkali-kali. Itu yang terjadi dengan undang-undang ini. Berkali-kali dilakukan menteri tidak pernah datang. Soal PU, UU Demonstrasi, berkali-kali. barulah nanti di pembukaan, KOMPAS mengulas dalam laporan khusus Kami, baru menterinya mau datang. Tadinya, berapa kali rapat menteri-menteri tidak mau datang. Jadi, satu bahaya UU inisiatif DPR adalah menteri tidak pernah datang dalam rapat pembahasan bersama. contoh, UU Pembangunan Desa 2004-2009. ini inisiatif DPR. Semua fraksi sudah sepakat, bahkan menteri dalam negeri sudah sepakat tapi menteri keuangan tidak sepakat. Gagal juga, tidak jadi. Sampai sekarang, pemerintah minta depdagri tidak bisa. Mendagri katakan akan berikan surat amanat presidennya untuk dibahas di DPR. Bahkan, sidang kabinet sudah memutuskan. Sehingga, mendagri sudah memberikan draft UU Pilkada dan UU Desa, sudah diberikan kepada SBY. Tapi, SBY hanya tanda tangan UU Pilkada untuk dibahas di DPR. UU Desa yang sudah diserahkan menterinya, tidak ditandatangan. Saya dengar informasi, ada kekuatiran, jika ada UU desa maka akan terbuka terjadi manipulasi suara, menggandakan jumlah desa. Dalam UU Desa kan akan ditetapkan, berapa jumlah desa sebenarnya. Karena, ini bicara anggaran. Desa alokasi anggarannya berapa. Nanti akan ditetapkan dalam UU, desa seperti ini, setidaknya dalam pembahasan. Nanti akan terbongkar, ada juga pembengkakan desa untuk pilpres kemarin. Pemerintah takut di situ. jadi, ada persoalan yang harus kita cermati. Tema politik bisa dikaitkan dengan soal-soal lain yang tidak ada hubungannya dengan naskah akademik atau concern kita di sini. Dinamika pembahasan UU bisa seperti itu.
Kemudian, Stedy, pertambangan, sikap DPR. Kami di Komisi II, Saya tidak bisa bicara yang lain karena yang berkaitan dengan pertambangan adalah Komisi VI, sudah membicarakan agar diadakan review HGU. Seluruh HGU, kita review. Prosesnya bagaimana? sah atau tidak? Kalau tidak sah, dicabut. Lihat, moratorium HGU di tingkat BPN atau pertambangan, Saya tidak tahu. Komisi II sepakat ada review terhadap HGU. Soal apakah dia PDIP atau bukan, akan Saya cek. Karena sekarang susah juga mengukur apakah sebuah policy itu benar-benar menterjemahkan-. Karena bisa satu bupati dari partai yang sama, dengan Bupati lain dari partai yang sama, dengan forum yang sama, penanganannya bisa berbeda, bisa sangat bertentangan. Bisa seperti itu karena belum ada standarisasi secara value. Saya tidak tahu tentang moratorium pertambangan. Kalau soal perkebunan rencananya akan kita review .
Soal pelaksanaan di lapangan, Saya sepakat soal pelaksanaan di lapangan. Tapi, kita hidup di sebuah negara yang mengakui konsitusi, sistem. Kita mengakui bahwa kita masih dalam rangka reformasi bukan revolusi. Saya sepakat ada dinamika di dalam sistem. Tapi, di luar sistem juga ada. Kalau dinamika di luar sistem akibatnya bisa ada konflik sosial, kekerasan, ada orang mati. kalau dinamika di dalam sistem paling hanya teriak ha hu ha hu saja, tidak perlu ada orang mati. kita masih butuh sistem ini.
Pelaksanaan, unsurnya banyak, unsur pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, perimbangan kekuatan politik. Maka, Saya tidak bosan-bosan katakan, aktifis jangan alergi kekuasaan, jangan alergi politik, jangan alergi partai. Masukklan ke DPR, DPRD, jadilah Gubernur, jadilah Bupati, mencalonkan presiden. Karena di titik-titik itulah terjadi policy making. Persis di titik-titik itu ada kebijakan TAP MPR, UU, apapun. Itu proses yang ada karena sistem. Moncongnya, sistem. Supaya ada UU pro-rakyat, itulah sebaiknya aktifis jadi DPR, jadi Gubernur, Bupati, atau Presiden. Seperti Rieke Dyah Pitaloka, Saya dukung untuk maju jadi Gubernur Jawa Barat. Bagus sudah berjuang di bpjs. Berjuang menjadi Gubernur Jawa Barat, kenapa tidak. Saya harap suatu saat teman-teman mencalonkan diri dari DPR, Bupati, DPRD. Kemudian, punya perhatian terhadap perkebunan, pertambangan. Apalagi, teman-teman dari gerakan, masyarakat yang terorganisir. PARADE Nusantara punya gagasan “lumbung suara desa”, 2014 mengangkat mantan kepala desa menjadi DPRD kabupaten agar bisa mengeluarkan perda-perda yang bisa meningkatkan alokasi terhadap desa. Tahun 2009, Kita coba di Madiun, 36 dari 45 anggota DPRD dari parade Nusantara tapi disebar di beberapa partai. Akhirnya, masing-masing mendorong pembangunan alokasi dana desa. Tahun 2014, kita harapkan gerakan ‘Lumbung Suara Desa’ ini tidak hanya di kabupaten Madiun tapi di semua kabupaten yang ada PARADE Nusantaranya, kebetulan 352 kabupaten. Tahun 2014, kita jadikan mantan kepala desa menjadi calon DPRD kabupaten. Kita pikirkan, tidak cukup untuk menjadi DPRD, DPR juga. Saya sedang menghubungi teman-teman aktifis, profesional yang mau jadi anggota DPR RI. Kalau mau, turun, kabupaten ini, ini basis desanya, kepala desanya, garap selama 2 tahun. Partainya terserah. Misalnya, Usep dari Garut atau Cirebon. Ya sudah, kalau mau Cirebon ini ada data 40 kepala desa yang mencalon DPRD tingkat II.
Moderator: itu dari berapa?
Budiman Sujatmiko: kalau desa di Indonesia ada 68.000 desa. Jawa, sekitar 24.000 desa. Satu desa kalau di Jawa, sampai 100%, rata-rata dengan 6.000 penduduk, misalnya. Sebusuk-busuknya kepala desa 20% penduduk desa akan bergabung. Mereka rata-rata sudah menang 2 kali, jadi menanglah. Tapi, dia mencalon DPRD, lawannya dari luar desanya, otomatis dia menang. Ketika Usep mau mencalonkan diri, aku kasih data 60 kepala desa di kabupaten Cirebon, namanya, alamat, dan nomor handphone-nya. Garap sejak sekarang, 2 tahun. Pasang stiker fotomu di setiap rumah kepala desa, pasti menang. Saya sudah membuat gerakan “Lumbung Suara Desa”itu. kita akan gabung dengan AMAN, teman-teman kelompok petani untuk beberapa daerah. Sayang, orang mengeluh masuk politik, biayanya milyaran. Aktifis, tidak punya uang. Sekarang, ada social network, manfaatkan. Kita coba di kabupaten Madiun. 2014 kita akan coba di setidaknya 300 kabupaten tapi dengan tandemnya DPRD Propinsi dan DPR RI. Partainya nanti kita tentukan 2013.
Noer Fauzi: Nasdem
Budiman Sujatmiko: tidak harus. Tidak harus PDI juga. mungkin kita pilih partai kecil saja yang kosong. Partai besar sudah banyak penumpangnya. Partai yang kosong tapi begitu kita isi, kita isi dengan aktifis-aktifis DPR. Karena, sudah cukup 13 tahun kita memberikan kepada orang yang tidak bisa mereformasi Indonesia. Sekarang, kita mengambil alih itu. Tapi, karena tidak punya uang, kita gunakan gerakan. Itu saja yang Saya sampaikan. Terima kasih. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Saya mohon pamit.
Moderator: terima kasih. beri applause kepada Budiman.
Karena dari sisi waktu sangat sempit, Saya minta Profesor Yuliandri memberikan respon balik. Tapi mungkin ringkas-ringkas saja.
Prof. Yuliandri [Universitas. Andalas]: terima kasih. pertama, dari mas Andi dari Komnas HAM, lalu Reza dan Mardi. Ada satu hal yang bagi Saya mengganjal. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Zaenal dari KPA. Kita harus paham, prinsip draft itu apa. Secara hirarki, makna hirarki dalam perundang-undangan harus dijelaskan. Misalnya, UU 12 ini menjelaskan UUD adalah ini, UU adalah ini. Tapi, di TAP MPR tidak menjelaskan tapi menunjuk. Kalau hanya sebatas itu tidak pada hirarki tapi ada pasal dalam UU itu yang memberikan justifikasi bahwa UU ini juga mengakomodasi secara substansi terhadap TAP no. I tahun 2003. Tap MPR itu kok menunjuk. Itu aneh, keluar dari forma standar yang ada di pikiran kita. Sekarang, kita lihat dia sebagai bagian hirarki. Konsekuensinya apakah ketika TAP ini dibentuk, sekarang saja lembaga yang membentuk dalam sistem negara kita sudah salah. kok tiba-tiba di UU lain beda. Saya lihat, problemnya bukan di wajib masuk atau tidak, tapi esensinya. Ini sudah menjadi keputusan politik, implikasinya yang harus disikapi. Tadi, Saya kasih contoh saja. Kalau kita mau menampung semua, kenapa ordonansi tidak dimasukkan? ordonansi punya arti penting. ordonansi punya kedudukan yang jelas, walaupun sekarang tidak disebut.
Problem kita sebetulnya, UU ini membuka peluang kepada semua lembaga pemerintah untuk mengajukan rancangan UU. Tapi, tidak jelas siapa yang menjadi koordinator. Katakanlah, Depkumham sebagai pintu akhir untuk melakukan harmonisasi dan siskronisasi. Tapi, ini tidak jalan ketika dia tidak tahu substansinya, tidak bisa dicover semua. termasuk problem utama, yang ada khususnya insiatif pemerintah. Karena, substansi, beda-beda orangnya. Celakanya, ketika orang yang mengawal tidak paham apa yang diusulkan. Maka, menjadi problem dari segi administrasi. Maka, kita tahu ketika UU sudah jadi, begitu kan Reza, ada tim sinkron dan tim harmonisasi. Tapi, ini tumpul. Itu yang Saya pahami.
Menurut Saya, kita mesti –sama seperti yang disampaikan Budiman soal target prolegnas. Pernahkah kita bayangkan di tahun 2011, ada UU Resi Gudang. Resi Gudang, UU itu tidak pernah masuk prolegnas di 2010 untuk 2011. Tiba-tiba 2011 itu masuk. Resi gudang ini, suatu UU yang prospek sekali ke depan, belum sekarang. Misalnya, ada petani yang punya gabah, sekian ribu ton. Gabah disimpan di satu gudang. Pemilik gudang akan mengeluarkan resi. Resi bisa menjadi surat berharga dan berpindah-pindah. Kita belum urgent. Tapi, kemudian ini jadi. Menurut Saya, sekarang bagaimana kita mengawal substansi setiap UU yang menurut kita urgent dan dibutuhkan dengan substansi yang benar.
Bagaimana melakukan harmonisasi? Ini memang pekerjaan besar. Kenapa? Karena sekarang masing-masing undang-undang itu saling posisi tawar masing-masing. Maka, tadi ada UU yang basah, ada yang kering. Maka, semua tergantung masing-masing lembaga pemerintah. Sama dengan tadi, bagaimana kita melihat hubungan atau keterkaitan antara UU satu dengan UU yang lain, bagaimana melihat UU yang satu lex specialist terhadap UU yang lain. Saya ambil contoh, berkaitan dengan pertanyaan Mardi. Untuk melakukan prinsip-prinsip perundang-undangan, lex generalis – lex specialis, harus dengan UU wewenang yang sama, tidak bisa dengan yang lain. kita bisa lihat, bagaimana kita mengatakan suatu UU dalam bidang sumber daya specialis dengan yang lain atau tidak. Saling mengatur hal yang sama walaupun sttingnya beda-beda. Ini juga menjadi problem. Maka, yang penting, pertama, kita harus memperbaiki mekanisme usul, siapa yang mengajukan RUU. Betul masing-masing departemen bisa mengawal. Kemudian, bagaimana peran Depkumham tetap sebagai departemen yang mengawal terhadap hirarki hukum terhadap UU yang diajukan oleh masing-masing departemen. Kemudian, bagaimana mengefektifkan proses harmonisasi. Ini kuncinya. Kalau tidak dilakukan, kita akan non sense saja. Berlombalah orang untuk mengajukan berbagai RUU yang kadang-kadang menurut kita tidak urgent untuk kondisi sekarang.
Kenapa isi TAP tidak menjadi UU. Ini problem. Karena beda antara TAP yang menjadi UU HAM dengan TAP no. IX. Karena, TAP no. 9 tidak langsung menunjuk. Dia hanya mengatur tataran kebijakan. Ini yang mesti dilakukan. Kemudian, mendorong harmonisasi peraturan di bidang sumber daya alam. Ini kan luas. Kalau HAM kelihatan simpel. Dalam arti, substansinya bisa dipetakan. Itu bedanya. Ini beberapa hal yang Saya sampaikan. Terima kasih.
Moderator: terima kasih Prof. Yuliandri. Terakhir, Bang Oji.
Noer Fauzi: masalahnya untuk menghapus UU Pokok Agraria, Saya punya keberatan yang sangat. Karena ini adalah satu-satunya perundang-undangan yang secara ideologis menegaskan kembali sedimen negara bangsa dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dalam prinsip tanah punya fungsi sosial, social function of the land. Tidak ada UU lain yang menyatakan prinsip seperti ini. Masalah pokoknya adalah ketidakmampuan dari bagaimana prinsip fungsi sosial atas tanah ini diwujudkan oleh pemegang mandat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau di tengah kedigdayakan pasar sekarang dibuka pintu untuk mengganti perundang-undangan ini, maka itu akan hilang. Di banyak contoh, seperti yang terjadi di Mexico, begitu dibuka perubahan –bukan hanya pada perundang-undangan- pada konstitusi, maka yang terjadi adalah UU yang menyatakan fungsi sosial atas tanah, maaf, Pasal 27 Undang-undang Dasar yang menyatakan tanah punya fungsi sosial dan harus ada redistribusi tanah, hilang dari konstitusi mereka. Itu akibat langsung, dari proses pengintegrasian meksiko dalam koalisi NATA, North America trade are.
Sekarang, digdaya pasar ini bukan hanya proses restrukturisasi. Kedudukan Indonesia dalam kaitan dengan ASEAN, kaitan hubungan dengan China, India, Asia Pasifik, tapi juga kedigdayaan pasar sudah masuk ke pikiran para legislator. Saya disuplay oleh teman-teman seperti Budiman di DPR. Dari ratusan perundang-undangan yang dihasilkan, orientasi liberalismenya besar sekali dibandingkan yang Saya hadapkan dengan orientasi mengunakan konstitusi dan paham koberalisme sebagai cara berpikir untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini, mewujudkan keadilan sosial seperti pada pembukaan UUD 1945. Komitmen para legislator, lebih-lebih komitmen eksekutif negara terhadap pasar sudah begitu kuat. Mereka lebih banyak menjadi warga pasar daripada warga negara. Kok bisa begitu? Contohya, pada praktek aparatus keamanan, praktek-praktek legislasi. Keduanya punya kewenangan monopolisitik dari negara. Mereka bisa lakukan itu untuk pasar, korporasi besar, ketimbang menjadi negara yang menegaskan pelindungan terhadap warga negaranya. Sebaliknya, ketika aspirasi rakyat direpresi, ketika produk legislasi menghancurkan akses dan kontrol rakyat dari sumber daya alam tempat dia hidup, maka jalur transformasi dari penduduk menjadi warga negara putus. Mereka menjadi anti negara. Kesempatan mentransformasi diri dari penduduk menjadi warga negara ditutup. Banyak penduduk Indonesia yang belum jadi warga negara dalam arti –bukan keimigrasian tapi dia harus dilayani hak-hak dasar. Hak untuk punya hak sebagai warga negara Indonesia yang punya constitutional right. Kewajiban-kewajiban dalam hal ini, kalau menggunakan kosnep HAM state obligation, kewajiban itu adalah transformasi berlangsung. Dari populasi, warga etnik, warga tempatan, warga agama menjadi warga negara. Jalurnya putus, bahkan dihambat sehingga mereka bersikap anti terhadap negara, anti legislasi, anti aparat birokrasi, anti aparat polisi dan keamanan, dan kemudian meneriakkan aspirasi kemerdekaan. Aspirasi kemerdekaan ini, adalah sesuatu yang universal. Kalau kita telusuri lebih jauh, negara kolonial.
Maka, menurut Saya, tidak ada jalan lain selain gerakan sosial mengembangkan kemampuannya yang berasal dari ketidakpuasan terhadap praktek-praktek negara. tapi, di pihak lain, merebut kembali, mere-edukasi, membuat proses yang monopoli lembaga negara yaitu birokarsi, legislasi, aparat keamanan menjadi birokrasi konstitusi, pemegang mandat konstitusi. Dalam hal ini, ultimately yang berteguhkan pada keadilan sosial. keadilan sosial tidak bisa dicapai tanpa menggunakan itu, keadilan sosial sebagai prinsip. Salah satu prinsip keadilan sosial itu pada penguasaan tanah dan sumber daya alam. Maka, tanah menjadi central yang sudah lama ditinggalkan. Kalau itu kita buka untuk diganti, maka pemikiran pasar yang mendominasi dari para legislator kita, eksekutif kita akan melindas semua sedimen nasionalisme yang berlangsung selama 20 tahun, 45 sampai 65. ini adalah sisa paling akhir.
Sebaliknya, Saya memanggil kita semua membuat paham konstitusi untuk menjadi pegangan dasar. Tahun 67-98 konstitusi ini dipandang sebagai sesuatu mensakralkan konstitusi tapi konstitusionalisme tidak pernah dikembangkan menjadi alat pendidikan sehingga warga negara paham hak-haknya. Kemudian, liberal, tahun 97 segala hambatan negara yang otoritarian di desentralisasi. Maka, sekarang arus pasar bekerjasama dengan demokrasi dan desentralisasi. Jadi, jangan membuat anggapan liberalisasi dan desentalisasi itu sesuai aspirasi rakyat. Kita lihat praktek di lapangan keduanya kerjasama dengan kekuatan pasar. Desentralisasi dan demokrasi, para oligar yang bekerja dengan prinsip pasar mampu menyesuaikan diri dan bisa kerja efektif dalam alam demokrasi. Berarti, korupsi makin besar, perampasan tanah lebih banyak, pemanfaatan negara sebagai alat modal semakin besar. Itu yang belum cukup dipahami oleh banyak pemegang mandat. Maka, Saya mengundang kita semua memikirkan jalur transformasi baru, bagaimana bisa mencegah sektoralisme menguat dari perundang-undangan maupun kelembagaan, HAM belum jadi pegangan dimana tranformasi dari penduduk ke warga negara dilayani pemenuhan HAM itu. sebaliknya, birokasi, keamanan, Legislasi digunakan pasar yang counter-revolusi, tandingan, terhadap proses transformasi. Kalau pasar dipegang sebagai kerja dari pemerintahan, keamanan, legislasi, maka yang ada adalah reaksi tanding, sifat protektif masyarakat terhadap tanahnya. Itu yang terjadi di Papua. Ini krisis yang kronis dan meledak-ledak dari waktu ke waktu. Jangan dipahami saja yang terjadi di Mesuji atau tempat lain sebagai eksplosi perlakuan pemerintah, tapi dia adalah eksplosi dari landasan yang sifatnya sudah menahun, kronis. Neokolonialisme sudah dikukuhkan melalui praktek dimana menggunakan pemerintah sebagai instrumen. Saya menggunakan proses seperti ini supaya kita punya dorongan untuk memahami ini dalam konteks membangun kembali konstitusionalisme. Tidak ada jalan lain. Konstitusionalisme harus dihidupkan kembali, harus didasarkan atas sejarah dan perbedaan geografis dimana kepulauan Indonesia ini memang beragam sekali. Terima kasih.
Moderator: terima kasih untuk mengakhiri jawaban karena sempitnya waktu. Bapak Ibu sekalian. Tiga narasumber sudah menyampaikan komentar balik dari komentar dan masukan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dalam diskusi ini kita bisa kembali ke kerangka awal diskusi ini dari teman-teman HuMa. Sosialisasi, menginformasikan bahwa TAP MPR sudah masuk dalam hirarki. Tapi, membongkar isi dibalik masuknya TAP MPR, apakah bisa jadi peluang bagi advokasi ke depan. Tadi, analisanya banyak. Ternyata, di internal DPR ternyata tidak satu suara. Ini tetap jadi tantangan. Oji katakan, kita harus waspada pada dominasi pasar. Waspada harus di-double-kan. Karena Pasar bisa kerja di rejim yang sosialis sekalipun apalagi yang demokratis yang memberi ruang cukup banyak. Itu terakhir dari Saya dalam memandu proses dialog ini. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih dan applause untuk kita semua.
Mc: bagi teman-teman, sudah disediakan makan siang di restoran dengan membawa voucher. Bagi yang belum dapat bisa memintanya kepada panitia. Terima kasih.


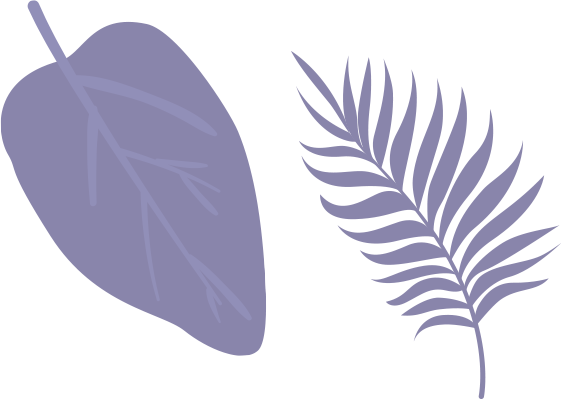
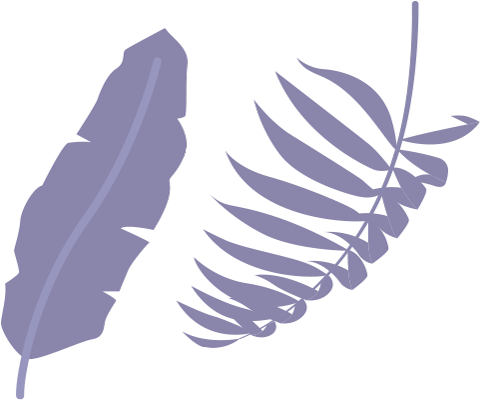
3 Komentar
Tinggalkan Balasan