Jakarta, 17 Desember 2013. Indonesia tengah berada di persimpangan jalan. Komitmen SBY untuk menurunkan emisi sebesar 26% atau 41% dari kondisi bisnis seperti biasa pada tahun 2020 sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 7% mulai dipertanyakan oleh masyarakat sipil, terlebih ketika kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang tercakup dalam Perpres No. 88/2011 atau MP3EI, justru mengancam keberadaan hutan Indonesia yang tersisa, yang merupakan tumpuan hidup puluhan juta penduduk, termasuk masyarakat adat dan lokal. Janji Pemerintah untuk ‘menghijaukan’ MP3EI pasca-protes masyarakat sipil pun belum terlihat sementara Pemilu sudah di depan mata. Berdasarkan analisis HuMa dan 23 organisasi lain yang terlibat dalam jaringan pendokumentasi konflik, kerusakan lingkungan dan konflik agraria diperkirakan akan meningkat menjelang tahun politik seiring maraknya transaksi ekonomi-politik untuk mencapai kursi kekuasaan. Dalam hal ini, daerah menjadi medan pertempuran penting karena di tingkat inilah konsesi eksploitasi SDA banyak dikeluarkan secara masif menjelang pemilu.
Kebijakan Pemerintah untuk menurunkan emisi dari kerusakan hutan yang dikenal dengan REDD+ kini berjalan di tengah inkonsistensi kebijakan di atas. Satu setengah tahun telah berlalu sejak janji untuk memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia dimaktubkan dalam Strategi Nasional REDD+ yang diluncurkan pada bulan Juni 2012. Setelah sekian lama, kelembagaan REDD+ yang diharapkan dapat segera menjalankan Stranas pada akhirnya dibentuk, namun kewenangannya dibatasi dan pemimpinnya pun tidak kunjung diumumkan sehingga Badan REDD+ tampak tertinggal dalam berbagai proses kebijakan yang saat ini mulai bergulir.
Stranas REDD+ mulai diturunkan ke dalam Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) untuk mengimplementasikan REDD+ di tingkat daerah. Konsistensi substansi SRAP dengan Stranas sekaligus kemampuan untuk merangkai solusi atas persoalan kehutanan di daerah dalam strategi aksi yang konkrit merupakan harapan utama yang ditaruh ke pundak SRAP. Dalam konteks ini, Perkumpulan HuMa memeriksa secara menyeluruh substansi SRAP di tiga Provinsi: Sumatera Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah, khususnya terkait isu hak masyarakat adat dan lokal. Analisis awal menunjukkan beberapa temuan penting, di antaranya tidak dimasukkannya proyeksi deforestasi dan potensi kehancuran lingkungan dan hutan akibat MP3EI, sebagaimana dalam SRAP Sulawesi Tengah.
“SRAP Sulteng tampak lebih merefleksikan persoalan lingkungan hidup masa lalu,” kata Martje Leninda, Direktur Perkumpulan Bantaya. “Bagaimana rencana kongkrit Pemda untuk mengurangi deforestasi sekaligus menyelesaikan konflik kehutanan di wilayahnya ketika dihadapkan pada proyek-proyek MP3EI yang justru berpotensi menambah konflik baru?”
“Meski Sulteng menjadi provinsi percontohan REDD+, ekspansi tambang mengalami peningkatan luar biasa,” ujar Rifai Hadi, Manajer Kampanye Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah. “Di tahun 2013, ada 356 Izin Usaha Pertambangan dengan luasan 1,5 juta hektar, belum menghitung jumlah Kontrak Karya dan industri LNG.”
Selain itu, ekspansi sawit di Sulteng pun mengkhawatirkan. “Di atas kertas, HGU sawit di Sulteng sudah mencapai 94.000 hektar. Di Morowali saja, dalam 5 tahun terakhir terjadi ekspansi sawit sebesar 100%,” ujar Ahmad, Direktur Walhi Sulawesi Tengah.
Selain itu, ada juga persoalan basis hukum yang kurang kuat. Wadah hukum SRAP yang hanya berupa Peraturan Gubernur menyulitkan implementasi SRAP karena tidak bisa mengalahkan Perda yang menjadi dasar hukum eksploitasi SDA di Sulteng. “Pergub adalah baju yang kekecilan untuk menampung postur persoalan yang seharusnya dituangkan dalam produk hukum yang lebih tinggi,” ujar Azmi Sirajuddin dari Yayasan Merah Putih (YMP) Palu. “Kelemahan lain SRAP di Sulteng adalah dokumen ini hanya familiar di level provinsi, namun tidak diketahui di level kabupaten/kota. Ini menyebabkan kurangnya dukungan dari pemkab/pemkot yang ada di Sulteng terhadap dokumen SRAP dan implementasinya ke depan,” ujarnya lagi.
Andreas Lagimpu, Anggota Utusan Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional Regio Sulawesi, mengingatkan bahwa program REDD+ di Sulteng harus serius mengembangkan dan mendukung model pengelolaan hutan lestari oleh komunitas. “Masyarakat adat dan lokal memiliki pengetahuan dan tertib sosial sendiri untuk mengelola dan melindungi hutan sehingga adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain LSM, kalangan akademisi pun mengkritisi MP3EI. “Penyusunan MP3EI dan penentuan aktivitas-aktivitas pembangunan di regio tidak melalui studi yang baik” kata Prof. Dr. Deddy Hadriyanto, M. Agr., Kepala Center for Climate Change Studies Universitas Mulawarman. “Padahal MP3EI belum hijau, namun sudah diadopsi oleh Gubernur.”
Rully Darmadi dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menambahkan bahwa MP3EI berpotensi menambah transaksi politik yang merusak dan konflik. “Selama ini, terbukti bahwa menjelang Pilkada, izin-izin eksploitasi SDA cenderung meningkat,” imbuhnya.
Sementara itu, di Sumatera Barat, yang menjadi elemen unik dalam SRAP adalah promosi hutan Nagari sebagai strategi REDD+. “Pengelolaan hutan Nagari berbasis pada kelembagaan adat dan pengetahuan tradisional. Selain mencegah deforestasi, pengelolaan hutan oleh Nagari juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari serta menyelesaikan konflik kehutanan yang terjadi di masa lalu,” ujar Rainal Daus, Manajer Proyek dari KKI-Warsi.
Akan tetapi, perlu dukungan kelembagaan yang kuat untuk menjalankan terobosan ini. “Tanpa dukungan kelembagaan dan personel yang kuat, Nagari akan tetap mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan izin yang merusak dan menimbulkan konflik. Apalagi bila izin tersebut merupakan bagian dari ongkos politik lokal,” ujar Naldi Gantika, Manajer Program Penyelesaian Konflik Perkumpulan Qbar.
“Pemerintah pusat maupun daerah harus segera mengakhiri inkonsistensi kebijakan penyelamatan hutan melalui REDD+ dan MP3EI yang eksploitatif,” ujar Anggalia Putri, Koordinator Program Perubahan Iklim Perkumpulan HuMa. “Tanpa konsistensi kebijakan pembangunan yang lebih luas, REDD+ tetap akan menjadi pulau kecil yang terisolasi, bahkan mungkin pada akhirnya akan tenggelam.”***
Kontak Media:
1. Anggalia Putri, Koordinator Program Kehutanan, Perubahan Iklim, dan Hak Komunitas Perkumpulan HuMa,anggaliaputri@gmail.com, 08562118997.
2. Martje Leninda, Direktur Perkumpulan Bantaya, Sulawesi Tengah, martjeleninda@gmail.com, 085243274832.
3. Andreas Lagimpu, Anggota Utusan Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional Regio Sulawesi,andreas_yth2006@yahoo.com, 081341047373.
4. Azmi Sirajuddin, Koordinator Program Hutan & Perubahan Iklim Yayasan Merah Putih (YMP) Palu, azmiss@gmail.com; 081245038678
5. Rainal Daus, Manajer Proyek KKI-Warsi, gumesrain@gmail.com, 081363181880
6. Naldi Gantika, Manajer Program Penyelesaian Konflik Perkumpulan Qbar, gantika74@yahoo.co.id, 081266425282
7. Prof. Dr. Deddy Hadriyanto, M. Agr., Kepala Center for Climate Change Studies Universitas Mulawarman,d_hadriyanto@yahoo.com; dhadriyanto@gmail.com, 081254440817.
8. Rifai Hadi, Manajer Kampanye Jatam Sulawesi Tengah, fhayhadi@gmail.com, 085256248909.
9. Ahmad, Direktur Walhi Sulawesi Tengah, pelor_forest@yahoo.co.id, 081354311740


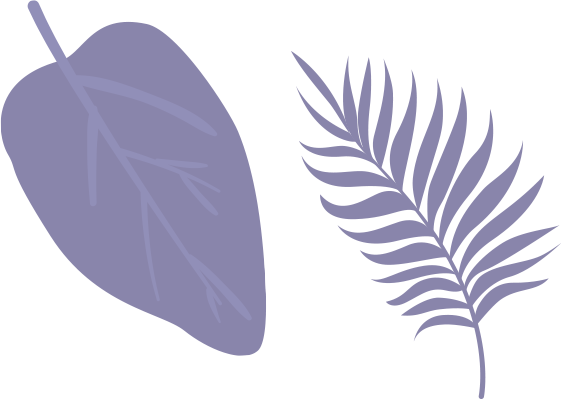
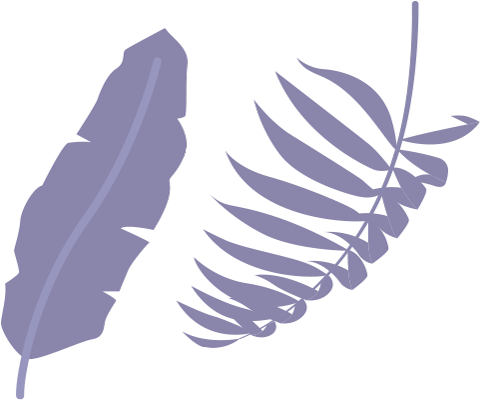
0 Komentar
Tinggalkan Balasan