Untuk memotret sebuah dusun kecil bernama Ngrimpak dapat kita lihat melalui sejarah dan perspektif sosio-kultural yang ada. Sejarah dalam masyarakat Jawa, dianggap berasal dari sejare-jare (katanya-katanya)—sebuah pernyataan kirata (dikira-kira, tetapi nyata). Sejarah masih diselimuti unsur-unsur legenda dan mitologi, yang sangat kuat tanpa ada tahapan heuristik dan kritik yang lebih mendalam. Namun begitu, kekuatan mitos/legenda (power of myth) sebagai poros utama dalam penanaman nilai-nilai warisan di kampung halaman masih ada sampai saat ini.
Ngrimpak terletak di Desa Lowungu Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Secara administratif, Lowungu berjarak 11 km dari ibukota Kecamatan Bejen dan 37 km dari ibukota Kabupaten Temanggung. Sebelah utara Desa Lowungu berbatasan dengan Desa Prangkoan, di sebelah barat dengan Desa Bendungan, sebelah Timur dengan Desa Larangan Luwok dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lembuyang. Topografi Ngrimpak sendiri berbukit sedang dengan suasana udara cukup sejuk di ketinggian 695 mdpl.
Ngrimpak juga besar lewat budaya dan kental dengan sejarahnya. Sejarah punya cerita, Temanggung selalu dikaitkan dengan raja Mataram Kuno yang bernama Rakai Pikatan. Nama Pikatan sendiri dipakai untuk menyebutkan suatu wilayah yang berada pada sumber mata air di sekitaran Temanggung. Sejarah Temanggung mulai tercatat pada Prasasti Wanua Tengah III Tahun 908 Masehi yang ditemukan penduduk dusun Dunglo Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Temanggung pada bulan November 1983.
Secara sosio-kultural, masyarakat Ngrimpak merupakan masyarakat dalam masa transisi, karena merupakan masyarakat yang mengalami migrasi besar-besaran dari Kerajaan Mataram. Migrasi besar-besaran itu lebih tertuju pada masalah ekonomi. Tidaklah heran jika, “modal dasar” (sumber daya alam) sangat dijadikan acuan utama dalam menyambung hidup.
Hutan dan pedalaman tak hanya memperdengarkan suara seruling, tapi juga jadi unggur api pembakaran yang ganas, revolusi dan cinta tercipta di dalamnya, seperti dengan indahnya dituliskan oleh Ramadhan K.H. dalam sebuah puisi panjang tentang Priangan. Dan kita pun hidup dengan trauma. Kita hidup dengan kecemasan atas hutan.
Mata pencaharian masyarakat Ngrimpak rata-rata adalah bertani. Mereka memanfaatkan lahan subur yang diapit oleh tiga gunung, yaitu Gunung Prau, Sindoro dan Sumbing. Mereka harusnya rukun, karena petani sejatinya sangat gotong royong. Tak ada masalah sampai-sampai kedua elemen masyarakat Desa Lowungu harus bersengketa dengan Perum Perhutani, Kedu Utara. Lahan masyarakat seluas 81 ha di Dusun Ngrimpak diklaim sepihak oleh Perum Perhutani.
Gesekan Awal
Sejarah penguasaan tanah di Dusun Ngrimpak, Desa Lowungu merujuk pada penguasaan eks perkebunan teh dan kina dalam hak erfpacht yang semulamilik pengusaha Tionghoa asal Parakan, Temanggung. Pengusaha tersebut meninggalkan lahan miliknya dan tidak pernah datang kembali semenjak gudang teh perkebunan terbakar pada 1932. Pada 1940, diadakan Rembug Desa yang dihadiri Residen Cokro Sutomo dan Wedono Candiroto, Sudirman serta warga Ngrimpak dan memutuskan bahwa sebanyak 13 KK buruh pemetik teh perkebunan dapat memanfaat lahan eks perkebunan teh tersebut seluas 17 Ha dengan pembagian yaitu untuk rumah dan pekarangan masing-masing 0,25 Ha, serta kebun seluas 1 Ha.
Kemudian di tahun 1958, warga Ngrimpak mengajukan permohonan ke pihak pemerintah untuk menggarap lahan eks perkebunan teh dan kina tersebut, karena keadaan penduduk yang semakin padat dan membutuhkan lahan sebagai mata pencarian. Proses panjang ini baru disetujui oleh Pemerintah di tahun 1967, dengan dikeluarkannya petok D/letter D dari kantor agraria untuk lahan garapan masyarakat Ngrimpak.
Konflik yang terjadi antara warga dusun Ngrimpak dengan Perhutani sebenarnya “indikasinya” sudah berlangsung lama, yaitu semenjak Sutomo menjadi kades pada 1970an. Soetomo intens didatangi petugas kehutanan. Soetomo diminta agar menyerahkan tanah eks perkebunan teh kepada pihak kehutanan. Namun Kades Soetomo tidak mau memyerahkan sertifikasi tanah eks perkebunan masyarakat ke Perhutani.
Di tahun 1975, Kades Harsono (pengganti Sutomo) melakukan penarikan surat tanah Petok D/letter D milik warga Ngrimpak dengan alasan pembaharuan administrasi. Pada tahun 1976, Mandor-mandor Perhutani mulai masuk dan menyatakan bahwa tanah di Ngrimpak adalah tanah Perhutani dan bukan merupakan tanah Government Ground (GG).
Hingga saat ini, tanah seluas 81 Ha di Dusun Ngrimpak yang awalnya dikuasai warga Ngrimpak, kini hanya dikelola seluas 27 Ha, dengan ditanami tanaman keras seperti sengon serta kopi, jagung dan ketela. Kemudian lahan seluas 17 ha ditanami pinus Perhutani, serta lahan seluas 37 ha digarap oleh petani pendatang dari Desa Bendungan dan Desa Tening. Jadi lahan sejumlah 81 ha merupakan lahan yang dipersengketakan oleh masyarakat Dusun Ngrimpak dengan pihak Perhutani.
Menurut Andrianto, pendamping masyarakat Ngrimpak, terlihat jelas bahwa terjadi tumpang tindih hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan Perhutani. “Warga Ngrimpak memiliki cukup bukti atas kepemilikan tanah tersebut berupa girik. Konflik ini dilatarbelakangi, ketika kepala desa saat itu menarik girik dari warga, dan pada saat hampir bersamaan, mandor-mandor dari KPH Kedu Utara masuk”. Sengkarut lahan ini tak juga menemukan hasil karena kedua belah pihak tidak ada yg mau mengalah.
Untuk memperkuat posisi tawar masyarakat setempat, mereka telah menanami kawasan hutan yang diklaim Perhutani tersebut, dengan kopi dan jagung. Kini kasusnya sedang dimediasi, dengan melibatkan Komnas HAM dan Tim Task Force Kementerian Kehutanan. Namun kini, hal itu belum juga menuai hasil memuaskan.
Hawa di Dusun Ngrimpak bertolak belakang dengan kesejahteraan ekonomi warganya. Sebagai contoh, dari empat petani, yaitu Atmojo, Wasis, Kabul, dan Agus Marto, semuanya hanya mengandalkan pendapatan dari hasil kopi yang dipanen setahun sekali. Mereka tak punya lagi kesempatan untuk menanam palawija yang bisa dipanen dalam waktu bulanan, karena mereka tak punya lahan lagi untuk menanam tanaman kebun lainnya. Lahan yang dianggap milik mereka tersebut sudah ditanami pinus oleh pihak Perhutani. “Ya mau bagaimana lagi, saya terima nasib saja” ujar Pak Atmojo petani dari Dusun Ngrimpak.
Semenjak 2009, kondisi konflik diperparah dengan datangnya masyarakat dari desa lain yang justru dibolehkan Perhutani menanam di areal sengketa. Masyarakat Desa Bendungan dan Desa Tening, mengaku mereka justru diperintahkan oleh pihak Perhutani menanam di areal konflik tersebut. Ada semacam upaya “adu domba” oleh Perhutani agar terjadi konflik psikologis antar masyarakat desa. Setelah itu, tentu akan memperkuat posisi tawar pihak Perhutani atas tanah sengketa tersebut.
Sempitnya lahan garapan yang dihadapi masyarakat Ngrimpak sendiri juga menambah masalah yang ada. Misalnya, terdapat Sembilan keluarga yang tidak memiliki lahan garapan. Mereka hanya mengandalkan kehidupan dari non-pertanian, misalnya, berjualan di warung makan atau menjadi tukang ojek. Ini tentu tidak logis bila melihat masih banyak lahan kosong di areal konflik yang malah ditanami pinus Perhutani, serta digarap masyarakat Desa di luaran Ngrimpak.
Sebetulnya ada beberapa mediasi yang sudah dapat dilakukan, misalnya saja Kades Lowungu mengajukan permohonan kembalinya tanah Government Ground di Dusun Ngrimpak yang diakui Perhutani sebagai Bosch Wezen kepada Bupati Temanggung. Kemudian DPRD Temanggung membentuk tim investigasi kasus tanah Ngrimpak, namun hingga kini belum ada kerja pasti dari tim dan pemda setempat. Sehingga kedamaian hutan seperti apa yang diutopiakan orang dari makna kemerdekaan masih jauh dari panggang.*** (AGW)


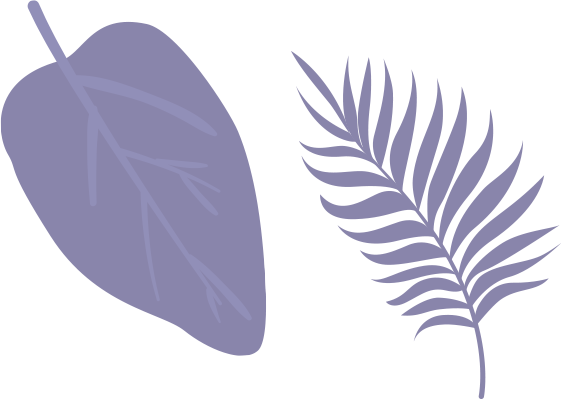
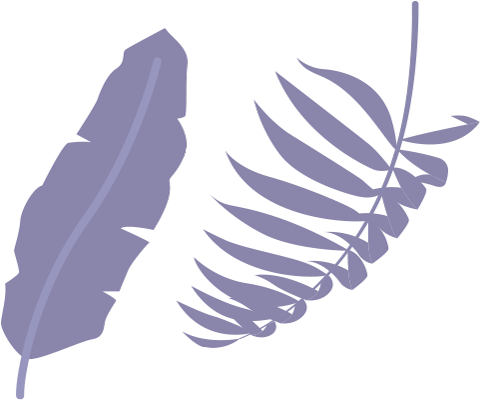
0 Komentar
Tinggalkan Balasan