Di tengah bergulirnya protes masyarakat sipil terhadap proses dan substansi Program Investasi Kehutanan (FIP) yang digawangi oleh tiga Lembaga Keuangan Internasional (Bank Dunia, ADB, dan IFC), dokumen Rencana Investasi Kehutanan Indonesia disetujui oleh Tim Sub-Komite FIP pada tanggal 5 November 2012 di Istanbul, Turki. Disetujuinya Rencana Investasi Kehutanan ini memberi lampu hijau untuk dikembangkannya berbagai proyek MDBs yang tercakup di dalam dokumen tersebut. Dana yang disetujui untuk Indonesia adalah 70 juta dollar: 37,5 juta dollar berupa hibah dan 32,5 juta dollar berupa hutang/pinjaman konsesional.
Rapat ini menyetujui pula digelontorkannya dana persiapan sebesar 1,3 juta dollar untuk tiga proyek berikut:
1) Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (CFI-ADD+)”, (ADB): US$ 500.000
2) “Strengthening of Forest Enterprises to Mitigate Carbon Emissions”, (IFC); US$ 300.000
3) “Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development ”, (World Bank): US$ 500.000
Pemerintah Indonesia dan MDBs diminta untuk mempertimbangkan komentar-komentar yang dilontarkan pada saat rapat pada tahap pengembangan program dan proyek, juga mengkaji dan menanggapi komentar masyarakat sipil, masyarakat adat, dan kelompok komunitas lokal. Namun, timeline dan mekanisme untuk hal ini belum disebutkan maupun diumumkan oleh Tim FIP Indonesia dan perwakilan MDBs.
Berbagai kekhawatiran akan proses dan substansi program dan Rencana Investasi Kehutanan ini mendorong masyarakat sipil untuk terus mengawal proyek MDBs ini, mengingat dalam sejarahnya proyek MDBs justru banyak menimbulkan permasalahan bagi komunitas yang berada di lokasi proyek, bahkan berbagai bentuk pelanggaran HAM.
Catatan kritis masyarakat sipil terhadap FIP di antaranya menyoroti permasalahan mendasar di mana FIP masih mengacu bulat-bulat pada landasan hukum yang bermasalah, yakni UU Kehutanan No. 41/1999 yang belum sepenuhnya mengakui hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup di dalam kawasan hutan. Dokumen FIP juga tidak sungguh-sungguh mendorong perubahan kebijakan kehutanan dan review berbagai kebijakan sumber daya alam bermasalah lainnya yang menjadi amanat TAP MPR IX/MPR/2001. TAP MPR ini hanya menjadi tempelan saja di dalam dokumen Rencana Investasi FIP.
Permasalahan mendasar lain adalah FIP tidak mengakui dan menjawab masalah ketimpangan penguasaan hutan yang didistribusikan secara sangat tidak merata dan menimbulkan ketidakadilan penguasaan yang sangat tinggi. Hingga saat ini, luas skema kehutanan untuk masyarakat masih berada di bawah angka satu juta hektar sementara distribusi sumber daya hutan untuk sektor swasta mencapai lebih dari 30 juta hektar.
Catatan-catatan umum lainnya adalah belum kuatnya dokumen FIP dalam menjawab isu ketidakadilan gender dalam penguasaan sumber daya alam; lemahnya fokus pada illegal logging; diabaikannya peran historis lembaga keuangan internasional sendiri dalam mendorong deforestasi di Indonesia; diabaikannya pendorong ekonomi-politik akibat desentralisasi; kuatnya fokus pada pasar yang berpotensi mengarah pada jebakan pasar dan penumpukan hutang baru, dan tidak jelasnya status komentar dan masukan publik dalam dokumen final FIP.
Secara spesifik, masyarakat sipil menyoroti perbedaan standar kebijakan pengaman (safeguards) di antara masing-masing lembaga keuangan internasional dan keterpisahannya dengan safeguards nasional (PRISAI) yang tengah dikembangkan; masih problematisnya unit-unit yang menjadi fokus intervensi dalam rencana investasi, khususnya KPH terkait dengan masalah perizinan; terpenjaranya hak masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk hak FPIC, dengan dicantumkannya berbagai reservasi hak seperti ‘hak yang legitimate dan klaim komunitas yang valid’ dengan mengacu pada persyaratan legal-formal BAU yang tidak memberi keadilan bagi masyarakat; belum jelasnya kepemilikan, tanggung jawab, dan akuntabilitas program; diabaikannya masalah-masalah terkait skema restorasi ekosistem; pengelolaan hutan berbasis komunitas dan resiko hutang; marketisasi melalui fokus yang tidak berimbang pada hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat; tidak jelasnya kriteria penunjukan wilayah uji coba (pilot); serta masih kaburnya definisi berbagai istilah yang digunakan.
Submission masyarakat sipil terhadap dokumen FIP ini diusung oleh HuMa, BIC, debtWatch Indonesia, ELAW Indonesia, AMAN, Solidaritas Perempuan, KPSHK, Forest Peoples Programme, IESR, Greenpeace, Walhi, AKSI, Ulu Foundation, Pusaka, Sawit Watch dengan catatan khusus dari Walhi mengenai kelayakan penerapan FIP di Indonesia.
Dokumen komentar lengkap dapat diunduh ditautan berikut:
Komentar dan Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk FIP 21 September 2012
Versi Bahasa Inggris
FIP Commentary and Recommendation Sept 2012- english


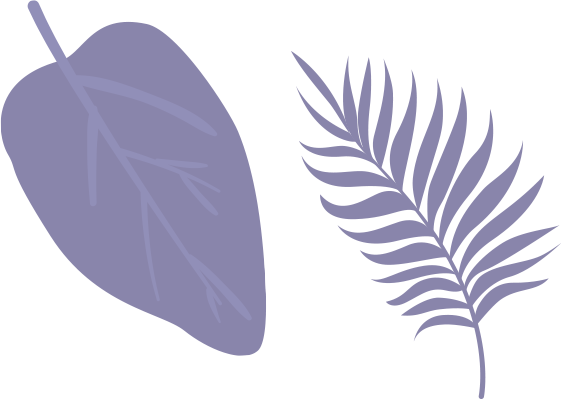
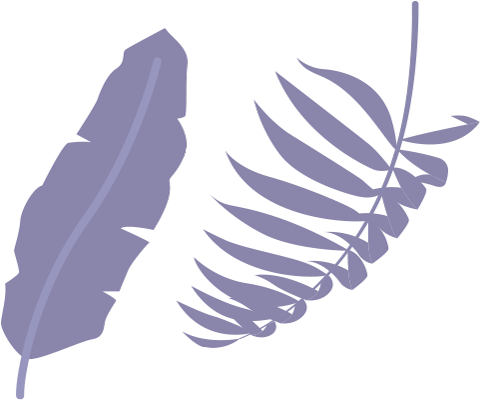
0 Komentar
Tinggalkan Balasan