Jerih payah José R. Martinez Cobo tak sia-sia. Dari meja tugasnya, laporan berjudul Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Population yang ditulis pada 1982 menginisiasi peristiwa penting dua dekade mendatang, yakni dibacakannya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat pada 13 September 2007 oleh Majelis Umum PBB. Hari itu selalu dikenang dunia sebagai Hari Deklarasi PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP). Laporan Cobo menyentak banyak orang tatkala kelesuan ekonomi global melanda awal 1980-an. Ia menjabarkan ada sekelompok manusia yang selalu mendapatkan diskriminasi atas kebijakan negara-negara dunia.
Setidaknya ada sepuluh aksi yang diperlukan dunia untuk menghormati hak-hak masyarakat adat menurut laporan Cobo, yaitu perihal pemulihan masyarakat adat atas: tanah; kesehatan; perumahan; pendidikan; bahasa; sosial-budaya dan pranata hukum; pekerjaan dan pelatihan; hak politik; hak beragama dan keadilan administrasi melalui pendampingan hukum. Dari laporan Cobo, kelompok kerja masyarakat adat dibentuk PBB pada 1982. Kelompok kerja ini masuk ke dalam enam kelompok kerja yang berada di bawah naungan komando Sub-Komisi untuk Hak Asasi Manusia. Selama 24 tahun kelompok kerja ini merancang instrumen khusus yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat adat di seluruh dunia.
Prosesnya berjalan sangat lambat karena tentu saja kekhawatiran negara-negara terhadap beberapa ketentuan inti dari rancangan deklarasi tersebut, yaitu hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat adat dan penguasaan sumber daya alam di atas tanah-tanah adat. Disintegrasi jadi kekhawatiran bagi negara yang abai atas adanya pluralisme hukum di negaranya. Dashlibroon dan Zamani (2020), dalam Journal of Critical Reviews mengatakan “supremasi hukum dalam masyarakat yang berada dalam transisi kediktatoran menuju demokratis amatlah konfrontatif. Hal ini dikarenakan kapasitas hukum nasional di negara transisi tersebut tidak dapat menangakap hukum lokal di negaranya. Sementara itu mekanisme formalisme atau informalisme hukum tidak dapat efektif karena dalam situasi yang selalu berlawanan. Sistem hukum yang adaptiflah yang harusnya dikembangkan.”
Baru pada 1994 kelompok kerja mengajukan draf deklarasi pertama tentang hak-hak masyarakat adat kepada Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas. Draf tersebut dikirim untuk dipertimbangkan ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB bidang Ekonomi Sosial dan Budaya (Ecosoc). Draf 1994 ini kemudian diperinci oleh kelompok kerja antar-sesi untuk diadopsi di Majelis Umum PBB, namun kurun waktu dekade pertama 1995-2004 kelompok kerja gagal mengurai draf deklarasi tahun 1994, sehingga masa kerjanya ditambah menjadi dua dekade kedua pada 2005-2015.
Pada tanggal 29 Juni 2006, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat. Kemudian Pada 28 Desember 2006, Komite Ketiga Majelis Umum bidang Sosial Ekonomi dan Budaya mengadopsi rancangan resolusi inisiatif deklarasi masyarakat adat yang didukung oleh beberapa negara seperti negara Eropa dan Amerika Latin. Namun inisiatif yang dipimpin oleh Namibia, bersama sejumlah negara Afrika, menghasilkan rancangan perubahan. Dalam bentuk barunya, rancangan tersebut meminta Majelis memutuskan “untuk menunda serta mempertimbangkan secara matang Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, juga memberi waktu untuk konsultasi lebih lanjut di tiap-tiap perwakilan negara”.
Akhirnya, pada 13 September 2007, Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat diadopsi oleh 144 negara, 4 suara menentang yaitu berasal dari: Australia, Kanada, Selandia Baru dan Amerika Serikat. Jelas negara-negara ini masih memiliki White Supremacy atas sistem politiknya dan menganggap beban bila mengakui suku asli di negaranya. Sebelas negara abstain (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Rusia, Samoa, dan Ukraina). Sejak Deklarasi dibacakan, secara berangsur-angsur, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Kanada kini semuanya telah membalikkan posisi mereka dan menyatakan dukungan untuk Deklarasi Masyarakat Adat ini.
Revivalisme Adat di Indonesia
Gerakan global kebangkitan adat pada medio 1980-an menginspirasi perlawanan Masyarakat Adat di Indonesia. Di tengah proyek swasembada pangan dan berbagai kebijakan pembangunan pemerintah, gerakan masyarakat adat muncul secara sporadik. Situasi ini menggugah keprihatinan banyak aktivis dan akademisi atas kondisi yang dihadapi oleh Masyarakat Adat. Pada tahun 1993 di Toraja, Sulawesi Selatan disepakati pembentukan sebuah wadah yang diberi nama Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang dipelopori para tokoh adat, akademisi, pendamping hukum dan aktivis gerakan sosial.
Dalam pertemuan JAPHAMA menyepakati istilah Indigenous Peoples dalam konteks Indonesia sebagai ‘Masyarakat Adat’. Penggunaan istilah ini merupakan bentuk perlawanan terhadap istilah yang dilekatkan kepada Masyarakat Adat dalam pemerintahan Orde Baru yang melecehkan, seperti ‘suku terasing’, ‘masyarakat perambah hutan’, ‘peladang liar’, ‘masyarakat primitif’, ‘penghambat pembangunan’. Pertemuan ini menegaskan bahwa Masyarakat Adat adalah sekelompok manusia bermartabat dan memiliki hak konstitusional untuk diperlakukan layaknya warga negara Indonesia lainnya.
Gerakan reformasi 1998 yang menuntut adanya pengalihan otoritas dari pusat ke pinggiran (desentralisasi) memunculkan gerakan kebangkitan kembali (revivalisme) adat. Menurut Adam D. Tyson (2010), hal ini dipicu karena kebijakan yang tidak memiliki partisipasi publik, sehingga otonomi memberikan semangat untuk pengakuan dan pemulihan hak bagi masyarakat adat. David Henley dan Jamie S. Davidson (2008) mengatakan ada gerakan di desa-desa yang menolak keras untuk menyerahkan tanah adat untuk tujuan pembangunan negara. Tapi desa-desa ini kemudian menjadi sasaran intimidasi, penahanan, kriminalisasi. Bahkan dalam kasus-kasus tanah komunal atau tidak bersertifikat biasanya mereka tak mendapat kompensasi apapun. Henley dan Davidson menyatakan kepentingan saat ini dalam perjuangan adat bukan sekedar wacana nasional-internasional tentang hak-hak masyarakat adat. Kebangkitan adat harus dimaknai melampaui pemahaman ideologis, ia harusnya ditandai sebagai referensi normatif hukum dalam mendapatkan tanah mereka.
Tokoh-tokoh adat kemudian berkumpul untuk melakukan konsolidasi atas gagasan mengenai Masyarakat Adat dan identifikasi cita-cita bersama. Pada tanggal 17-22 Maret 1999, untuk pertama kalinya, dilaksanakanlah Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) di Hotel Indonesia, Jakarta. Lebih dari 400 pemimpin dan pejuang Masyarakat Adat hadir dalam KMAN I. KMAN I mendiskusikan permasalahan eksistensi Masyarakat Adat dari berbagai aspek, seperti: pelanggaran Hak Asasi Manusia; perampasan tanah, wilayah dan sumber daya; pelecehan terhadap budaya adat maupun kebijakan pembangunan yang meminggirkan Masyarakat Adat.
KMAN I juga membahas dan menyepakati visi-misi, asas, dan program kerja bagi Masyarakat Adat. KMAN I menghasilkan Pandangan Dasar Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 tentang “Posisi Masyarakat Adat terhadap negara” yang dengan keras menegaskan bahwa Masyarakat Adat telah lebih dulu ada sebelum adanya Negara Indonesia, posisi itu dikenal dengan jargon; “Jika Negara Tidak Mengakui Kami, maka Kamipun Tidak akan Mengakui Negara.” KMAN I pun telah memberikan landasan kesetaraan gender dalam gerakan Masyarakat Adat. Dari KMAN I terbentuklah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai wadah perjuangan Masyarakat Adat. Di Indonesia, tanggal 17 Maret diperingati sebagai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan sekaligus Hari Ulang Tahun AMAN.
Gerakan Dunia Menggugat melalui Jalur Hukum
Secara global, deklarasi hak-hak masyarakat adat menggugah keberanian untuk membawa kasus masyarakat adat ke ranah hukum. Di Indonesia pada Juni 2013 Mahkamah Konstitusi Indonesia mengabulkan uji materi UU Kehutanan (UU 41/1999). Mahkamah Konstitusi Indonesia mengabulkan sebagian permohonan penggugat untuk mengeluarkan hutan adat dari hutan negara. Pemohon berasal dari organisasi AMAN, Masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu di Banten dan Masyarakat Adat Kuntu di Riau. Di Peru tahun 2015, masyarakat adat Wampis menggugat konstitusi Peru dengan menyatakan diri memiliki pemerintah adat yang otonom dan mempertahankan 1,3 juta hektar wilayah leluhur mereka dengan hukum adatnya. Di Kenya 26 Mei 2017, Pengadilan Hak Asasi Afrika menyatakan kemenangan bagi komunitas Ogiek melawan pemerintah Kenya. Mereka berhak atas tempat tinggal mereka di Kawasan hutan madu dan mendapat kompensasi atas perjuangannya dengan diadopsinya Undang-Undang Tanah Masyarakat atas Wilayah Tenurial Adat. Lalu, ada putusan-putusan pengadilan yang menyiratkan hal-hal positif seperti keputusan Pengadilan HAM Inter-Amerika terhadap Suriname yang menyoroti hak-hak masyarakat adat Saamaka.
Semua keputusan tersebut sebagian besar merujuk pada Deklarasi PBB 2007. Hal ini tentu menjadi yurisprudensi (rujukan melalui peradilan) bahwa sebagian besar instrumen hukum menegaskan kembali masyarakat adat sebagai subyek hukum. Akan tetapi hak atas wilayah adat tentu saja masih harus diperjuangkan. Kemajuan-kemajuan ranah hukum ini dapat memberi inspirasi masyarakat adat di belahan bumi lainnya untuk terus berjuang mempertahankan haknya, namun di sisi lain, gugatan ranah hukum juga membuat para perampas lahan memikirkan strategi formalisme untuk menguasai tanah-tanah adat. Skema invasi dengan mengatasnamakan lahan pangan, ekonomi hijau dan pembangunan ramah lingkungan sering jadi dalih bahwa mereka telah menghargai hak adat. Nyatanya, tekanan bagi masyarakat adat terus meningkat dari ancaman penggusuran, perampasan tanah melalui dalih legalisasi dan perampasan tutupan hutan yang semakin tinggi.
Hingga saat ini, diskriminasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat terus bertambah. Laporan Defender of the Earth dari Global Witness melaporkan terdapat lebih dari 200 pembela tanah dan lingkungan – yang hampir 40%-nya adalah masyarakat adat. Hingga 2016 telah terjadi pembunuhan yang tersebar di 24 negara karena masyarakat adat mempertahankan tanah mereka dalam situasi konflik. Di samping kematian, masyarakat adat menghadapi kekerasan, penghilangan, penganiayaan dan ancaman terhadap keluarga mereka. Bahasa dan religi adat juga telah banyak musnah terutama di wilayah Amerika Latin dan Asia Pasifik.
Pemulihan masyarakat adat hari-hari ini mendapatkan tuntutan yang lebih mendasar. Sebab acapkali pemulihan masyarakat adat hanya bersifat artifisial semata. Simbolisme pejabat menyerahkan penghargaan melalui pesta dan tari-tarian adat tidak didasari partisipasi melibatkan masyarakat adat dalam proyek pembangunan. Kebutuhan dasar masayrakat adat sendiripun masih jauh dari kata terpenuhi.
Permintaan menanggalkan sifat karitatif (kasihan) dan uniformitas (seragamisasi) dalam tiap kebijakan bagi kelompok masyarakat rentan terus didengungkan. Secara prinsipil karitatif dan uniformitas ingin menerapkan keadilan welas-asih dalam skala besar, sehingga misi politik yang diemban adalah soal bagaimana mengubah struktur kelompok masyarakat. Padahal aktor perubahan yang ada dalam masyarakat itu beragam dan bahkan harusnya bisa melampaui sifat elitisme semata.
Tuntutan masyarakat adat hari ini meminta adanya kebutuhan para penyintas di kelompok masyarakat adat yang beragam, sehingga sejatinya kebijakan memerlukan non-aggression principle (NAP). Non-aggression principle atau prinsip non-intervensi adalah posisi etis yang menyatakan bahwa kesalahan terbesar yang bisa dilakukan seseorang terhadap orang lain adalah dengan melakukan agresi, agresi diartikan sebagai intrusi atau pelanggaran terhadap hak dan wilayah otonomi orang lain. Misalnya bagaimana mewujudkan pemulihan adat, yang seharusnya juga memulihkan hak kolektif perempuan adat. Tentu perempuan adat memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan wilayah domestik mereka sendiri dan berbeda dengan para elit adat. Kelompok perempuan adat tentu mengalami kekerasan bertubi karena prinsip non-intervensi tidak dilakukan. Tuntutan ini juga disematkan kepada kelompok rentan lainnya, seperti pemuda adat, kaum difabel adat, hingga anak-anak adat.
Tuntutan inklusi sosial semacam ini tentu saja bisa memperkuat gerakan masyarakat adat global dan bisa saja lebih kompatibel dengan prinsip lokalisme yang menyadari pentingnya skalabilitas di dalam menerapkan prinsip etis/politis di dalam hidup bermasyarakat (pertama-tama, berbuat adil terhadap lingkup kecil terlebih dahulu sebelum menerapkan keadilan sosial). Hingga kini gugatan masyarakat adat pada dunia terus-menerus keras, tapi kebijakan pemulihannya begitu malas [.]
Telah dimuat sebelumnya di https://tirto.id/masyarakat-adat-menggugat-dunia-gjrc, tanggal 13 September 2021.



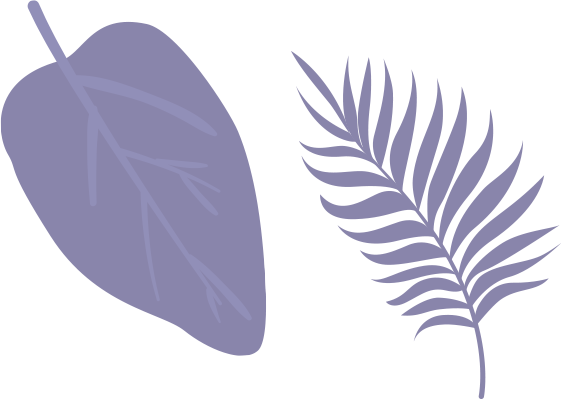
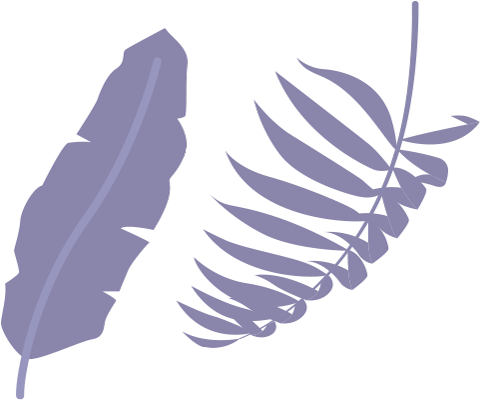
0 Komentar
Tinggalkan Balasan