Seminggu belakangan ini, beberapa koran dihiasi dengan pemberitaan terkait dengan kepala desa merangkap sebagai petani yang diduga memproduksi dan mengedarkan benih dengan cara ilegal. Saya teringat kembali dengan banyaknya kisah prihatin yang dialami oleh petani kita, mulai dari kesulitan untuk menentukan harga komoditas yang dipanen karena sudah ditentukan oleh makelar atau tengkulak hingga kesulitan banyak petani di Indonesia dalam mengakses lahan karena maraknya land grabbing dengan berbagai cara.
Ironis memang, sejak dahulu negara kita dikenal sebagai negara agraris yang memiliki komoditas-komoditas unggulan yang menjadi incaran banyak negara penjajah. Ditambah lagi dengan kenangan lagu band legendaris “Koes Ploes” yang menyebut bahwa Indonesia adalah negara kaya, sampa-sampai tongkat batu bisa jadi tanaman. Mungkin itu hanya tinggal kenangan saja saat ini, karena menjadi petani gurem yang masih banyak tersebar di seluruh pelosok negeri kondisinya sangat memprihatinkan
Revolusi Hijau yang Merusak
Kejadian yang menimpa Bapak Munirwan di Aceh mengingatkan kembali saya pada sejarah pangan dunia yang menelurkan konsep “Revolusi Hijau”. Adanya konsep “Revolusi Hijau” yang digaungkan oleh William S. Eaud pada tahun 1968 cukup membawa dampak yang signifikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia membungkus konsep Revolusi Hijau tersebut dengan judul “Panca Usaha Tani” yang banyak dikecam oleh banyak pihak. Panca Usaha Tani menitikberatkan pada usaha dalam ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian yang kaku, kekakuan yang dimaksud dikarenakan kewajiban bagi setiap petani untuk menanam tanaman yang diinstruksikan oleh Pemerintah (Mubyarto, 1979).
Adanya kebijakan penyeragaman tanaman tersebut berimplikasi pada tereduksinya jumlah bibit dan benih lokal yang ada di Indonesia. Padahal, negara ini adalah pemilik dari banyak bibit maupun benih dari berbagai model dan bentuk tanaman. Secara tak langsung, hal ini menghilangkan kekayaan sumber daya yang seharusnya menjadi milik bangsa ini. Salah satu contoh menarik yang penulis temukan di Kalimantan Barat, tepatnya di salah satu desa di Kabupaten Melawi.
Tahun 1983, desa di Kabupaten Melawi ini mendapatkan bantuan bibit dan benih bersama dengan pencetakan sawah seluas 13 (tiga belas) hektar sebagai bentuk CSR dari salah satu perusahaan yang memiliki IUPHHK-HTI. Dengan adanya sawah, praktis masyarakat mulai beralih dari sistem pertanian ladang ke sistem pertanian sawah. Tentunya, masyarakat harus dibina untuk memahami sistem pertanian sawah dan menggunakan pupuk kimia, karena sebagian besar masyarakat yang bermukim disana adalah masyarakat Dayak yang budayanya adalah menggunakan sistem pertanian ladang dan menggunakan pupuk alami yang dihasilkan dari proses pembakaran ladang sebelum menanam. Selanjutnya, masyarakat diberikan bibit padi dengan nama varietas “Cimandiri” yang diberikan oleh OPD Dinas Pertanian disana dan masih digunakan hingga kini.
Sejak tahun 1999, penghasilan dari komoditas Padi Cimandiri tersebut mulai menurun dan hingga kini semakin merosot produksinya. Hal ini membuat beberapa petani yang masih menyimpan dengan baik bibit-bibit lokal untuk kembali melakukan penanaman yang dilakukan dengan sistem pertanian ladang. Pada awal tahun 2019 ini, penulis berkesempatan mengunjungi dan menanyakan perihal masalah komoditas padi tersebut dengan membandingkan hasil panen dari Padi Cimandiri yang dibandingkan dengan Padi Badu (bibit lokal). Hasilnya sangat mencengangkan, karena hasil bulir padi dalam satu tangkai padi yang panen sangat berbeda jauh, Cimandiri menghasilkan 30 bulir per tangkai sementara Badu menghasilkan 150 bulir per tangkai.
Cerita singkat diatas menyadarkan saya bahwa kecaman keliru terhadap program Panca Usaha Tani dapat dibuktikan, sehingga penyeragaman tanaman atau komoditas menjadi tidak tepat dalam konteks tanah Indonesia. Selain itu, program Panca Usaha Tani yang fokus pada usaha intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan salah satu hal yang tidak tepat. Intensifikasi yang menekankan pada penggunaan pupuk kimia berimplikasi pada rusak dan hilangnya kesuburan serta pencemaran tanah (LIPI, 2008). Di lain sisi, usaha ekstensifikasi yang dilakukan dengan mencetak sawah juga banyak membuka hutan dan mengurangi jumlah kawasan hutan.
Gagapnya Hukum Indonesia
Sebagai salah satu negara yang menggantungkan hidupnya dari komoditas pertanian, Indonesia dirasa sangat minim sekali dalam memperbaharui maupun melakukan riset pengembangan pertanian yang komprehensif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh dua hal: Pertama, rumit dan panjangnya proses birokrasi untuk melakukan budidaya. Hadirnya aturan teknis dan pelaksana sebagai kepanjangan dari UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman belum bisa mengakhiri birokrasi yang rumit. Selain itu, sangat sedikit penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang mampu untuk menjangkau serta memiliki kapasitas yang memahami situasi dan kondisi dari tanaman serta petani. Kedua, pola keseragaman yang mewajibkan petani untuk menanam satu jenis tanaman tertentu. Hal ini merupakan kelanjutan dari program Panca Usaha Tani yang masih dianut oleh sebagian besar PPL, sehingga berdampak pada tidak berkembangnya ilmu dan pengetahuan terkait pertanian yang bisa disampaikan kepada petani.
Selain pengembangan budidaya tanaman, Indonesia hingga kini juga masih belum menyadari betapa berbahayanya produk rekayasa genetik (PRG) yang memiliki banyak dampak buruk, diantaranya adalah potensi penyakit bagi konsumen dari PRG serta kerusakan lingkungan akibat dampak dari pengembangan PRG. Perlu disadari, beberapa negara maju mulai meninggalkan pola pengembangan PRG dan mulai mencari bibit dan benih lokal yang merupakan sumber pangan asli yang dimiliki oleh mereka.
Jalan Keluar Bagi Petani
Menyikapi berbagai polemik terkait pengembangan budidaya tanaman yang dilakukan oleh petani, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 tentang pengajuan gugatan terhadap UU Nomor 12 Tahun 1992 mengubah bunyi Pasal 9 ayat (3) menjadi “Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin kecuali untuk perorangan petani kecil.’ Dengan bunyi pasal yang diubah, praktis konsekuensi dari pengembangan tanaman sejatinya dapat dilakukan oleh petani dan tanpa perlu mendapatkan lisensi terlebih dahulu. Ditambah lagi dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah wajib untuk memberikan dukungan serta menyediakan sarana pertanian sebagai salah satu upaya implementasi dari Pasal 19.
Keberadaan dari 2 (dua) UU yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya dapat dikatakan bermanfaat bagi petani dengan didukung oleh 2 (dua) hal. Pertama, adanya proses penyederhanaan birokrasi dan perubahan perilaku dari birokrat di tingkat daerah dalam memberikan dukungan kepada petani. Kedua, mensinergikan dan menselaraskan program-program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa hingga provinsi secara lebih khusus untuk pengembangan ilmu pengetahuan pertanian dan peningkatan kapasitas secara bersama antara Lembaga/Badan Pemerintah yang bergerak di bidang pertanian dengan petani-petani secara komprehensif dan sesuai dengan konteks permasalahan dari setiap wilayah pertanian.
Telah dimuat sebelumnya di https://jakarta.fixindonesia.com/berita/ironi-menjadi-petani-di-negeri-sendiri/72c079ff-f788-4849-91c7-edb30ae88b36, tanggal 24 September 2021.



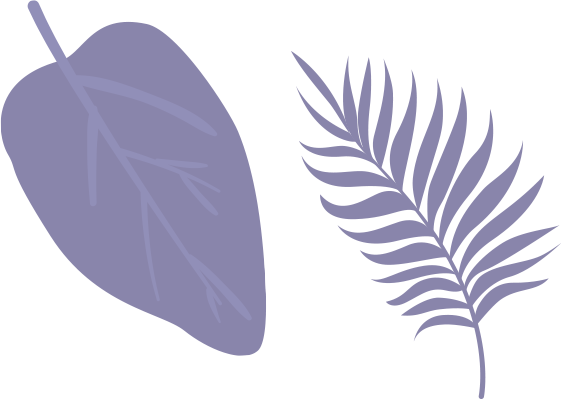
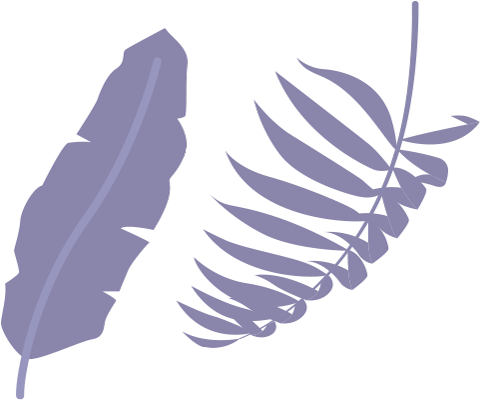
0 Komentar
Tinggalkan Balasan