Oleh Courtney Bristow*
Ketika berada di HuMa, saya tertarik membuka buku Carol Warren dan Anton Lucas (ed), Land for the People (2013). Dalam bab terakhir, mereka menyelesaikan buku tersebut dengan artikel menarik “Agrarian Resources and Conflict in the Twenty-First Century“. Artikel ini masih relevan pada saat ini, dengan mengeksplorasi bagaimana reformasi hukum ternyata amat lambat, untuk bergerak melawan pemerintah atas perampasan tanah oleh perusahaan, dan itu berdampak pada masyarakat di Indonesia. Analisis mereka dimulai dari era Reformasi dan krisis ekonomi Asia 1997-1998. Artikel bab ini membingkai konflik mengenai masyarakat lokal atas hak tanah mereka dengan latar belakang krisis ekonomi. Kemudian perampasan tanah muncul sebagai dalih mencoba mengurangi dampak dari kemerosotan ekonomi yang tiba-tiba tersebut. Mereka menyoroti krisis pangan Indonesia dengan percikan awal konflik, bahwa negara akan memanfaatkan “lahan tidur” atau tanah terlantar. Ternyata sebaliknya, bahwa akumulasi tanah ini sebenarnya berfungsi sebagai cara untuk mengamankan pihak lain, yaitu investor.
Pada titik inilah penulis mengeksplorasi keuntungan dan kerugian investasi skala besar versus kepemilikan pemegang aset kecil di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa terlepas dari potensi dan manfaat investasi skala besar, pengalihan tanah juga menimbulkan masalah-masalah seperti, “proses klaim sepihak dan nir-konsultasi, masalah ganti rugi hukum yang tidak memadai, pengabaian perlindungan lingkungan dan sosial, diskresioner proses persetujuan, kurangnya transparansi, pemantauan dan penegakan hukum”.1 Dalam konteks Indonesia, proses ini memiliki potensi untuk melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan bagi masyarakat setempat. Tentu ini mengurangi argumen bahwa investasi lahan semacam itu bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, malah kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang bertentangan, yakni kerusakan ekologis. Para penulis memeriksa kontradiksi yang tampak antara warisan revolusioner Indonesia dan prinsip panduan keadilan sosial yang termaktub dalam Pancasila, dan ketidakefektifan gerakan reformasi hukum di Indonesia sendiri.
Warren dan Lucas menghubungkan kegagalan hukum untuk melindungi warganya dengan kombinasi “penyuapan, koneksi elit politik-partai dan interpretasi yang salah dari hukum oleh pengadilan”.2 Mereka menggunakan contoh dari bab-bab dalam artikel sebelumnya untuk menyoroti hal ini. Dalam banyak kasus yang sering ditemukan, individu yang dirugikan alih-alih masalah mereka diselesaikan, mereka malah menghadapi tuntutan kriminal.
Akan tetapi bab ini berakhir dengan nada optimis. Warren dan Lucas menggambarkan perubahan dan reformasi yang telah dibuat Indonesia saat ini, seperti keputusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan “penyelesaian konflik dengan masyarakat hukum adat dalam status kawasan hutan”.3 Di sisi lain, kelompok LSM dan aktivis terus menulis, memetakan dan mengusulkan reformasi di banyak aspek sumber daya alam di Indonesia. Pasca tulisan ini dibuat tahun 2013, saya juga mengamati ada langkah-langkah lebih lanjut yang telah dilakukan, seperti pengakuan 8.800 hektare hutan adat, pada tahun 2016 dan 2017.4 Dalam komentar akhir, Warren dan Lucas mengakui tantangan yang sedang berlangsung dan masih akan memperlambat reformasi sosial, tetapi mereka juga optimis dengan menyimpulkan bahwa gerakan sosial sedang membangun pekerjaan yang mereka inginkan, jalan ke depan dapat ditemukan, untuk “kebaikan bersama”, meski sulit dipahami solusinya.5
Salah satu kritik terkait teks Warren dan Lucas dapat kita temukan dalam artikel dari Christopher Atkinson (2014), ia berpendapat bahwa dalam diskusi konflik, sudut pandang elit sangat jarang diungkapkan.6 Seperti Atkinson tunjukkan dalam kajian-kajian akademik, bahwa orang-orang lokal dan petani kecil jelas disuarakan, tapi terkadang kita perlu juga mengungkapkan dalih faktual (bukan asumsi) oleh pihak-pihak lain, terutama alasan-alasan bagaimana sistem peradilan dapat mengalahkan gugatan para petani kecil tersebut.7 Ungkapan dalam perspektif ini mungkin dapat menambah kedalaman pada artikel ini, serta kita dapat berstrategi atas manipulasi elit dan sistem peradilan di Indonesia.
Secara keseluruhan, naskah ini berhasil merangkum hambatan ekonomi dan secara sistematik menggambarkan perampasan hak atas tanah bagi masyarakat setempat yang telah menciptakan jurang kemiskinan – khususnya masalah perampasan tanah oleh pemerintah dan perusahaan. Artikel ini juga menjelaskan kurangnya otonomi dari petani kecil dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Mereka cenderung tak didengar dan tak boleh bersikap. Namun, catatan yang lebih optimis dari penulis mengungkapkan potensi ke depan, untuk mewujudkan reformasi hak atas tanah di Indonesia. Mencermati artikel ini, menarik untuk melihat reformasi dan perubahan apa yang telah dibuat, dan masalah apa yang masih ada. Ini adalah artikel yang berguna untuk memberikan latar belakang baru tentang apa yang masih menjadi masalah menonjol di Indonesia.
Menurut pengalaman saya, meskipun ada beberapa kesamaan, namun perjuangan Indonesia untuk mendapatkan hak atas tanah berbeda secara signifikan dari yang dilakukan oleh Penduduk Asli Australia (Aborigin), khususnya karena penggunaan sistem Common Law oleh Australia. Tidak seperti di Indonesia yang mengandalkan reformasi sosial untuk melakukan perubahan, Penduduk Asli Australia cenderung mampu mengejar reformasi hukum melalui gugatan di tingkat Pengadilan Tinggi, untuk memiliki hak atas tanah mereka agar diakui, yang paling menonjol adalah kasus Mabo (kasus bersejarah nomor dua di Australia). Dari kasus ini, pemerintah kemudian menerapkan Native Title Act (1993), yang membentuk Tribunal Penduduk Asli dan memberikan jurisdiksi khusus kepada Pengadilan Federal untuk memproses aplikasi dari penduduk asli.
Meski sama halnya dengan di Indonesia yang masih saja tetap ada konflik – khususnya ketika pemerintah atau perusahaan ingin menggunakan tanah suku Aborigin dalam pemanfaatan sumber daya alam mereka, seperti menambang batubara – akan tetapi Native Title dapat memandang praktik budaya di tempat itu. Dalam banyak kasus, wilayah mereka cenderung dipulihkan, karena telah terjadi kejahatan dan eksploitasi oleh orang pendatang atau penjajah di masa silam. Tentu pengalaman di Australia ini masih tetap harus direformasi, terutama terkait hal masyarakat adat yang sampai saat ini tidak memiliki hak untuk memveto keputusan pemerintah mengenai tanah mereka. Mereka hanya bisa bernegosiasi.
Perjuangan untuk memperkuat Hak Asli di Australia masih terus berlanjut hingga hari ini, dengan menyerukan undang-undang yang lebih kuat dalam mengamankan hak-hak tanah adat. Australia tentu berbeda dengan Indonesia, tapi dari artikel ini sangat menarik mengkaji tren konflik agraria di Indonesia dan tempat saya tinggal. Progresivitas gerakan sosial tentu berbeda-beda hasilnya[.]
—
1 Warren, C., & Lucas, A. (2013). Agrarian Resources and Conflict in the Twenty-First Century. In C. Warren, & A. Lucas, Land For The People (pp. 372-389). Ohio: Center for International Studies Ohio University, p. 376.
2 Ibid, p. 378.
3 Warren, C., & Lucas, A. (2013). Agrarian Resources and Conflict in the Twenty–First Century, p. 379.
4 Sawitri, A. S. (2018, September 12). Indonesia still behind in indigenous peoples land recognition. Retrieved January 28, 2019, from The Jakarta Post: https://www.thejakartapost.com/news/2018/09/11/indonesia-still-behind-in-indigenous–peoples-land-recognition.html.
5 Warren, C., & Lucas, A. (2013). Agrarian Resources and Conflict in the Twenty–First Century, p. 381.
6 Atkinson, C. (2014). Book Review. International Journal of Rural Management, 10(2), p. 202.
7 Ibid.
—
Bibliography
Atkinson, C. (2014). Book Review. International Journal of Rural Management, 10(2), 199-202.
Human Rights Working Group. (2008). Unveiling Racial Discrimination and Impunity in Indonesia. Jakarta: Human Rights Working Group.
Sawitri, A. S. (2018, September 12). Indonesia still behind in indigenous peoples land recognition. Retrieved January 28, 2019, from The Jakarta Post: https://www.thejakartapost.com/news/2018/09/11/indonesia-still-behind-in-indigenous-peoples-land-recognition.html.
Warren, C., & Lucas, A. (2013). Agrarian Resources and Conflict in the Twenty-First Century. In C. Warren, & A. Lucas, Land For The People (pp. 372-389). Ohio: Center for International Studies Ohio University.
—
*Courtney Bristow adalah mahasiswi Universitas Adelaide, Australia. Tertarik pada hukum lingkungan dan perjuangan masyarakat adat, serta hubungan dan relasi internasional terkait kebijakan lingkungan. Saat ini ia tengah magang di HuMa.
Publikasi lainnya dapat diakses di portal publikasi HuMa.




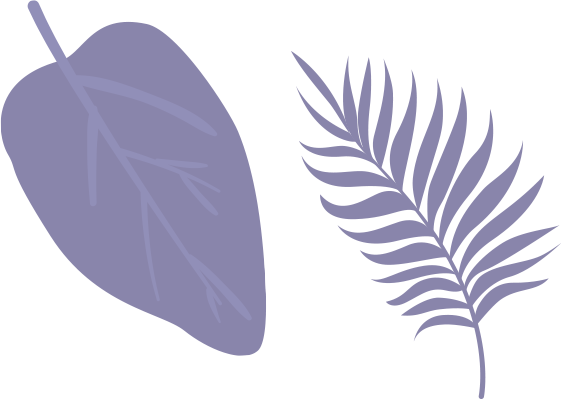
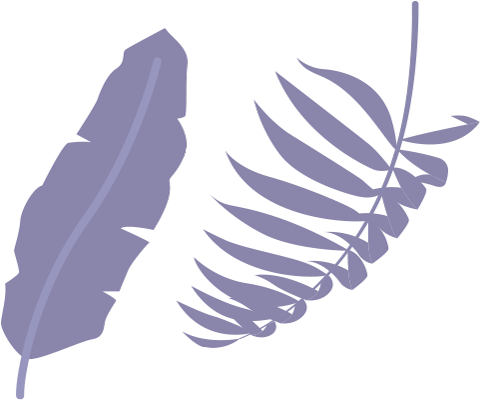
0 Komentar
Tinggalkan Balasan