Oleh Erwin Dwi Kristianto
“Bung Erwin, bangun kita sudah sampai”, ujar Amran, Direktur Yayasan Merah Putih, sembari menepuk pundakku.
“Kita sampai mana, Bung?”, sahutku sambil mengucek mata.
“Kita baru sampai Kota Luwuk, kita beristirahat dulu, besok kita melanjutkan perjalanan ke Morowali”, kata Amran sembari mengambil daypack hitam-nya.
Aku-pun bergegas mengambil daypack-ku dari kabin belakang mobil berpenggerak 4×4 itu. Waktu menunjukkan pukul 02.00 WITA. Sementara kami berangkat dari Kota Palu pukul 09.00 WITA. Itu artinya, 17 jam sudah kami menempuh jalan darat trans Sulawesi Tengah.
“Istirahat-lah Bung, besok Kita masih harus berkendaraan lagi selama delapan jam menuju Taronggo”, kata Amran sembari menarik retsleting sleeping bag-nya.
***
Desa Taranggo berada di kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara. Kabupaten Morowali Utara adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah. Morowali Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Morowali yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 12 April 2013.
Desa Taronggo berpenduduk 318 jiwa dan berada di kaki bukit Pegunungan Tokala. Desa ini merupakan salah satu dari belasan desa di kecamatan Bungku Utara yang dihajar banjir bandang dan tanah longsor pada tahun 2007. Saat itu, sejumlah warga di desa ini masih dinyatakan hilang akibat banjir bandang.
Rombongan telah sampai di Desa Taranggo. Dari sini, sudah tidak ada lagi jalan yang bisa dilalui oleh mobil. Bahkan oleh mobil berpenggerak 4×4 yang kami tumpangi. Kami harus berjalan kaki melintas sungai dan mendaki lereng bukit di Pegunungan Tokala. Kami memutuskan untuk bermalam di Desa ini, karena hari sudah beranjak senja. Gelap menunjukkan kuasanya.
“Ada berita buruk Bung, saya harus kembali ke Palu, Papa saya meninggal”
“Bung Erwin terus saja melanjutkan perjalanan ke Pegunungan Tokala”
Malam pun semakin sunyi.
***
Gerimis pagi itu. Kabut belum sepenuhnya hilang ketika kami berempat memulai tracking. Puncak-puncak bukit di Pegunungan Tokala tertutup awan hitam. Kami bergegas, karena khawatir hujan akan semakin deras. Jika hujan deras, maka debit air sungai Salato akan semakin besar. Tidak ada jembatan di sungai selebar hampir 100 meter itu. Kami harus menyeberangi Sungai Salato jika ingin menuju tempat tujuan kami.
Beberapa jam sudah kami berjalan. Kami sudah melintasi Sungai Salato. Kebun-kebun coklat dan kelapa. Kami sudah mulai memasuki hutan dengan vegetasi yang heterogen. Di kejauhan sudah nampak Posangke Junju atau hutan alang-alang. Beberapa rumah beratap daun kelapa juga sudah terlihat dari kejauhan.
Itu artinya tujuan kami sudah dekat. Ya, tujuan kami adalah Lipu-lipu di bukit-bukit Pegunungan Tokala. Lipu adalah unit sosial terkecil masyarakat Tau Taa Wana. Sebuah lipu biasanya terdiri dari beberapa rumah yang saling berdekatan. Di Lipu viatiro, kami bermalam. Selain bermalam, Agus dan Murni, staf Yayasan Merah Putih mengajar abjad dan angka kepada beberapa anak-anak di Skola Lipu. Skola Lipu adalah pendidikan alternatif untuk Tau Taa Wana.
***
Dalam beberapa literatur, Tau Taa Wana digolongkan dalam kelompok suku besar Koro Toraja. Leluhur mereka melakukan migrasi awal dari muara antara Kalaena dan Malili kemudian menyusuri Sungai Kalaena. Mereka lalu menuju bagian utara melewati barisan Pengunungan Tokolekaju hingga akhirnya sampai di bagian tenggara Danau Poso. Selanjutnya, mereka bergerak ke arah timur laut menyisir lereng Gunung Kadata menuju dataran Walati yang dialiri Sungai La, dan terus bergerak menyusuri Sungai Kuse sampai akhirnya tiba di daerah hulu Sungai Bau. Dari sini mereka terus bergerak bermigrasi ke arah Timur hingga akhirnya sampai di hulu Sungai Bongka, tepatnya di wilayah Kaju Marangka. Di wilayah Kaju Marangka ini, sebagian kelompok migran menetap dan berkembang menjadi kelompok etnik Tau Taa Wana. Dalam perkembangan selanjutnya, etnik Tau Taa Wana kemudian menyebar dan mengelompok menjadi empat suku sebagaimana disimpulkan oleh A.C. Kruyt.
Menurut Kruyt (1930), dari segi dialek bahasa, Tau Taa Wana terbagi menjadi empat suku, yaitu: Pertama, Suku Burangas, berasal dari Luwuk dan bermukim di Lijo, Parangisi, Wumanggabino, Uepakatu, dan Salubiro; Kedua, Suku Kasiala, berasal dari Tojo Pantai Teluk Tomini dan kemudian berdiam di Manyoe, Sea, serta sebagian di Wumanggabino, Uepakatu, dan Salubiro; Ketiga, Suku Posangke, berasal dari Poso dan berdiam di wilayah Kajupoli, Taronggo, Opo, Uemasi, Lemo dan Salubiro; Keempat, Suku Untunue, mendiami Ue Waju, Kajumarangka, Salubiro, dan Rompi.
Keempat dialek bahasa yang membagi etnik Tau Taa Wana menjadi empat suku tersebut, menurut Jane Monnig Atkinson adalah varian dialek dalam bahasa Pamona. Oleh karenanya, Atkinson menyimpulkan bahwa Tau Taa Wana merupakan sub-etnis dari kelompok etnolinguistik Pamona (Atkinson, 1992).
Secara etnografis, Tau (orang) Taa atau To Wana merupakan sub etnis dari kelompok etnolinguistik Pamona yang mendiami wilayah-wilayah sekitar sungai Bongka, Ulubongka, Bungku Utara dan Barong. Orang Wana memakai dialek Wana yang termasuk di dalam rumpun bahasa Pamona sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Dialek Wana juga disebut dialek Taa, sebuah varian dalam bahasa Pamona (Atkinson, 1992).
Secara linguistik, menurut Alvard (1999) orang Wana bertutur dalam bahasa Taa yaitu sebuah bahasa yang banyak digunakan disekitar kawasan pesisir dan dataran rendah di sekitar Cagar Alam Morowali. Orang Wana Posangke mendiami daerah dataran tinggi yang berlembah di sebelah barat Cagar Alam Morowali, yang lokasi mukimnya tersebar di sepanjang Sungai Salato, Sungai Sumi’i, Sungai Uwe Kiumo dan Uwe Waju. Sumber mata air sungai Salato berhulu di Gunung Tokala dan bermuara di sebelah barat (Teluk Tolo).
Wilayah sebaran utama Tau Taa Wana, pada membentang dari bagian timur dan dan timur laut Cagar Alam Morowali (Kabupaten Morowali Utara) sampai di bagian barat Pegunungan Batui (Kabupaten Banggai) dan Pegunungan Balingara (Kabupaten Tojo Una-Una). Dalam wilayah-wilayah tersebut konsentrasi terbesar lipu Tau Taa Wana, berada di sekitar gunung Tokala, Ponggawa, Katopasa dan lumut.
***
Siang itu kami sampai di Lipu Salisarao. Beberapa orang sudah berkumpul di sebuah rumah. Mereka sudah duduk melingkar. Beberapa botol pongasih sudah tersedia. Lembaran daun jagung kering berisi sejumput tembakau juga mereka sajikan. Kami kemudian berbincang, sekedar untuk mencairkan komunikasi.
Seorang warga Lipu Salisarao mulai bercerita. Dia bercerita mengenai hutan. Baginya, hutan bagi orang Taa sangat vital. Ia berkaitan dengan bagaimana mereka hidup dan melanjutkan kehidupan. Bagi mereka, hutan adalah tempat hidup dan sumber kesejahteraan.
“tanpa hutan, kami orang Taa mungkin akan kesulitan melanjutkan kehidupan,”
“Kami mengambil getah damar dan rotan dari hutan”
“Kami juga membuka hutan dan berkebun” ujar Indo Lako.
Dalam aturan adat Tau Taa Wana, terdapat banyak pengaturan tentang hutan, termasuk larangan-larangan adat tentang hutan. Mereka memiliki ketakutan terhadap kemungkinan bisa terjadi kesalahan atau melanggar garis ketentuan adat, dalam praktik pembukaan ladang. Sehingga mereka memilih melakukannya secara bersama-sama, sebelum lahan siap dibagi.
Beberapa penamaan hutan lahan yang masih kental dan ditemui di Posangke junju (hutan alang-alang), pangale (hutan dengan kayu-kayu besar), Pangale kapali (hutan larangan) ini biasanya karena ada pohon besar, pohon beringin, dan batuan besar, Vaka nafu (bekas kebun), yopo mura (hutan muda), Yopo masia (hutan muda), Bonde (kebun-kebun kecil), nafu toto (padi tiga bulan).
Warga Lipu Salisarao yang lain kemudian, menjabarkan beberapa contoh pembagian hutan lahan itu. Menurutnya Yopo adalah hutan bekas areal rotasi peladangan. Berisi kayu-kayu kecil yang terdiri dari beberapa tingkat waktu dan umur. Sebagai hutan bekas peladangan ia memiliki struktur yang dibedakan dari umur. Pertama, yopo masia adalah bekas ladang yang sudah berumur 5 – 15 tahun; Kedua, adalah yopo mangura, bekas peladangan yang berumur 1-3 tahun. Keberadaan umur dari Yopo adalah gambaran ukuran waktu setiap rotasi peladangan yang berlaku.
Kemudian ada Pangale. Pangale adalah hutan lebat membentuk galeri tegakan yang umurnya sudah mencapai 30 tahun. Pangale ini adalah lahan bekas peladangan atau yopo yang telah tumbuh dan membentuk hutan primer. Ia akan lebat menjadi sebuah hutan yang memiliki fungsi sebagai tujuan rotasi selanjutnya dalam tahapan dan periode tertentu berdasarkan yang disepakati, dari jarak awal waktu membuka ladang.
Ada juga Pangale Kapali. Pangale Kapali adalah hutan larangan yang tidak boleh mengambil apapun di dalamnya. Bahkan untuk mengambil daun bambu yang jatuh sekalipun itu dilarang. Lalu, Tanah Rajuyu adalah tanah yang dimliki secara bersama tidak ada larangan untuk diolah.
Dalam sistem pengaturan lahan orang Taa, tanah diwariskan pada seluruh penghuni isi bumi, tidak boleh dimiliki oleh hanya orang seorang. Yang dimiliki manusia adalah apa yang ditanam atau dia tumbuhkan di atas tanah. Kepercayaan ini menjadi bagian dari spiritual atau keyakinan leluhur orang Taa yang berlangsung dari generasi ke generasi. Kalau ada yang melanggar ketentuan adat ini, maka ia akan di kenai sanksi atau givu bilapersaya
Kami kemudian menyampaikan informasi mengenai putusak MK 35, hutan adat dan UU Desa. Kami juga menyampaikan informasi mengenai Perda Morowali tentang Pengakuan dan Perlindungan Tau Taa Wana. Mereka antusias mendengar informasi tersebut.
***
Berbagai pembelajaran dari Tau Taa Wana sudah kami petik. Senyuman dan beberapa botol pongasih mengantarkan kami meninggalkan Lipu Salisarao. Kami bergegas menuruni perbukitan, karena ada agenda lain dengan Perkumpulan Bantaya di Bahotokong. Masyarakat Bahotokong sudah menunggu kami. Mereka akan mengajarkan kepada kami mengenai “nafas panjang” dalam melakukan reclaiming lahan Hak Guna Usaha.
Palu, 21 – 31 Mei 2014


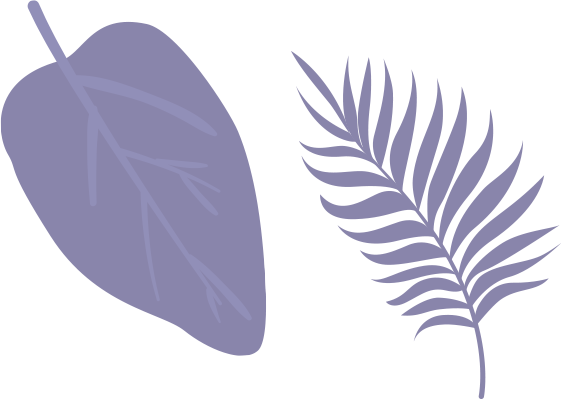
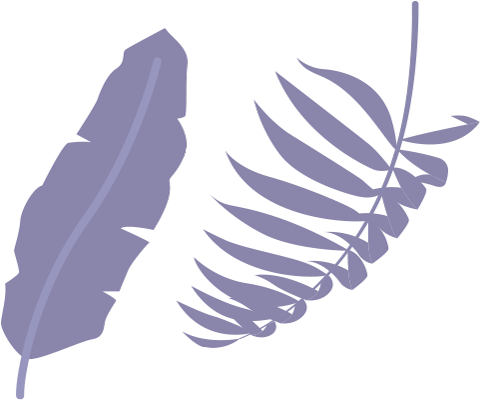
0 Komentar
Tinggalkan Balasan