(Dipublikasi dalam Siaran Pers Geo-Data Nasional Rabu, 23 Juli 2014)
Satu dekade masa Reformasi ini telah membawa perubahan dalam tata kelola sumberdaya alam, baik dalam sisi kebijakan dan implementasinya. Tragisnya, perubahan tersebut tidak disertai perubahan yang fundamental dalam fondasi struktur ekonomi dan politik Indonesia yang kapitalistik, state capitalism yang berkembang pada masa orde baru hanya sekedar bertranformasi menjadi private oligharcic capitalism (Hadiz dan Robison, 2004). Lalu, kawasan kelola rakyat, mau kemana?
Setidaknya berdasarkan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh anggota Jaringan Kerja Pemetaan partisipatif (JKPP) hingga tahun 2013, tercatat dari luasan 5.263.058,28 ha wilayah kelola rakyat, kurang lebih 4.050.253,38 atau 81,4 % tumpang tindih dengan kawasan hutan dan sekitar luasan 2.637.953,94 ha bertumpang tindih dengan perijinan (konsesi HPH, tambang, sawit dan HTI). Besarnya luasan tumpang tindih tersebut menunjukan tingginya konflik dan potensi konflik perebutan ruang yang berimplikasi pada semakin sempitnya ruang kelola rakyat yang mengancam kedaulatan pangan.
Huma menyatakan secara umum terdapat 281 konflik di 24 Provinsi meliputi 80 kasus kehutanan, konflik agraria/pertanahan mencapai 32 kasus, serta konflik pertambangan 23 kasus dan paling banyak adalah perkebunan mencapai 147 kasus dengan luas 2.706.725 Ha (Outlook Huma, 2013), luasan ini setara dengan satu Provinsi Sumatera Barat, dan hal ini hanyalah potret permukaannya saja, konflik pastinya lebih dari itu.
Sawit watch hingga tahun 2014 mencatat lebih dari 720 konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit. konflik ini terus meningkat seiiring dengan semakin kurangnya lahan untuk masyarakat. Pertambahan luas perkebunan sawit setiap tahunnya sekitar 400.000 Hektar. Sawit Watch menemukan untuk Kalimantan Tengah saja tanah yang tidak ber “penghuni” tersisa sekitar 1,2 juta hektar, itu pun hanya berada di sempadan sungai. Ini membuktikan bahwa kepemilikan lahan antara perusahaan besar dan masyarakat semakin timpang. Dimana untuk satu provinsi saja tanah sudah dikuasai perusahaan besar perkebunan sawit, pertambangan, HPH dan HTI.
Peningkatan izin pertambangan membuat krisis sosial dan ekologi makin meingkat. Kekerasan, Kerusakan lingkungan, kriminalisasi, konflik selalu terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Berbicara tambang bukan semata membahas seberapa besar rupiah yang masuk ke kas negara, namun juga berkaitan erat dengan keselamatan dan ruang hidup warga. Hal ini bisa dilihat dengan munculnya 10.935 izin usaha pertambangan yang memiliki luasan lebih dari 40 juta hektar wilayah daratan Indonesia (Data Jatam, 2013). Pulau Kabaena yang hanya memiliki luas 86.769 Ha, sudah dikavling 35 izin konsesi tambang dengan luas 66.166 Ha atau 76% sudah dikavling oleh tambang.
Kesemerawutan tata pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia muncul dari difungsikannya hutan sebagai potensi ekonomi nasional, dimana dijadikan sebagai indikator nilai kontribusi pertubuhan ekonomi sektor kehutanan melalui konsesi-konsesi yang dikeluarkan untuk HPH, HTI, HPHH. Dalam perkembangannya, pemerintah mengeluarkan izin dalam pemanfaatan kehutanan sosial melalui SK Menhut nomor 31 Tahun 2002 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKM). Dalam mendukung sistem pengelolaan dan pemanfaatan hutan di masyarakat, keluarlah PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan penggunaan kawasan Hutan. Di dalamnya diatur mengenai sistem yang bisa dikelola oleh masyarakat. Berdasarkan SK tersebut, KPSHK mencoba melakukan identifikasi di tahun 2010 kawasan SHK yang berpotensi dalam mengembangkan skema perhutanan sosial. Dari hasil identifikasi tersebut, diperoleh bahwa Hutan Adat Desa di wilayah SHK mencapai 2686.64 Ha; usulan untuk hutan adat desa seluas 719.04 Ha; HKM mencapai 27,674.04 Ha; Hutan Rakyat mencapai 2100 Ha; Hutan Tanaman Rakyat mencapai 72,375.69 Ha.
Konflik-konflik tersebut terjadi seiring dengan proses regulasi yang memberikan porsi yang lebih besar kepada pengusahaan skala besar seperti perkebunan dan pertambangan, dan dengan sengaja menahan dan memberikan porsi yang sangat kecil terhadap pengelolaan berbasis masyarakat, bahkan saat program HKM, HD atau HTR ditargetkan. Berdasarkan alokasi pemanfaatan hutan untuk produksi pada tahun 2010, 97,5% atau sekitar 34,3 juta hektar dikelola oleh korporasi, sisanya 2% atau sekitar 678.414 hektar dikelola oleh masyarakat. Berdasarkan luasan penguasaan perkebunan besar seluruh Indonesia, pada tahun 2008 didominasi oleh perkebunan sawit yang diperkirakan mencapai 79% atau sekitar 4,5 juta ha. Sementara dari total luasan perkebunan sawit, 61% dikuasai oleh perkebunan besar, dan sisanya dikuasai oleh rumah tangga petani (39%).
Beragam komentar di atas terungkap dalam peluncuran Sistem Geo-Data National (GDN) CSO (Civil Society Organization) Versi 3.0. Sistem GDN ini berupaya untuk memperkuat advokasi dalam mempertegas wilayah kelola rakyat atas sumber daya alam melalui suatu penyajian sistem data dan informasi spasial yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penyelesaian konflik sumberdaya alam dan ketimpangan penguasaan sumberdaya alam. Bahkan sistem GDN ini berharap menjadi cikal-bakal database bagi lembaga tinggi negara dalam penyelesaian konflik agraria dan lingkungan.***
###
Informasi lebih lanjut:
Agung, Huma: 0812 8114 0154
Anwar/Uteng, Jatam: 081287914635
Arie Munir, KpSHK: 0812 572 4674
Yusriansya Kent, KPA: 081331643545
Ratriyono/Andi, FWI : 0816103468
Rahmat Sulaiman, JKPP: 082194224676
Bondan Andriyanu, Sawit Watch: 082125570136
Kusuma Bambang, Buka Peta: 08128631303
Catatan Redaksi:
- Geodata Nasional (GDN) adalah suatu sistem database bersama diinisiasi oleh beberapa lembaga NGO diantaranya JKPP, Sawit Watch, KpSHK, KPA, FWI, Jatam, Huma, dan Bukapeta. Dalam pengembangan sistem database GDN ini yang menjadi targetnya penyajian sistem GDN ialah publik. dimana publik dibagi menjadi 3 kategori di GDN, pertama ialah publik yang merupakan bagian langsung dari pendukung jaringan kerja sistem GDN. Kedua, publik yang terbiasa dengan akses internet dalam pencarian berbagai hal mengenai kondisi pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Ketiga, publik yang memang jauh dari akses internet, dimana jaringan kerja GDN menyediakan dan juga menyajikan suatu report 3 bulan berupa liflet maupun jurnal. Dari hasil kompilasi dan juga analisis tim kerja GDN ini akan membantu publik dalam mengetahui kondisi pengelolaan Sumberdaya alam bahkan juga ikut terlibat, sehingga pengembangan sistem database GDN mejadi bagian dalam suatu sistem penyediaan data dan informasi yang interaktif bagi penggunannya. Laman data tersebut dapat dikunjungi di http://geodata-cso.org/



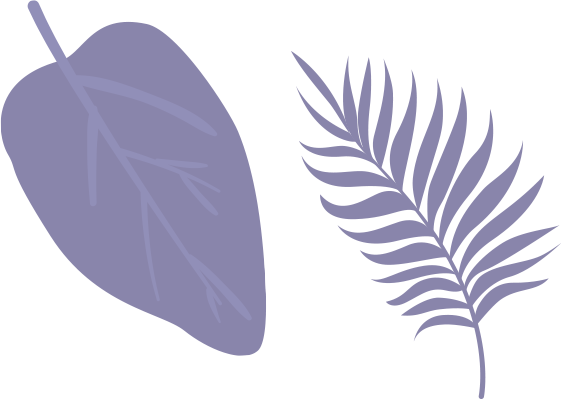
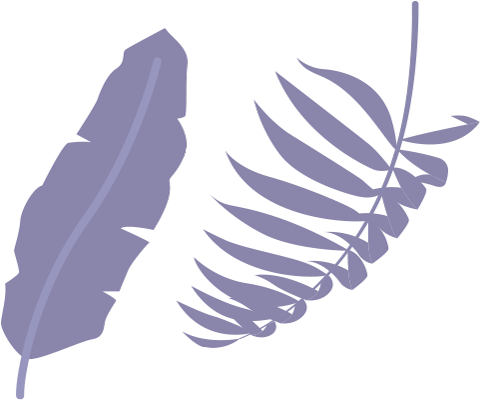
0 Komentar
Tinggalkan Balasan