Artikel ini dimuat di dalam majalah Warta Tenure Edisi-10, 2012 ISSN-1978-1865
oleh: Sisilia Nurmala Dewi dan Andiko (Perkumpulan HuMa)
Persoalan tenurial masih belum bisa dilenyapkan dalam pengelolaan kehutanan di Indonesia. Persoalan tenurial yang dimaksud adalah perihal tumpang tindih penguasaan kawasan hutan. Berdasarkan hasil observasi terhadap artikel media massa nasional, 359 peristiwa konflik di sector kehutanan telah terjadi dari Januari 1997 sampai dengan Juni 2003[2]. Dari 359 kasus konflik yang berhasil dicatat, 39% diantaranya terjadi di areal HTI, 34% di kawasan konservasi (termasuk hutan lindung dan taman nasional), dan 27% di areal HPH. Dalam sebuah pendataan yang dilansir oleh HuMa dinyatakan bahwa pada tahun 2011 konflik sumber daya alam yang terjadi sejumlah 157 kasus. Di atara kasus-kasus tersebut, sebanyak 65 kasus atau sebesar 41% dari keseluruhan konflik merupakan konflik yang terjadi di kawasan hutan. Jumlah ini merupakan yang terbesar dibanding kasus-kasus di sector lain. Ketidakpastian dan ketimpangan penguasaan kawasan hutan telah menghambat pencapaian efektivitas dan keadilan dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat maupun masyarakat local, yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi bisnis kehutanan dan pemerintah[3].
Dalam sebuah pertemuan petani hutan di Jawa Tengah pada tahun 2006[4], diketahui berbagai permasalahan dalam pengelolaan hutan Jawa. Pertama, persoalan yang berkaitan dengan asal-usul atau sejarah tanah; kedua, penentuan tata batas lahan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat; ketiga, perbedaan konsep masyarakat dan Perhutani tentang hutan dan pengelolaannya; keempat, masyarakat tak bisa mengelola hutan sendiri; kelima, persoalaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat; keenam, Operasi Hutan Lestasi (OHL) yang berujung pada penangkapan petani hutan. Dari situ kita bisa melihat konflik tenurial hutan yang kuat antara masyarakat, dalam hal ini petani, dengan perusahaan Negara. Ini sehubungan dengan klaim hutan Negara di atas hutan adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Klaim hutan Negara memberi ruang bagi penguasaan Negara yang secara sepihak atas hutan melalui perusahaan-perusahaan yang dimilikinya atau pemberian izin di atasnya dengan otoritas yang dimiliki pemerintah daerah.
Menjadi jelas kemudian bahwa tumpang tindih klaim atas hutan terjadi di antaranya akibat legislasi dan kebijakan yang tidak terformulasi secara jelas, pemberian izin yang tak terkoordinir dan dinafikannya pengakuan terhadap masyarakat adat dan masyarakat local pengguna hutan lainnya. Konflik ini juga diawali dengan pandangan yang paling mendasar tentang pengelolaan hutan. Selama ini, hutan dipandang hanya objek. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Hariadi Kartodihardjo, Guru Besaar Kebijakan Kehutanan di Fakultas Kehutanan IPB. Pengelolaan kehutanan selama ini berbasis pada doktrin yang diambil dari pengelolaan hutan yang berasal dari Eropa Kolonial, yaitu hutan masih dipandang sebagai penghasil utama kayu, mempertahankan kelestarian hasil hutan berjangka panjang, dan hutan sebagai objek pengetahuan ilmiah. Maka, dalam tahap implementasi kebijakan, yang dituju adalah mendapat manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya dari pemanfaatan hutan. Hal ini, tanpa mengindahkan keberadaan masyarakat baik adat maupun local yang tinggal di hutan dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan sumber daya alam yang disediakan sang Ibu Bumi., Di kawasan hutan, lebih dari 40 juta orang hidup dan menggantungkan hidupnya pada hutan. Menurut Kementrian Kehutanan (Kemenhut), lebih dari 10 juta jiwa komunitas tersebut hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, perlu diingat, mereka telah ada secara turun-temurun sebelum Negara terbentuk, dan sebelum hutan mereka terjebak dalam hegemoni hutan Negara. Di samping itu, kebijakan yang sektoral dan desentralisasi yang merebak dalam dasawarsa terakhir memperparah pula kondisi ini.
Untuk memperbaiki situasi ini, dan membawa kepastian dan keadilan tenurial, diperlukan aksi bersama pemerintah dan kelompok masyarakat sipil pada tiga ranah utama, yang meliputi: pertama, perbaikan kebijakan dan percepatan proses pengukuhan kawasan hutan; kedua, penyelesaian konflik kehutanan; ketiga, perluasan wilayah kelola rakyat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat local lainnya[5]. Upaya mereformasi kebijakan tenurial ini merupakan mandat dari UUD 1945, TAP MPR No IX/MPR/2001 tentang. Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Ranah pertama, yakni perbaikan kebijakan dan percepatan proses pengukuhan kawasan hutan, penting untuk mengatasi ketidakpastian legal atas kawasan hutan. Sebagai awal dari proses, yang perlu dilakukan aalam penunjukkan, penetapan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan sehingga terdapat suatu kawasan hutan yang legal dan legitimate. “Legal” berarti secara hukum sudah mengikuti tata aturan yang sudah ditetapkan (baik secara procedural maupun substansi), sementara “legitimate” berarti terdapat pengakuan dan penerimaan dari pihak lain terhadap tata batas dan keberadaan kawasan hutan tersebut. Langkah pertama ini penting dalam hal bertemu tiga kepentingan yang berbeda di lapangan hutan yang sama, antara Negara, masyarakat sekitar hutan dan pemegang izin usaha kehutanan. Tentunya, ini memerlukan partisipasi dari ketiganya. Tidak saja sepihak dari pemerintah yang kemudian menjadi sumber konflik. Partisipasi masyarakat terutama sebagai manusia dengan hak-hak dasar yang perlu dilindungi dan dihormati tidak boleh diabaikan dan harus dilihat sebagai peluang untuk menghindari konflik-konflik di masa mendatang. Dalam kerangka kebijakan, penting pula diselesaikan pengurusan tanah yang selama ini berada di bawah dualisme sektoral antara Kemenhut dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sementara ranah pertama adalah langkah pencegahan, langkah ranah adalah langkah penyelesaian terhadap konflik-konflik tenurial yang telah maupun tengah terjadi. Sebetulnya, selama ini terdapat banyak inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini. Namun dinilai belum ada mekanisme penyelesaian yang bersifat komprehensif dan terlembaga. Oleh karena itu, kecepatan penyelesaian konflik lebih lambat dari lahirnya konflik baru. Keterlibatan pemerintah di ranah penyelesaian konflik bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementrian Kehutanan saja, tetapi juga perlu melibatkan instansi pemerintah pada sektor lain yang seringkali menerbitkan izin penyebab tumpang tindih penguasaan hutan, semisal untuk izin pertambangan, perkebunan, transmigrasi dan sebagainya. Egosektoral ini harus diatasi dengan koordinasi yang lebih kokoh antar instansi. Pada kelompok masyarakat sipil sendiri, mengusulkan pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria yang berlanjut dengan pembentukan Badan Otorita Reforma Agraria. Penyelesaian konflik ini tidak akan efektif tanpa prasyara-prasyarat berupa (1) kepercayaan semua pihak, (2) ketersediaan data dan pengolahan data yang akuntabel, (3) ketersediaan sumber daya manusia dan danayang memadai, (4) unit penanganan pengaduan sebagai lini terdepan pencegahan konflik, (5) keberlanjutan penanganan konflik , serta (6) keadilan dan kesejahteraan bagi korban.
Ranah ketiga, merupakan penguatan basis komunitas dalam pengelolaan hutan yang berujung pada perluasan kawasan kelola rakyat dan peningkatan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Dalam konflik tenurial, kondisi masyarakat di kawasan memang seperti jatuh dan tertimpa tangga. Jarang sekali diuntungkan. Pun jika diberi hak-hak istimewa lewat kebijakan Hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa, hutan tanaman rakyat (HPR) dan kemitraan, capaiannya sangat. Total yang diterbitkan sangat jauh dari perizinan untuk pengusahaan hutan dalam skala besar. Maka dari itu, pengakuan Negara terhadap hak-hak masyarakat adat sebetulnya sangat-sangat penting. Keberadaan mereka sebagai subjek hukum yang diakui Negara kiranya merupakan senjata yang cukup ampuh untuk menuntut hak mereka atas hutan yang telah lama mereka tinggali serta sumber pemenuhan kebutuhan hidup yang vital. Di samping itu pemberdayaan masyarakat adat baik secara hukum, lingkungan, maupun ekonomi tidak boleh dikesampingkan. Dengan peningkatan kapasitas komunitas basis, maka mereka dapat berupaya merebut hak-hak rakyat atas tanah dan mengolahnya dengan baik utnuk meningkatkan kesejahteraan sehingga masyarakat dapat membuktikan bahwa mereka layak diberi hak kelola hutan tersebut. Masyarakat adat dan local di kawasan hutan senyatanya tak membutuhkan pihak ketiga seperti perusahaan besar yang akan memberikan bantuan sosial, pendidikan dan semacamnya untuk menjadi sejahtera.
Bicara hutan yang memiliki peran besar dalam mengakibatkan perubahan iklim, kita tak bisa lari dari kebijakan-kebijakan internasional berkaitan dengan pencegahannya. Saat ini, kita banyak mendengar tentang kebijakan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). REDD merupakan suatu mekanisme global yang bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang untuk melindungi hutannya[6]. Tanda ‘plus’ di belakangnya menambahkan konservasi dan pengelolaan hutan secara lestari, pemulihan hutan dan penghutanan kembali, serta peningkatan cadangan karbon hutan. REDD+ sangat terkait dengan konflik kehutanan, karena REDD+ adalah aktivitas berbasis lahan. Proyek-proyek REDD+ pada akhirnya akan meminta lahan-lahan, semisal hutan atau tanah terlantar, yang ditengah koordinasi instansi pemerintah bernafaskan sektoralisme, mengalami tumpang tindih perizinan pemanfaatan. Dalam demonstration activities REDD di Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, hak masyarakat untuk dilibatkan dalam penentuan wilayah REDD berupa free, prior, and informed consent (FPIC) telah diabaikan sedemikian rupa oleh pemrakarsa. Sementara, kompensasi atas pengurangan karbon masuk kantong pemerintah, masyarakat justru dibebani dengan kegelisahan yang teramat sangat atas status kepemilikan tanah dan akses penguasaan hutan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Dalam konteks pelaksanaan yang demikian, REDD+ tak bisa dikatakan sebagai solusi, melainkan bebas.
Akan tetapi, para penggagas dan lingkar penjaga system REDD dengan intensi yang fundamental (meminimalisis perubahan iklim akibat laju deforestasi) tentu juga berefleksi dari pengalaman ini. Oleh karena itu, belakangan ini dibuatlah strategi nasional REDD yang mengadakan perubahan paradigm yang salah satunya berinisiasi untuk memperbaiki tata kelola hutan. Sebab tata kelola hutan yang buruk adalah sebab mendasar deforestasi. REDD+ juga bergerak secara strategis dalam melakukan intervensi pengharmonisasian kebijakan tentang hutan termasuk resolusi konflik tenurial.
Karena itu, program REDD tidak dapat dijalankan tanpa upaya resolusi konflik kehutanan dan kepastian hak tenurial masyarakat atas hutan. Sehingga program REDD dapat menjadi peluang dan pintu masuk bagi penyelesaian konflik kehutanan dengan syarat adanya pengakuan hak tenurial masyarakat atas hutan dan dapat pula menjadi ruang konflik baru ketika hak tenurial masyarakat tidak diakui.
[1] Dimuat dalam Majalah Warta Tenure Edisi-10,2012 ISSN-1978-1865
[2] Yuliana Cahya Wulan, dkk, Analisis Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003, (Bogor: CIFOR, 2004), hal. 8.
[3] Myrna Safitri, dkk, Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial: Pandangan Kelompok Masyaraka Sipil Indonesia tentang Prinsip, Prasyarat, dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan di Indonesia, (Jakarta: koalisi masyarakat sipil, 2011), hal, 1.
[4] Proceeding Workshop Multi Pihak: Issue Illegal Logging Berkaitan Dengan UU 41/1999 (Tinjauan Terhadap Operasi Hutan Lestari), LBH Semarang & HUMA, Semarang, 24-26 April 2006.
[5] Ibid., hal. 6
[6] http://www.redd-indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=68


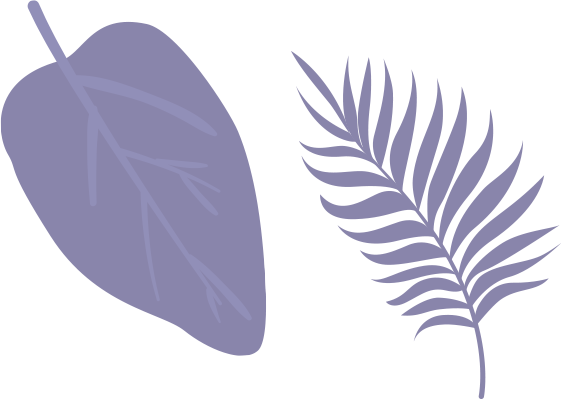
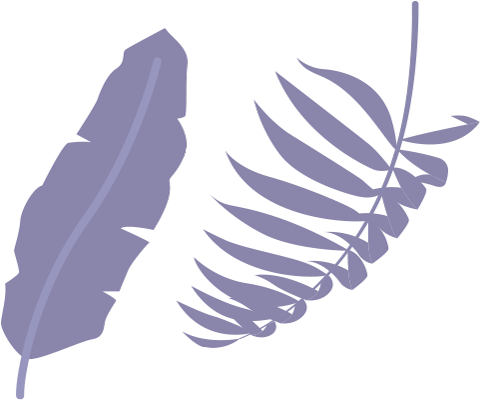
0 Komentar
Tinggalkan Balasan