
Membara, Menyebar dan Meluas
Konflik sumberdaya alam dan agraria sepanjang tiga tahun terakhir menyita perhatian publik mengingat intensitas ledakannya yang cukup sering. Ada tren yang cukup kuat, konflik yang dulu bersifat laten berubah menjadi manifes. Perbedaan sistem penguasaan lahan antar pihak dalam konflik agraria tak kunjung ada kepastian. Masyarakat gigih mempertahankan hak penguasaannya secara turun-temurun dan bersifat informal, sementara perusahaan dan para pihak lain datang dengan sistem aturan formal yang tidak dikenal dalam kebiasaan masyarakat.
Konflik bermula dari pertentangan dua sistem ini yang meletusnya dipicu dengan keinginan salah satu pihak untuk memaksakan sistemnya kepada pihak lain. Banyak konflik yang mulanya terjadi secara diam-diam, tiba-tiba meletus ke permukaan.
Perubahan tren konflik tersebut terjadi merata di seluruh Indonesia. Kita bisa simak mulai dari Mesuji di Lampung Utara, Ogan Komering Ilir, Kebumen, hingga Sumbawa. Outlook Konflik 2012 ini menggambarkan sebaran, para pihak, jenis konflik, sektor dan dimensi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
Konflik ini direkam dan didokumentasikan HuMa melalui sistem HuMaWin sejak 2006 sampai pendataan akhir tahun 2012. Tidak dalam periode setahun saja. Berikut peta sebaran konflik yang didokumentasikan HuMa:
1) Sebaran Konflik
Hingga November 2012, HuMa mendokumentasikan 232 konflik sumberdaya alam dan agraria. Ratusan konflik tersebut terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia dengan tingkat frekuensi yang berbeda. Beberapa provinsi tidak masuk karena keterbatasan data yang ada. Sangat mungkin provinsi seperti ini justru memiliki intensitas konflik yang tinggi.
Sebut saja seperti Provinsi Papua, dimana megaproyek ambisius pengadaan lumbung pangan Merauke Integrated Food and Energy Estate atau dikenal MIFEE, sedang berlangsung. Proyek ini akan mengkonversi sekitar sejuta hektar lahan yang dikuasai masyarakat adat menjadi areal perkebunan dan pertanian oleh korporasi-korporasi besar.
HuMa mencatat konflik berlangsung di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi. Yang memprihatinkan, luasan area konflik mencapai 2.043.287 hektar atau lebih dari 20 ribu km2. Luasan ini setara dengan separoh luas Provinsi Sumatera Barat. Secara kuantitas, konflik yang didokumentasikan HuMa ini hanya potret permukaan saja. Bisa dibayangkan jika semua konflik berhasil diidentifikasi jumlah dan luasannya yang pasti akan jauh lebih besar.
Dari 22 provinsi konflik yang didokumentasikan HuMa, tujuh provinsi di antaranya memiliki konflik paling banyak, yakni Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
|
Provinsi dengan Konflik Terbanyak | ||||||||||||
|
No |
Provinsi |
Jumlah kasus |
Luas Lahan (hektar) | |||||||||
|
1 | Kalimantan Tengah |
67 kasus |
254.671 | |||||||||
|
2 | Jawa Tengah |
36 kasus |
9.043 | |||||||||
|
3 | Sumatera Utara |
16 kasus |
114,385 | |||||||||
|
4 | Banten |
14 kasus |
8,207 | |||||||||
|
5 | Jawa Barat |
12 kasus |
4,422 | |||||||||
|
6 | Kalimantan Barat |
11 kasus |
551,073 | |||||||||
|
7 | Aceh |
10 kasus |
28.522 | |||||||||
Kalimantan Tengah menjadi provinsi yang paling banyak konflik, dimana 13 dari 14 kabupaten dan kotanya memendam masalah klaim atas sumberdaya alam dan agraria. Artinya, konflik berlangsung merata di wilayah administratif provinsi tersebut. Sebanyak 85% dari kasus di Kalimantan Tengah terjadi di sektor perkebunan. Sedangkan 10% merupakan konflik di sektor kehutanan. Sisanya adalah konflik pertambangan dan konflik lainnya.
Meluasnya ekspansi perkebunan monokultur seperti sawit di Kalimantan tak ayal membuat luas hutan berkurang drastis. Perubahan status kawasan hutan melalui mekanisme pelepasan, tukar-menukar yang tak seimbang, maupun izin pinjam pakai marak terjadi dan cenderung kian tak terkendali. Akibatnya, konflik klaim adat atas wilayah hutan melawan penunjukan sepihak oleh negara yang paling sering terjadi, makin runyam. Ketika kasus macam ini belum tuntas, kini konflik bertambah antara masyarakat dengan perusahaan.
Keempat provinsi se-Kalimantan menyumbang angka 36 persen konflik secara keseluruhan dari data konflik HuMa. Konflik-konflik yang terjadi di provinsi-provinsi lain di Nusa Tenggara, Sulawesi, Sumatera dan Jawa juga menunjukkan kondisi yang mencemaskan.
Tipologi konflik yang terjadi di Sumatera hampir mirip dengan Kalimantan, yakni konflik klaim komunitas lokal atau masyarakat adat dengan negara dan perusahaan. Dua pulau besar ini memiliki kawasan hutan yang luas dan belakangan menjadi wilayah dominan ekspansi perkebunan sawit di Indonesia.
Sementara konflik di Jawa, lebih banyak menyangkut sektor kehutanan, dimana gugatan masyarakat terhadap penguasaan wilayah oleh Perhutani masih dalam deretan teratas. Konflik yang melibatkan Perhutani terjadi di seluruh wilayah kerja perusahaan plat merah tersebut, yaitu di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Data resmi Perhutani menunjukkan bahwa perusahaan ini menguasai kawasan hutan seluas 2,4 juta hektar. Terdapat sekitar 6.800 desa yang berkonflik batas dengan kawasan Perhutani di Pulau Jawa.
2) Konflik Dilihat dari Sektor
Menurut data HuMa, konflik perkebunan dan kehutanan menjadi konflik yang paling sering terjadi di Indonesia. Konflik di dua sektor ini mengalahkan konflik pertanahan atau agraria non kawasan hutan dan kebun. Konflik perkebunan terjadi sebanyak 119, dengan luasan area konflik mencapai 413.972 hektar.
Meski frekuensi konflik kehutanan lebih sedikit dibanding konflik perkebunan, namun secara luasan konflik sektor ini paling besar. Dari 72 kasus, luas area konflik kehutanan mencapai 1.2 juta hektar lebih.
Meluasnya area konflik sektor perkebunan ditengarai sebagian besar berada di kawasan hutan. Hutan yang sebelumnya ditumbuhi pohon-pohon lebat dan banyak yang dikelola oleh masyarakat, dalam satu dekade mengalami deforestasi yang amat parah. Tingkat konversi hutan cukup tinggi di daerah dimana ekspansi sawit merajalela.
Dorongan untuk memacu laju investasi sektor perkebunan sawit diduga memperkuat tekanan atas kebutuhan lahan, dan yang paling rentan dikorbankan adalah kawasan berhutan. Ini terjadi di Nagari Rantau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang melibatkan PT. Anam Koto. Perusahaan ini memegang hak guna usaha seluas 4,777 hektar di atas tanah yang dulunya diklaim sebagai wilayah hutan adat. Pendampingan kasus ini dikerjakan oleh Q-Bar, mitra HuMa yang berbasis di Sumatera Barat.
a) Konflik Kehutanan dan Akarnya
Konflik sektor kehutanan pada umumnya disebabkan hak menguasai negara secara sepihak pada tanah-tanah yang dikuasai oleh komunitas lokal secara komunal. Politik penunjukan tanah yang diklaim milik negara menyulut perlawanan yang menyebabkan konflik berlarut-larut.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemenhut tahun 2007 dan 2009, terdapat 31.957 desa yang saat ini teridentifikasi berada di sekitar dan dalam kawasan hutan yang sedang menunggu proses kejelasan statusnya. Di banyak desa bahkan hampir secara keseluruhan wilayah administratifnya berada di dalam kawasan hutan lindung atau konservasi yang berarti dapat dengan mudah dianggap sebagai tindakan ilegal, bila ada masyarakat yang memungut atau mengambil kayu hasil hutan.
Ambil contoh Desa Sedoa yang terletak di Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Wilayah administratif desa ini hampir 90 persen berada di kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Lore-Lindu. Kasus Desa Sedoa kini masih dalam proses pendampingan oleh Bantaya, mitra HuMa yang berada di Palu, Sulawesi Tengah. Atau Kelurahan Battang Barat, Kota Palopo, yang sekitar 400 hektar terkena perluasan kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Nanggala III yang diadvokasi oleh Wallacea.
Bagi desa yang berada dalam kawasan hutan, seperti Desa Sedoa atau Kelurahan Battang Barat, maka atas tanah-tanah dalam desa tersebut tidak dapat diterbitkan sertifikat atau bukti terkuat kepemilikan atas tanah. Domain pengaturan tanah dalam kawasan hutan berada dalam rezim Kementerian Kehutanan, sementara sertifikat atau registrasi tanah berada di bawah Badan Pertanahan Nasional.
Sepintas masalah desa-desa di sekitar dan di dalam kawasan hutan ini masalah administratif. Akan tetapi perbedaan rezim ini berimplikasi pada pelayanan publik, jaringan infrastruktur, dan lain sebagainya, yang rentan menghadirkan diskriminasi bagi masyarakat desa dalam kawasan hutan tersebut.
Selain konflik mengenai kejelasan status wilayah administratif, konflik kehutanan juga dilatari perbedaan cara pandang antara perusahaan dengan komunitas setempat atas jenis tanaman yang ditanam. Biasanya konflik seperti ini maraknya terjadi pada area-area konsesi hutan produksi atau hutan tanaman industri yang memiliki tutupan primer. Perusahaan membutuhkan lahan skala luas untuk ditanami bahan baku pembuatan kertas atau kayu lapis olahan.
HuMa mencatat salah satu contoh konflik kehutanan kategori ini terjadi pada kasus PT. Toba Pulp Lestari di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Perusahaan membabat Hutan Kemenyan (Tombak Haminjon) yang sudah dikuasai secara turun temurun oleh masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, dan menggantinya dengan pohon ekaliptus.
Terjadi pula pada kasus PT. Wira Karya Sakti yang membabat hutan primer untuk ditanami akasia dan ekaliptus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Serta kasus PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Semenanjung Kampar, Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau.
b) Akar-akar Konflik Perkebunan
Sementara itu, jika konflik sektor perkebunan tidak mendapat perhatian serius, bukan tak mungkin luas lahan yang disengketakan akan menyamai, bahkan melebihi luas area kehutanan yang berkonflik.
Konflik perkebunan yang massif terjadi belakangan secara tidak langsung dipicu oleh ambisi Pemerintah untuk menjadikan sawit sebagai komoditas unggulan Indonesia yang terbesar di dunia.
Dalil ini kemudian dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha sawit untuk mendapatkan berbagai proteksi dari Pemerintah. Parahnya, Pemerintah lokal juga turut ‘bermain’ dalam memudahkan penguasaan lahan dan pengoperasian perkebunan sawit di daerahnya dengan pertimbangan ekonomi-politik jangka pendek.
Dari data HuMa, paling tidak terdapat 14 provinsi yang tercatat memiliki konflik perkebunan yang mayoritas terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Banyak sumber yang merilis data mengenai konversi besar-besaran kawasan hutan menjadi area perkebunan kelapa sawit. Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, misalnya, menyebut penyusutan kawasan hutan seluas 1,1 juta hektar di Jambi dalam dua dekade terakhir.[1]
c) Konflik Pertambangan
Data konflik sektor pertambangan agaknya memang tak sebanyak konflik kehutanan dan perkebunan. Akan tetapi konflik sektor ini sangat mudah meletup dibanding sektor kehutanan, yang cenderung bersifat laten. Dari pantauan HuMa, komunitas lokal sangat gigih mempertahankan wilayah kelolanya yang dirampas oleh perusahaan dengan izin konsesi tambang, tanpa ada pertimbangan persetujuan dengan dasar informasi tanpa paksaan atau free, prior and informed consent (FPIC).
Wilayah-wilayah pertambangan perusahaan umumnya berada di kawasan yang memiliki dimensi religius-magis bagi masyarakat adat setempat. Perusahaan berdalih memegang izin formal, masyarakat kukuh mempertahankan wilayah yang sakral bagi leluhur mereka. Konflik pun termanifes.
Konflik pertambangan memiliki kecenderungan sering terjadi bentrok fisik di dalamnya. Korban luka banyak berjatuhan, beberapa di antaranya sampai meninggal dunia.
Dalam konflik pertambangan, perusahaan hampir selalu tampil sebagai pemenang. Aparat polisi, jaksa, hingga hakim cenderung lebih mengutamakan pihak yang memegang konsesi sebagai alas hukum ketimbang adat yang dianggap tak resmi atau formal.
Perusahaan tambang sendiri dengan mudah membelokkan tudingan penyerobotan tanah, kawasan hutan atau pencemaran lingkungan sebagai efek destruksi pengolahan tambang terhadap lingkungan, menjadi persoalan administrasi konsesi atau kontrak karya.
Tak jarang justru perusahaan-perusahaan dibantu aparat penegak hukum melakukan kriminalisasi terhadap warga yang melakukan protes dengan dalih anarkis. Warga ditangkapi, ditahan, bahkan banyak yang dipenjarakan. Seperti yang terjadi pada PT. Sorikmas Mining yang beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Mahkamah Agung dalam putusan hak uji materi SK Menteri Kehutanan No.126-Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Kawasan Taman Nasional Batang Gadis memenangkan perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh Aberifoyle Pungkut Investment Singapura ini. Terkait kasus yang sama, lima orang masyarakat Desa Huta Godang Muda diseret ke pengadilan atas laporan PT. Sorikmas.
Di Kalimantan Barat, tepatnya di Pelaik Keruap, Kabupaten Melawi, yang merupakan daerah dampingan Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), tiga orang tokoh komunitas setempat dihukum penjara dengan dakwaan menahan tanpa hak rombongan surveyor perusahaan eksplorasi tambang PT. Mekanika Utama yang masuk kampung tengah malam. Padahal masyarakat setempat sejatinya berniat untuk menanyakan maksud kedatangan rombongan saat itu.
Kasus kriminalisasi dalam konflik pertambangan juga menimpa empat warga Sirise, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Mereka dihukum lima bulan penjara karena mempertahankan lingko atau hutan adat yang diserobot konsesi perusahaan tambang.
3) Siapa Para Pihak yang Terlibat Konflik?
HuMa dengan menggunakan sistem pendokumentasian HuMaWin, mengidentifikasi para pihak bersifat komunal. Unit terkecilnya adalah komunitas, masyarakat, atau kelompok. Tidak individual. Ada sembilan pihak yang terlibat dalam konflik sumberdaya alam dan agraria yang diidentifikasi HuMa, yaitu:
a) Masyarakat Adat;
b) Komunitas Lokal;
c) Kelompok Petani;
d) Taman Nasional/ Kementerian Kehutanan;
e) Perhutani;
f) PT. Perkebunan Nusantara (PTPN);
g) Perusahaan/ Korporasi;
h) Perusahaan Daerah;
i) Instansi Lain.
Masyarakat adat dengan komunitas lokal sengaja dibedakan untuk menjelaskan perbedaan klaim historis atas lahan konflik. Sementara kelompok petani diidentifikasi bagi pihak yang terkait dengan relasi kontraktual dengan perusahaan. Ketiga pihak ini merupakan pihak yang menjadi korban. Kementerian Kehutanan masuk sebagai pihak yang berkonflik karena kewenangan institusionalnya yang melekat untuk menunjuk hingga menetapkan kawasan hutan.
|
Para Pihak |
Frekuensi dalam Konflik |
| Perusahaan/Korporasi |
158 |
| Komunitas Lokal |
153 |
| Petani |
41 |
| Masyarakat Adat |
34 |
| Perhutani |
30 |
| Taman Nasional/ Kemenhut |
20 |
| PTPN |
11 |
| Pemerintah Daerah |
7 |
| Instansi lain |
2 |
Perhutani sebagai institusi dipisahkan dengan Kementerian Kehutanan. Sebagai unit bisnis yang memiliki sejarah dan area konsesi tersendiri, perusahaan plat merah yang mengelola hutan Jawa ini patut dipertimbangkan sebagai pihak yang berkonflik. Dasar pendirian Perhutani pertama kali adalah Surat Keputusan Gubernur Jenderal (Staatblad No. 110 tahun 1911) dan mengalami berkali-kali revisi terakhir adalah Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara.
Demikian pula PTPN. HuMa dalam setahun terakhir mencermati perkembangan perusahaan negara di sektor perkebunan ini, terutama terkait konflik lahan. Posisinya dalam peta ekonomi nasional semakin signifikan tatkala kebijakan nasional mendorong pertumbuhan investasi dengan menggenjot produksi komoditas dalam negeri. HuMa menganggap penting mendudukkan PTPN sebagai unit pelaku yang terlibat konflik secara tersendiri, terpisah dengan entitas perusahaan (swasta). Menurut data yang didokumentasi HuMa, paling tidak PTPN terlibat dalam 11 kasus konflik agrari, tentu kesemuanya berada di sektor perkebunan.
PTPN berperan penting sebagai produsen komoditas andalan nasional, seperti gula dan kopi. Tak heran bila Menteri Negara Urusan Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN), Dahlan Iskan, yang membawahi PTPN, mati-matian membela luasan wilayah PTPN ketika meletup kasus Cinta Manis, Sumatera Selatan, yang digugat warga karena telah menyerobot tanah mereka.
Instansi lain di sini merujuk pada organ kekuasaan yang ternyata mengklaim punya penguasaan atas tanah, seperti TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut.
Dari data yang dihimpun HuMa, perusahaan/korporasi atau koperasi menempati urutan pertama sebagai pelaku dalam konflik agraria dan sumberdaya alam. Perusahaan/korporasi banyak terlibat konflik di sektor perkebunan dan pertambangan berlawanan dengan komunitas lokal, masyarakat adat, bahkan dengan kelompok petani. Bila terlibat di sektor kehutanan, dapat dipastikan mereka terlibat di kawasan hutan yang status kawasannya hutan produksi.
Frekuensi keterlibatan perusahaan/korporasi mencapai 35% dari keseluruhan data pelaku yang didokumentasikan HuMa. Posisi perusahaan/korporasi sebagai pelanggar hak asasi manusia yang tinggi juga tercatat dalam laporan yang dirilis oleh Komnas HAM atau lembaga advokasi seperti Walhi. Hal ini menunjukkan makin besarnya peran perusahaan/korporasi di segala sektor kehidupan masyarakat, menggeser peran dominan negara.
Dominannya swasta bisa kita simak lewat perputaran uang yang melibatkan sektor swasta. Menurut Sofian Wanandi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), perputaran uang di swasta mencapai Rp. 7.000 trilyun. Bandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya sekitar Rp. 1.200 trilyun.
Dengan demikian peran swasta di masa depan, dapat dipastikan akan membesar. Ini catatan penting untuk diantisipasi dalam proses penyelesaian konflik agraria yang akan mengorbankan masyarakat.
Taman Nasional atau dalam hal ini Kementerian Kehutanan pada umumnya terlibat dalam sengketa tata batas atau perluasan kawasan secara sepihak oleh Kementerian Kehutanan, seperti terjadi di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS), yang tertuang dalam SK Menhut No. 175/Kpts-II/2003.
Seperti yang diidentifikasi Rimbawan Muda Indonesia (RMI), paling tidak terdapat 314 kampung yang terkena perluasan itu yang tersebar di sekitar kawasan Gunung Halimun-Salak, di Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Lebak. Salah satu kampung yang terkena perluasan TNGHS adalah Kampung Nyungcung, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dari uraian para pihak yang terlibat dalam konflik agraria dan sumberdaya alam di atas, perusahaan menjadi para pihak yang paling sering menjadi pelaku konflik. Perusahaan terlibat dalam 158 konflik yang didata oleh HuMa. Disusul kemudian Perhutani dengan 30 kasus, dan Taman Nasional 20 kasus, PTPN di 11. Kemudian Pemda dengan 7 kasus dan instansi lain 2 kasus.
Berikut tabel para pihak sebagai pelaku konflik sumberdaya alam dan agraria yang dihimpun HuMa:
4) Tipologi Konflik dan Pelanggaran terhadap HAM
a) Tipologi Konflik Berdasar Pelaku
Secara umum dengan melihat para pihak yang terlibat dalam konflik sumberdaya alam dan agraria, terdapat empat jenis konflik yang dominan terjadi di Indonesia. Posisi perusahaan/korporasi atau koperasi sebagai pelaku utama muncul paling sering di dalam empat tipologi kasus dominan tersebut. Empat tipologi konflik tersebut adalah:
(1) Komunitas Lokal melawan Perusahaan/Korporasi atau Koperasi;
(2) Petani melawan Perusahaan;
(3) Komunitas Lokal melawan Perhutani;
(4) Masyarakat Adat melawan Perusahaan.
Tingginya frekuensi keterlibatan perusahaan ini disumbang dari konflik sektor perkebunan dan pertambangan. Barangkali hampir keseluruhan konflik sumberdaya alam dan agraria berdasar pada perbedaan dasar klaim para pihak yang menyebabkan tumpang-tindih klaim. Dasar klaim formal umumnya dijadikan pegangan oleh perusahaan berhadapan dengan klaim historis nonformal versi komunitas lokal atau masyarakat adat.
Berangkat dari tipologi konflik yang telah dipaparkan, sejumlah pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi di dalamnya.
Sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia, maka saat ini perusahaan atau korporasi dapat dikategorikan sebagai pelaku. Tidak hanya negara. Perusahaan tidak hanya beroperasi dengan bersinggungan dengan dimensi publik atau rakyat, akan tetapi perusahaan atau bisnis juga mengalami pergeseran peran yang dalam banyak hal menggerus kewenangan negara.
Menurut Kerangka Kerja PBB mengenai Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan”, setidaknya terdapat tiga pilar penting dalam hal kaitan bisnis dan hak asasi manusia ini. Pertama, tugas negara untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis, melalui kebijakan, peraturan, dan peradilan yang sesuai.
Kedua, adalah tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, yang berati bahwa perusahaan bisnis harus bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari dilakukannya pelanggaran atas hak pihak lain dan untuk mengatasi akibat yang merugikan di mana mereka terlibat. Ketiga, adalah kebutuhan atas akses yang lebih luas oleh korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, baik yudisial maupun non yudisial.
Dalam realitas di lapangan, perusahaan seringkali menggunakan instrumen atau aparatur negara dalam melakukan tindak kekerasan. Perusahaan dengan modalitas ekonominya mampu mempengaruhi dan bahkan memaksa aparatur negara menghalau demonstrasi atau protes-protes komunitas lokal atau masyarakat adat dengan membabi buta. Contoh kongkrit dalam relasi organisasi bisnis yang menggunakan entitas atau aparat negara yang mengakibatkan korban dapat kita lihat dalam kasus Mesuji atau Cinta Manis yang mengakibatkan korban komunitas lokal berjatuhan.
b) Pelanggar dan Pelanggaran HAM
Sistem pendokumentasian HuMaWin mengklasifikasi kejadian seperti ini masuk dalam kategori peristiwa yang melingkupi kasus. HuMaWin mendokumentasikan konflik dengan dasar kasus, bukan peristiwa. Sehingga keluaran data pelanggar berbeda dengan data para pihak yang bertindak sebagai pelaku dalam konflik yang didokumentasikan.
Bila dalam kategori pelaku konflik, perusahaan atau korporasi menempati urutan teratas, maka dalam kategori pelanggar hak asasi manusia dalam konflik agraria, entitas negara yang menempati pelanggar pertama.
Dari tingginya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi melingkupi konflik agraria menunjukkan bahwa penanganan konflik yang termanifes pada umumnya berlangsung sistematis menyasar pada kelompok masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi menentang konsesi atau izin perusahaan.
Aparat negara, seperti personel Brimob, dalam hal ini cenderung memposisikan dirinya sebagai pihak yang mengamankan aset perusahaan ketimbang melindungi masyarakat. HuMa mencatat sebanyak 91.968 orang dari 315 komunitas telah menjadi korban dalam konflik sumberdaya alam dan agraria.
HuMa juga mengidentifikasi pelaku pelanggar hak asasi manusia dari kalangan individu yang memiliki posisi dan pengaruh dalam kekuasaan, umumnya di tingkat lokal. Kategori pelaku individu ini dialamatkan kepada orang seperti ketua kerapatan adat, yang menggunakan kekuasaan simboliknya sebagai tetua adat untuk menghasut atau menyerang masyarakat yang melakukan protes-protes. Berikut tabel pelanggar HAM yang berhasil dihimpun:
|
Pelaku Pelanggar HAM |
Peristiwa |
Prosentase |
| Entitas Negara |
266 |
53,96% |
| Organisasi Bisnis |
179 |
36,31% |
| Individu dalam posisi memiliki kekuasaan |
48 |
9,74% |
| JUMLAH |
493 |
100,00% |
Dalam konflik sumberdaya alam dan agraria, jenis pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial-budaya—utamanya adalah hak ekonomi, akan tetapi hak sipil-politik dalam berbagai bentuk seperti bentrokan yang disertai penembakan, sweeping, penangkapan, penganiayaan, penggusuran, dan perusakan properti milik komunitas juga kerap dilakukan pelaku.
Berikut contoh beberapa kejadian yang di dalamnya terdapat pelanggaran hak sipil-politik:
|
No |
Daerah |
Pihak yang bersengketa dengan komunitas |
Pelanggaran hak sipil dan politik |
| 1 | Aceh Tamiang | PT Sinar Kaloy Perkasa Indo | Pemaksaan Datok Desa tandatangani rekomendasi perluasan HGU |
| 2 | Muara Enim | Pengusaha Burhan | Penangkapan Junaidi dan Kosim |
| 3 | Pasaman Barat | PT. Permata Hijau Pasaman II | 20 orang terluka, 1 keguguran saat polisi melakukan sweeping. Warga lain trauma todongan senjata. |
| 4 | Tanjung Jabung Barat | PT Wira Karya Sakti | Ahmad (45) tewas ditembak anggota Brimob. |
| 5 | Pasaman Barat | PT. Anam Koto | Penculikan terhadap 2 aktivis dan 5 warga |
| 6 | Binjai | PTPN 2 Sei Semayang | Remi (22) tewas akibat panah beracun saat pertahankan lahan |
| 7 | Bengkalis | PT Arara Abadi | Penangkapan 200 warga disertai kekerasan, 1 balita mati |
| 8 | Manggarai Timur | Pemda Manggarai | Pemukulan terhadap warga yang tolak tanda tagan penyerahan tanah |
| 9 | Minahasa Selatan | PT. Sumber Energi Jaya | Frengky Aringking luka tertembak peluru polisi, penangkapan Yance secara paksa disertai sweeping |
| 10 | Labuhanbatu Utara | PT Smart | Penangkapan terhadap 60 petani, Gusmanto (16) tertembak |
| 11 | Aceh Barat | PT KTS | Tgk Banta Ali ditembak mati pertahankan tanahnya |
| 12 | Ogan Ilir | PTPN VII Cinta Manis | Angga (12) tewas dan 23 orang tertembak Brimob |
| 13 | Kotawaringin Timur | PT. Nabatindo Karya Utama | Penangkapan warga |
| 14 | Sumba Timur | PT. Fathi Resources | 4 warga mengalami luka-luka akibat kerusuhan, 24 warga dikriminalisasikan |
| 15 | Rokan Hulu | PT Merangkai Artha Nusantara | Bentrokan warga dengan preman perusahaan, 5 warga tidak pulang. |
| 16 | Mandailing Natal | PT Sorikmas Mining | Bentrok dengan petugas perusahaan, 4 luka dan 1 mengalami luka tembak |
| 17 | Donggala | PT. Cahaya Manunggal Abadi | Masdudin (50) tewas dan lima lainya tertembak polisi |
Dilihat dari jenis-jenis pelanggaran HAM, pelanggaran terhadap hak rakyat untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber alam yang paling sering terjadi (25%). Umumnya pelanggaran ini terjadi pada sengketa yang terkait dengan kepemilikan kolektif, misalnya sekelompok masyarakat adat yang kehilangan akses mereka terhadap hutan adat akibat penetapan lahan tersebut sebagai hutan negara yang dikelola oleh perusahaan swasta.
Hal ini terjadi pada kasus perampasan tanah ulayat milik masyarakat Tanjung Medang oleh pengusaha di Muara Enim, atau pembabatan hutan Kemenyan milik Kemenyan Humbahas oleh PT Toba Pulp Lestari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.
Kemudian pelanggaran terhadap hak untuk memiliki atau menguasasi kekayaan (19%). Hal ini terjadi pada perampasan tanah-tanah yang dimiliki masyarakat secara individu. Sebagian korban mempunyai surat kepemilikan tanah dan sebagian lain tidak memilikinya. Di Kabupaten Aceh Timur misalnya, terdapat 700 orang yang tanah miliknya dalam sengketa dengan PT Bumi Flora. Warga yang tersebar di 7 desa tersebut tengah menunggu verifikasi tim pemerintah terhadap surat-surat bukti kepemilikan tanah mereka.
Kasus serupa juga terjadi pada kasus sengketa antara PT Lestari Asri Jaya dengan warga pendatang di Kabupaten Tebo. Mereka saling meng-klaim sebagai pihak yang memiliki secara syah tanah tersebut.
Pelanggaran hak atas kebebasan (18%), terjadi ketika aparat Pemerintah melakukan penangkapan semena-mena terhadap masyarakat yang melawan penyerobotan tanah. Peritiwa penangkapan besar-besaran terjadi dalam kasus sengketa tanah PT Arara Abadi di Kabupaten Bengkalis. Sebanyak 200 orang ditangkap dalam sebuah sweeping yang mencekam dan berdarah. Hal demikian juga terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana 60 warga yang menentang penyerobotan tanah PT Smart ditangkap. Contoh serupa juga dialami 24 warga penentang tambang PT. Fathi Resources di Kabupaten Sumba Timur.
Pelanggaran terhadap integritas pribadi, seperti dijumpai pada kasus-kasus yang diwarnai bentrokan. Bentrokan bisa terjadi antara masyarakat dengan petugas keamanan perusahaan maupun dengan aparat kepolisian. Tidak jarang sweeping oleh kepolisian dengan jumlah personel yang besar dilakukan di desa-desa dengan tujuan penangkapan mendapatkan perlawanan dari warga yang berakhir dengan penembakan dan penganiayaan.
Seperti yang terjadi dalam kasus PT. Permata Hijau Pasaman II di Kabupaten Pasaman Barat, sebanyak 20 orang mengalami luka tembak. Peristiwa berdarah PTPN VII di Ogan Ilir juga menyebabkan 23 warga luka tertembak.
Berikut merupakan daftar jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering dilakukan pelaku, yakni dari entitas negara (dalam hal ini seperti aparatur bersenjata, Brimob), atau dari kalangan korporasi, dan dari entitas individu yang memiliki kekuasaan:
|
Jenis Pelanggaran |
Prosentase |
| Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber alam |
25% |
| Pelanggaran terhadap hak untuk memiliki atau menguasai kekayaan |
19% |
| Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan |
18% |
| Serangan terhadap integritas pribadi |
7% |
| Pelanggaran terhadap hak atas lingkungan yang sehat |
7% |
| Pelanggaran terhadap hak hidup |
6% |
5) Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan
Konflik sumber daya alam terjadi di kawasan perkebunan, kehutanan, tambang, adalah buntut dari kebijakan Pemerintah yang dengan sewenang-wenang memberikan perijinan dan konsesi kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekstraktif seperti perkebunan dan pertambangan skala luas. Di sektor kehutanan masalah terbesar yang diwariskan oleh Pemerintah hingga kini adalah dengan penunjukan kawasan hutan secara sepihak tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat, lokal, serta kelangsungan ekosistem dan lingkungan berkelanjutan pada kawasan-kawasan yang ditunjuk tersebut.
Dalam pemberian ijin-ijin dan penunjukan tersebut, Pemerintah di segala tingkatan tidak menggunakan prinsip persetujuan dini tanpa paksaan atau mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Padahal, di banyak kasus, masyarakatlah yang sejak awal membuka hutan, dan mendiami lahan-lahan garapan mereka atau tanah-tanah ulayat. Pengambilalihan lahan-lahan komunitas lokal, masyarakat adat, atau petani yang sebagian terjadi di masa lalu (1965), masa Orde Baru, maupun setelah masa Reformasi inilah yang menjadi akar konflik agraria yang berlangsung hingga sekarang.
Konflik agraria ini terus meluas, menyebar, membara, dan berkelanjutan karena Pemerintah terus-menerus memberikan ijin-ijin atau konsesi-konsesi kepada perusahaan-perusahaan skala luas tersebut, tetapi di sisi lain membiarkan konflik-konflik agraria itu terjadi tanpa penanganan yang menyeluruh dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban.
Konflik agraria sekarang menjadi meluas karena Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, salah satunya dengan membuka perkebunan-perkebunan baru kelapa sawit, baik di atas tanah-tanah yang diklaim masyarakat sebagai tanah ulayat mereka, maupun dengan mengkonversi hutan. Di tengah sistem hukum yang mengindahkan keberadaaan klaim-klaim masyarakat atas sistem penguasaan lahan masyarakat, Pemerintah melalui aparatur penegak hukum dan bersenjatanya menopang kekuasaan perusahaan-perusahaan pemegang bukti formal meski terkadang diperoleh dengan mekanisme yang koruptif. Ini tampak kuat terjadi pada semua sektor konflik.
Negara, tak hanya memfasilitasi perusahaan-perusahaan untuk mengambil-alih tanah masyarakat, tetapi juga membangun mesin pencari keuntungan sendiri melalui PTPN-PTPN. Walhasil, perusahaanlah yang menjadi aktor utama yang berkonflik dengan masyarakat. Modus yang digunakan oleh perusahaan untuk membungkam masyarakat yang memprotes perampasan lahan itu adalah dengan menggunakan aparat hukum seperti polisi (Brimob) dan TNI. Mereka juga menggunakan centeng atau preman bayaran.
Penanganan konflik agraria oleh Pemerintah juga cenderung represif, sehingga alih-alih membuat konflik selesai, Pemerintah dan aparat penegak hukumnya bersama-sama perusahaan, justru melakukan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak sipil politik ketika melakukan penanganan terhadap masyarakat yang menuntut hak atas tanah. Pelaku pelanggaran HAM juga meluas, tak hanya negara, aparatusnya, dan perusahaan, tetapi juga para individu yang menjadi pemimpin-pemimpin kampung.
Rekomendasi
Konflik-konflik agraria tersebut akan terpelihara selama Pemerintah tidak melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, moratorium atas semua perijinan untuk perusahaan-perusahaan di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pesisir. Kedua, menghentikan segala bentuk penanganan konflik dengan cara kekerasan, Ketiga, membentuk sebuah lembaga Penyelesaian Konflik Agraria yang bertugas mengidentifikasi, menyelidiki, konflik-konflik agraria yang terjadi, case by case, dan memberikan rekomendasinya kepada pemerintah. Keempat, dari rekomendasi lembaga tersebut, pemerintah melakukan tindakan tegas berupa pencabutan maupun pembatalan izin-izin perusahaan tersebut, dan menindak secara pidana terhadap perusahaan maupun aparat pemerintah yang melakukan perampasan tanah rakyat, kelima, melakukan review terhadap peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih di bidang sumber daya alam dan semua perizinan yang dikeluarkan di bidang sumber daya alam, dan keenam, mengembalikan tanah-tanah hasil rampasan perusahaan maupun pemerintah kepada masyarakat sebagai pemiliknya. Keseluruhannya, dilaksanakan dalam kerangka menjalankan amanat TAP MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
[1] http://www.mongabay.co.id/2012/12/03/foto-udara-kehancuran-hutan-jambi-akibat-perambahan-ekspansi-perkebunan/
Klik untuk melihat dan mendownload Brief Outlook 2012 : Brief Outlook 2012


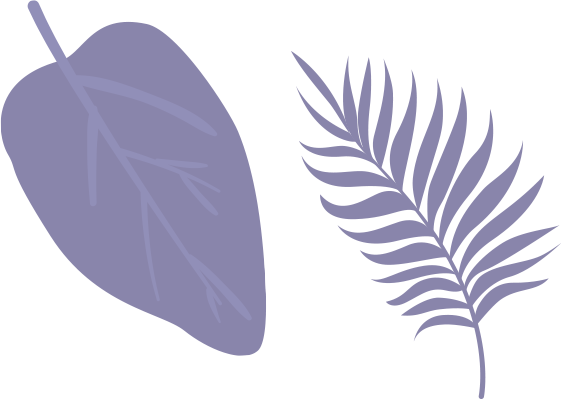
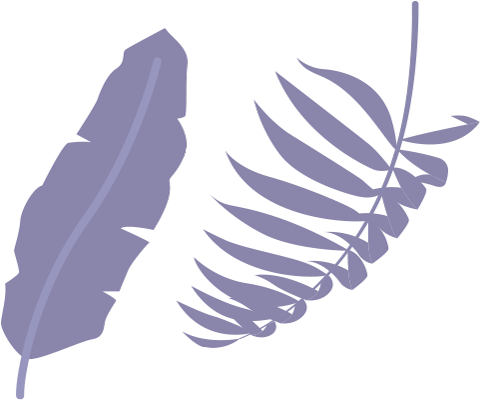
3 Komentar
Tinggalkan Balasan