Oleh Anggalia Putri Permatasari [1]
“Ketika kekuasaan berada di tangan rakyat dan komunitas, kehidupan dan inovasi tumbuh subur. Ketika kekuasaan terpusat di tangan badan-badan pemerintah atau perusahaan yang letaknya nun jauh di sana, kehidupan komunitas disedot ke luar…. Mereka yang membuat keputusan tumbuh makmur sementara komunitas lokal menanggung konsekuensinya.”
(Korten, The Great Turning)
Kuasa atas teritori dan sumber daya alam adalah kuasa atas kehidupan. Sejak dulu, masyarakat adat dan komunitas lokal hidup berdampingan dengan alam dan memiliki ikatan yang sangat kuat dengan tanah dan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya. Bahkan di zaman penjajahan, ada masanya ketika masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki otonomi untuk mengatur kehidupan dan pemerintahan mereka sendiri, termasuk mengenai bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka, tidak hanya untuk kesejahteraan kaumnya, melainkan juga untuk menopang masyarakat luar (baca: penduduk kota) dan demi kelestarian alam itu sendiri.[2] Sayangnya, kemudian datanglah masa-masa gelap di mana otonomi tersebut dipatahkan dengan paksa oleh tangan-tangan besi dari luar yang menamai diri mereka pemerintah pusat. Sentralisasi dan penyeragaman tata pemerintahan lokal di zaman Orde Baru dalam bentuk desa-desa yang ‘terstandardisasi’ semakin mencerabut kuasa lokal komunitas atas teritori dan sumber daya alamnya.
Berbagai proyek pembangunan dari atas yang bertujuan untuk memodernisasi segala sesuatu yang dipandang ‘terbelakang’ disuntikkan begitu saja, dengan atau tanpa persetujuan komunitas yang terdampak, bila perlu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan (yang karena berasal dari negara diklaim sebagai sesuatu yang sahih).[3] Ketika bangsa ini beranjak pada era reformasi dan desentralisasi, munculah segelintir harapan untuk kembali menarik kuasa ke tingkat paling bawah sehingga kedaulatan dan pemberdayaan rakyat dalam maknanya yang paling sejati dapat tercapai. Sayangnya, perubahan di tingkat pemikiran tidak serta-merta tercermin dalam praktik di lapangan, terlebih di tengah rezim penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam saat ini yang menempatkan negara bukan hanya sebagai pengelola, tapi pemilik absolut yang justru meminggirkan komunitas lokal, bahkan memandang mereka tidak ada.
Tulisan singkat ini membahas salah satu kegiatan HuMa berkenaan dengan upaya untuk mendorong pengembalian kuasa dan kontrol atas sumber daya alam ke tangan masyarakat adat dan komunitas lokal di Sulawesi Tengah melalui gerakan pembaharuan hukum. Kegiatan ini terkait dengan salah satu skema penanggulangan perubahan iklim yang saat ini tengah gencar dipromosikan oleh pemerintah pusat dan daerah, yakni REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degaradasi Hutan. Saat ini, REDD+berkembang menjadi salah satu isu terhangat dan menyetir perdebatan tentang kehutanan dan iklim.
Perubahan Iklim, REDD+, dan Sulawesi Tengah
Isu perubahan iklim dan penanggulangannya saat ini tidak hanya mendominasi wacana lingkungan di tingkat global , tetapi juga telah mulai merambah kehidupan masyarakat di tingkat lokal. REDD+ yang mempromosikan pengurangan emisi karbon yang berasal dari penggundulan dan kerusakan hutan mencuat sebagai primadona internasional untuk menanggulangi perubahan iklim karena dipandang tidak terlalu memberatkan negara-negara maju. Skema yang pada awalnya diusulkan oleh Papua Nugini dan Kosta Rika ini kemudian diadopsi sebagai program pemerintah Indonesia setelah SBY mendeklarasikan komitmennya untuk mengurangi emisi karbon nasional sebesar 26% (dengan upaya sendiri) atau 41% (dengan bantuan negara-negara lain). Komitmen tersebut dianggap luar biasa dan lalu mendatangkan miliaran dollar bantuan asing. Sejak itu, bermunculanlah berbagai kebijakan, peraturan, program, dan proyek terkait REDD+ di tingkat nasional, sub-nasional, dan lokal dengan komunitas sebagai ‘ujung mata rantai.’
Proses yang bergulir sangat cepat dari atas ini, yang disusun tanpa disertai informasi dan ruang partisipasi yang memadai, juga tanpa basis hak komunitas yang kuat, telah menimbulkan banyak keresahan dan kekhawatiran di tingkat masyarakat adat dan komunitas lokal. Kekhawatiran terbesar komunitas berkaitan dengan dengan keamanan tenurial, hak mereka atas lahan dan sumber daya alam lainnya yang hingga saat ini masih belum mendapat jaminan formal yang memadai dari negara. Hak-hak ini masih kerap diabaikan oleh aktor-aktor yang berkepentingan dengan teritori dan sumber daya alam mereka. REDD+bagaimanapun juga adalah proyek berbasis lahan dan ruang. Di tengah bobroknya tata kelola sektor kehutanan di Indonesia, makhluk ini tidak jarang dipandang sebagai hantu lain yang akan menambah rumitnya masalah komunitas. Pengalaman-pengalaman buruk warga desa ketika berhadapan dengan pihak ‘luar,’ termasuk Negara, masih membekas dan membayang.
Sulawesi tengah adalah salah satu provinsi yang menjadi lokasi percontohan (pilot province) REDD+ di Indonesia, yaitu di bawah program UN-REDD, kerja sama di antara beberapa organisasi internasional (FAO, UNDP, UNEP) dan Kementerian Kehutanan. Pada tahun 2011, Sulawesi Tengah diklaim sebagai provinsi yang paling siap untuk menjalankan REDD+.
un-redd.or.id
HuMa bersama Perkumpulan Bantaya dan jaringan aktivis lokal telah lama bekerja di Sulawesi Tengah untuk mempromosikan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Terkait perubahan iklim, aktivitas HuMa di Sulteng ditekankan pada upaya mendorong pembentukan peraturan di tingkat daerah dan lokal yang mengakomodasi kepentingan dan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, khususnya dalam konteks implementasi program REDD+ di Sulteng. Salah satu aktivitas yang dijalankan HuMa, Perkumpulan Bantaya dan jaringan adalah upaya mendorong penyusunan peraturan di tingkat regional (kabupaten) dan lokal (desa) yang mengandung substansi prinsip free and prior informed consent (FPIC), tidak hanya dalam program REDD+ tapi juga seluruh program pembangunan.
Meskipun perkembangan REDD+ di Sulteng baru sampai pada tahap pembangunan institusi, peraturan, dan kebijakan (strategi), serta belum memasuki tahap implementasi proyek yang spesifik, terdapat banyak preseden dari proyek-proyek pembangunan di masa lalu yang memperlihatkan kasus-kasus pengabaian dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, misalnya dalam kasus pembangunan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang membatasi akses komunitas adat dan masyarakat lokal terhadap hutan. Selain itu, studi pendahuluan yang dilakukan pada tahun 2011 mengenai potret pelaksanaan FPIC di Sulteng[4] menemukan bahwa hak FPIC komunitas lokal secara konsisten terus terlanggar dalam proyek DA REDD+, ditambah lagi dengan simpang siurnya tata batas kawasan hutan dan wilayah kelola masyarakat. Sebagaimana analisis awal mitra-mitra HuMa yang bekerja di lapangan, ketidakjelasan batas wilayah ini dapat memicu konflik ketika pelaksanaan proyek REDD+ di Propinsi Sulawesi Tengah tidak memperhatikan dengan seksama kondisi riil yang terjadi di masyarakat. Hingga bulan Oktober 2012, HuMa mencatat terdapat 72 konflik di kawasan hutan, yang tersebar di 17 provinsi. Di Sulteng sendiri, tercatat setidaknya sembilan konflik aktif yang mencakup wilayah seluas 55.603 ribu hektar (Database Konflik HuMa per-18 Oktober 2012).
Atas dasar ini, HuMa berkolaborasi dengan jaringan NGO Sulteng berinisiatif untuk menyusun naskah akademik peraturan daerah yang bernafaskan FPIC sebagai salah satu safeguard (rambu pengaman) dalam proyek pembangunan yang datang dari pemerintah, termasuk REDD+. Draft peraturan ini kemudian dikemas dengan nama Ranperda Demokratisasi Pembangunan yang rencananya akan didorong ke pihak Legislatif Daerah Sulteng.
Diskusi Kampung dan Masalah-Masalah Pembangunan di Sektor Kehutanan
Sejak bulan November hingga Maret 2012, HuMa dan jaringan NGO lokal di Sulteng telah mengadakan serangkaian diskusi kampung di lima desa dan dua kabupaten[5] untuk menggali aspirasi dan masukan dari tingkat akar rumput, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi warga desa. Putaran diskusi kampung di lima desa yang dihadiri secara total oleh lebih dari seratus orang ini berhasil menggalang dukungan di tingkat lokal terhadap Ranperda Demokratisasi Pembangunan sekaligus menggali berbagai masalah pembangunan yang dihadapi masyarakat adat dan komunitas lokal di wilayah masing-masing dengan sektor kehutanan sebagai titik tekannya. Hasil dari diskusi kampung ini menggarisbawahi pentingnya merebut kembali kuasa lokal atas teritori dan sumber daya alam sebagai prasyarat partisipasi sejati komunitas lokal dalam pembangunan. Perjuangan panjang untuk merebut kembali kuasa lokal memang belum dapat menumbangkan cengkeraman doktrin Hak Menguasai Negara yang sampai saat ini belum terpatahkan. Namun, berbagai wacana baru pembangunan berbasiskan hak membuka pintu-pintu baru untuk mendesak negara dan aktor-aktor lain untuk mengakui hak-hak asli komunitas lokal atas teritori dan sumber dayanya, salah satunya adalah wacana free prior and informed consent atau FPIC. Berikut ini adalah nukilan singkat dari proses dan hasil dari putaran diskusi kampung tersebut dan isu-isu penting yang mewarnainya.
Ngata Toro
Berbagai masalah pembangunan terangkat dalam diskusi kampung di Desa Toro (yang lebih memilih istilah ’Ngata’ untuk menggambarkan kesatuan sosial-politik mereka). Berbagai permasalahan di sektor ekonomi, pertanian, hukum, kehutanan, hingga kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian warga desa. Di sektor hukum dan kehutanan pada khususnya, warga desa secara umum merasakan ketidakadilan berkenaan dengan penerapan hukum negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Di samping pertentangan antara hukum negara dan hukum adat yang kerap terjadi, terdapat pula kesenjangan di antara pemerintah dan masyarakat dalam hal konsep dan praktik tata guna lahan, khususnya pemanfaatan hutan, di mana praktik dan pengetahuan pengelolaan hutan berbasiskan kearifan lokal tidak diakui dan justru terkriminalisasi oleh hukum formal negara. Selain itu, warga desa juga merasakan kurangnya keterbukaan informasi dalam hal pembangunan (misalnya alokasi anggaran daerah) dan minimnya ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan di sektor kehutanan, yang pada gilirannya menghilangkan hak dan membatasi akses mereka terhadap hasil hutan dan ruang hidup. Di sisi lain, di tingkat lokal sendiri belum ada peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam berbasiskan kearifan lokal yang bernafaskan kedaulatan komunitas. Oleh karena itu, diskusi kampung ini merekomendasikan penyusunan peraturan lokal (’Peraturan Ngata’) yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan penguatan nilai-nilai adat dalam kehidupan Ngata, termasuk peraturan yang mengatur peralihan nama dari ’Desa’ menjadi ’Ngata.’
Pertemuan di Salah Satu Kampung
Komunitas Tompu
Secara administratif, Komunitas Tompu terbagi menjadi dua desa, yaitu Ngata Baru dan Desa Loru. Kesan ketertinggalan dalam hal pembangunan sangat terasa di wilayah ini, yang dapat dikatakan berakar pada minimnya kuasa lokal atas teritori dan sumber daya alamnya. Di dalam diskusi kampung, terkuak bahwa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Ngata Baru belum memiliki kewenangan jelas untuk mengatur dan mengelola aset-aset desa dan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Sebagai contoh, kewenangan untuk mengelola objek Wisata Alam Kapopo yang berada di wilayah Ngata Baru berada jauh di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, masyarakat Ngata Baru merasa tidak memperoleh manfaat dari pemasangan pipa air minum yang dilakukan oleh dinas terkait. Untuk komunitas Tompu yang secara khusus berada di wilayah Taman Hutan Rakyat (TAHURA), terdapat pertanyaan besar mengenai status hukum mereka. Setelah mengalami pemindahan paksa pada tahun 1975 karena wilayahnya diklaim sebagai bagian dari hutan lindung (yang kemudian ditetapkan sebagai TAHURA pada tahun 1990), pada tahun 1998 mereka kembali ke wilayah Tompu dan menuntut hak-hak keperdataan mereka. Ketidakjelasan status hukum dan batas-batas wilayah mengancam keamanan tenurial dan kualitas hidup komunitas ini. Di samping itu, pemerintah lokal di wilayah Desa Ngata Baru belum memiliki produk-produk hukum berupa peraturan desa sebagai alat legitimasi pengaturan wilayahnya.
Desa Talaga
Terjadi sebuah hal menarik ketika diskusi kampung di Desa Talaga ini berlangsung. Warga desa digegerkan oleh berita pemasangan patok/tapal batas tanpa sosialisasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi yang melewati tanah dan kebun-kebun mereka. Keresahan pun menyeruak, berujung pada munculnya kelompok yang pro- dan kontra- terhadap skema REDD+ yang dicurigai berkaitan dengan pemasangan patok ’siluman’ tersebut. Berkaitan dengan masalah kehutanan secara umum, ketidakjelasan batas antara Hutan Lindung dan ruang kelola masyarakat mengakibatkan warga desa merasa tidak aman dalam mengelola hutan. Pembatasan akses mereka terhadap hasil hutan juga berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan dan tingkat kualitas hidup mereka. Selain itu, warga desa pun mempermasalahkan penetapan status Hutan Lindung secara sepihak yang dengan vulgar melanggar hak FPIC mereka. Berkaitan dengan hal ini, warga Desa Talaga merekomendasikan penyusunan peraturan desa mengenai tata kelola hutan sebagai langkah awal untuk mengembalikan kendali dan kuasa lokal atas sumber daya alam.
Presentasi Kelompok di Desa Talaga
Desa Povelua
Dari diskusi kampung di Desa Povelua, tampak bahwa masyarakat di Desa Povelua menghadapi masalah pembangunan yang cukup besar karena desa mereka dipadati oleh tiga aktivitas ekstraktif masif sekaligus: tambang emas, besi, dan perkebunan sawit. Berbagai aktivitas ’pembangunan’ tersebut datang dari luar sementara usulan-usulan pembangunan dari masyarakat desa sendiri hingga saat ini belum pernah disetujui oleh pemerintah derah setempat. Kebutuhan masyarakat desa akan layanan publik dasar seperti jalan dan listrik pun masih terabaikan sementara skema-skema pembangunan lain seperti perkebunan komoditas (misalnya cengkeh dan cokelat) justru bermunculan. Dari berbagai permasalahan tersebut, muncul inisiatif untuk memperkuat institusi adat istiadat (Lipu Ngata) dan meninjau kembali isi peraturan desa yang relavan.
Desa Salungkaenu
Dari diskusi di Desa Salungkaenu, berbagai masalah pembangunan di sektor kehutanan terungkap. Senada dengan permasalahan mendasar di desa-desa lainnya, status Hutan Lindung yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah pusat menjadi pertanyaan besar, juga kawasan hutan negara berbasiskan hukum formal yang tidak ramah terhadap wilayah adat dan hak-hak pengelolaan yang melekat padanya, belum lagi salah urus kawasan yang menyebabkan seringnya banjir di salah satu dusun di desa ini. Berbagai masalah ini, yang hanya merupakan satu dari sekian banyak masalah pembangunan di sektor-sektor lainnya, sangat berdampak pada kualitas hidup masyarakat Desa Salungkaenu. Salah satu rekomendasi dari diskusi kampung ini adalah pendampingan penyusunan peraturan desa untuk mendemokratiskan pembangunan dan mendesak pemerintah untuk memperjelas tata batas kawasan hutan dengan mengakui dan menghormati kuasa dan wilayah kelola adat dan masyarakat lokal.
Pemetaan Masalah di Desa Salungkaenu
Dari kelima nukilan singkat diskusi kampung di atas, tampak bahwa akar dari berbagai masalah pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat desa adalah tercerabutnya kuasa atas teritori dan sumber daya alam dari masyarakat dan komunitas lokal yang kemudian dikonsentrasikan di berbagai sentra kekuasaan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal. Proyek pembangunan kehutanan terkini yang diusung di bawah tema penanggulangan perubahan iklim berpotensi mengulangi pola pemaksaan dari atas di tengah tidak adanya basis legal penguasaan komunitas yang kuat. Hal ini hanya dapat dilawan dengan merebut kembali kontrol sumber daya ke tingkat lokal, termasuk dengan menggunakan wacana dan pendekatan hak yang mulai terakomodasi dalam kebijakan dan program-program terkait REDD+.
Meskipun bukan obat bagi segalanya, FPIC adalah salah satu pintu masuk yang dapat digunakan untuk mengambil kembali kekuasaan ke tingkat akar rumput, yakni dalam hal kekuasaan untuk menolak atau menerima sebuah skema atau program pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya atau yang berpotensi memberikan dampak. Dari segi paradigmatik, FPIC menjungkirkan paradigma pembangunan lama yang menganggap masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai objek dan bukan subjek pembangunan, yang aspirasinya dipandang inferior dibandingkan program dan rencana dari pusat atau luar negeri. Dari segi implementasi, pelaksanaan FPIC yang pada dasarnya merupakan hak prosedural dapat menjaga dan mendorong pemenuhan hak-hak lain yang merupakan prasyaratnya, termasuk hak atas informasi, partisipasi, hak untuk tidak diteror dan diintimidasi, dan sebagainya. Wacana FPIC yang tampak asing ini sebetulnya beresonansi dan dapat memperkuat tradisi dan norma-norma lokal yang mensyaratkan pihak luar ’permisi’ dan meminta persetujuan warga desa jika hendak melakukan sesuatu di wilayahnya. Dengan demikian, mendorong peraturan–peraturan daerah dan lokal yang bernafaskan FPIC untuk lebih mendemokratiskan pembangunan dapat dijadikan awal untuk mengklaim kembali kuasa untuk mengelola sumber daya alam di tingkat lokal. Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa yang lebih penting dari formalisme hukum dan keberadaan peraturan adalah komunitas yang terorganisasi dengan baik, yang memiliki power secara de facto untuk merumuskan, menyampaikan, dan mempertahankan kepentingan mereka akan pengelolaan sumber daya alam. Segala bentuk wacana, peningkatan kesadaran, dan pelatihan tentang hak maupun penyusunan peraturan harus jatuh pada konteks ini.
Sebagaimana ucapan Korten yang menjadi pembuka tulisan ini, kekuasaan yang berada jauh dari komunitas dan tersentralisasi di tangah pemerintah pusat, daerah, atau perusahaan hanya akan menyejahterakan mereka yang memegang kuasa tersebut sementara masyarakat lokalah yang menanggung segala dampak buruknya. Merebut kembali kontrol lokal atas ruang dan sumber daya alam adalah sesuatu yang mutlak untuk mencapai pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang sesungguhnya sehingga mereka benar-benar menjadi tuan di tanah mereka sendiri.
***
[1] Tulisan ini dibuat berdasarkan laporan tim pelaksana lapangan di Sulteng. Terima kasih penulis haturkan kepada Martje Leninda, Emma, Ewin Laudjeng, Wing Prabowo, Syahrun Latjupa, Syafruddin, Fathurrahman dan rekan-rekan lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
[2] Sebagian besar masyarakat desa atau komunitas pedesaan di seluruh Indonesia merupakan persekutuan atau kesatuan masyarakat hukum (rechtsge-meen-schap). Selama penjajahan Belanda, berdasarkan prinsip pemerintahan tidak langsung (indirect rule) yang dianut pemerintah jajahan, komunitas desa dibiarkan hidup dalam kesatuan sistem sosial dan sistem budayanya dan diberi kewenangan mengatur dirinya sesuai dengan hukum adatnya. Lihat Sardjono Jatiman, “Pemerintahan Desa: Antara Harapan dan Kemampuan,” Jurnal Masyarakat Vol. II tahun 1995, h. 34.
[3] Pemerintah Orde Baru memaksakan pembaruan dan penyeragaman kesatuan masyarakat hukum adat dalam bentuk desa administratif dan melakukan pelembagaan desa melalui UU No. 5 tahun 1979. Lihat ibid., h. 36-7.
[4] Lihat Laporan HuMa, Tak Ada Alasan Ditunda: Potret FPIC dalam Demonstration Activities REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah (HuMa: Jakarta, 2011).
[5] Di Kabupaten Sigi, ada dua lokasi pilihan pelaksanaan kegiatan yaitu Desa Toro Kec. Kulawi dan Tompu yang secara administratif terbagi dalam wilayah Desa Ngata Baru dan Desa Loru. Di Kabupaten Donggala, ada tiga lokasi pilihan pelaksanaan kegiatan yaitu di Desa Talaga Kec. Dampelas Sojol (Damsol), Desa Povelua Kec. Banawa Tengah dan Desa Salungkaenu Kec. Banawa Selatan.






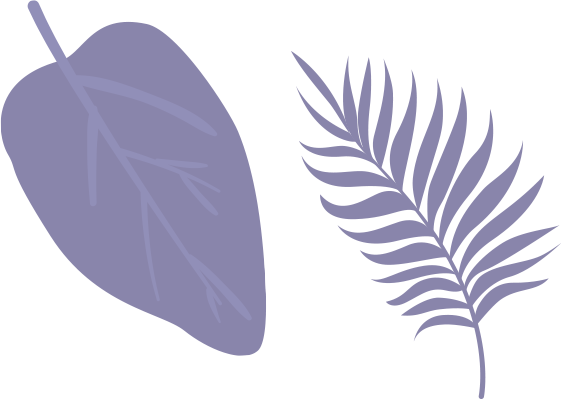
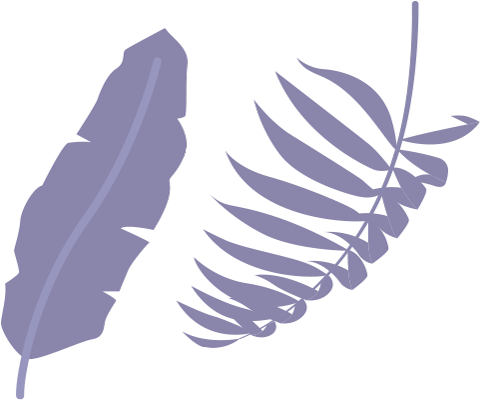
0 Komentar
Tinggalkan Balasan