oleh Deni Bram, Doktor Hukum Perubahan Iklim Universitas Indonesia dan Pengajar Hukum Lingkungan Universitas Tarumangara
Saat perdebatan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sesi ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum dengan salah satu tema Politik Internasional (22 Juni 2014) isu lingkungan internasional menjadi suatu hal yang kurang mendapatkan perhatian bagi para capres dan cawapres. Bahkan kekecewaan itu dirasakan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim yang melihat tidak ada pembahasan mendalam terkait isu emisi di Visi dan Misi Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Padahal, secara momentum penyelenggaraan debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sesi ketiga kemarin memiliki tenggat waktu yang berdekatan dengan diadakannya pertemuan tahunan dari Konferensi Perubahan Iklim yang berlangsung di Bonn, Jerman mulai dari 4 Juni 2014 sampai dengan 15 Juni 2014. Momentum ini seharusnya dapat dioptimalkan oleh para kandidat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dengan melakukan evaluasi kritis dengan mengusung strategi penyelamatan iklim yang dapat diusung oleh Pemerintah Indonesia ke depan. Urgensi dari kondisi ini pun semakin tinggi saat Indonesia telah mencatatkan komitmennya dalam dokumen internasional dan memiliki kekuatan mengikat dalam kerangka yuridis yang pada saat bersamaan telah diadopsi dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
Pada Conference on the Parties (COP) ke-19 di Bonn tahun ini menjadi semakin penting saat dalam pertemuan yang sama dibicarakan pula agenda serta strategi penyelamatan iklim yang akan menjadi alas untuk pertemuan selanjutnya di Lima, Peru pada akhir tahun 2014 serta pada akhirnya akan ditetapkan secara final dan mengikat pada pertemuan COP 21 di Paris pada tahun 2015. Beberapa hal strategis yang dinanti dalam rangka langkah penyelamatan iklim pada tataran dunia pada umumnya, serta peran strategis Indonesia pada khususnya menyeruak dalam pertemuan tersebut dengan mengerucut pada 3 (tiga) hal utama.
Pertama, pertemuan tahunan ke-19 ini secara implisit kembali mencoba untuk menempatkan rezim pasar sebagai satu–satunya solusi dalam upaya penyelamatan iklim. Hal ini menjadi sangat transaksional terlebih ketika Indonesia turut larut dalam rezim pasar tersebut tanpa mampu mendudukkan secara nyata posisi hukum dan personalitas dari masing–masing negara yang terlibat dalam rezim pasar tersebut. Hal ini menjadi sangat buruk saat Indonesia justru berharap mendapatkan pendanaan dari rezim pasar yang diusung sedangkan pada sisi lain keberadaan ekosistem hutan Indonesia yang diharapkan sebagai instrumen mitigasi terus berada pada angka deforestasi dan angka korupsi ekologis yang tinggi. Catatan penting yang harus diperhatikan adalah keberadaan rezim pasar justru secara perlahan namun pasti menggeser isu penyelamatan iklim dari negara annex ke negara non-annex dengan mencederai keadilan intra generasi dan menganggap transaksi karbon sebagai suatu hal yang mafhum dan layak secara etika untuk dilakukan. Hal ini pada akhirnya akan menjadi suatu pola yang berujung pada fetisisme ekologis dengan memberikan peluang kepada negara maju untuk patuh terhadap kewajibannya dengan mengandalkan instrumen yang ada dalam yurisdiksi negara–negara berkembang.
Kedua, hasil lain dari Konferensi Perubahan Iklim di bawah UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) yang berlangsung di Bonn pada pertengahan Juni 2014 memberikan umur baru bagi Protokol Kyoto yang berakhir pada tahun 2012 silam. Tercatat paling tidak 11 (sebelas) negara yang telah meratifikasi perpanjangan Protokol Kyoto Periode Komitmen Kedua yaitu Uni Emirat Arab, Barbados, Mauritius, Banglades, Monaco, Sudan, Negara Federasi Mikronesia, Kenya, Honduras, China dan Norwegia. Periode komitmen kedua ini berlaku efektif pada tahun 2013 hingga 2020 sesuai mandat dalam Doha Amendment sebagai hasil Konferensi Perubahan Iklim ke-18 di Doha, Qatar pada tahun 2012 silam. Hal ini menjadi kontradiktif pada saat eksistensi dari Protokol Kyoto justru mendapatkan vonis gagal dalam mencapai target bagi upaya penyelamatan iklim. Kehadiran Protokol Kyoto yang semula diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha penurunan nilai emisi gas rumah kaca, ternyata tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini paling tidak disebabkan oleh lemahnya keikutsertaan dan komitmen dari Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki sumbangsih besar dalam peningkatan emisi dari sektor bahan bakar fosil. Selain itu kehadiran dari Protokol Kyoto juga tidak dapat berperan maksimal pada saat negara–negara Annex yang diharapkan menjadi subyek utama dalam usaha penanggulangan perubahan iklim justru merumuskan kebijakan–kebijakan pada skala lokal dan nasional yang justru tidak mendukung dari Protokol Kyoto, sehingga membuat target penurunan konsentrasi gas rumah kaca menjadi sulit untuk dicapai. Pada sisi ilmiah, hal ini pun secara gamblang dikonfirmasi dalam publikasi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dengan mencantumkan tahun–tahun terpanas terjadi justru saat rezim Protokol Kyoto dianut. Ironisnya, konstruksi hukum yang diusung kini persis sama dengan komitmen perjanjian internasional sebelumnya, perjanjian internasional ini diperkenalkan ulang bahkan disodorkan sebagai salah satu solusi mitigasi emisi jangka panjang hingga tahun 2020. Kontradiksi lainnya terkait keberlakuan dari periode komitmen kedua ini yang mempunyai jangka waktu hingga 2020 yang secara otomatis akan selesai pada tahun 2015 yang merupakan tonggak awal dari strategi penyelamatan iklim global seiring dengan hasil COP di Paris kelak. Hal ini dapat dimaknai dalam bentuk lainnya bahwa kehadiran negara–negara maju yang mengikuti rezim periode komitmen kedua hanya dalam rangka kepentingan negosiasi internasional an sich dan tanpa langkah nyata perbaikan iklim.
Terakhir, belajar dari kegagalan rezim Protokol Kyoto yang sangat represif dan cenderung mengusung pendekatan Top Down approach hendaknya lahir sebuah pendekatan baru yang berorientasi pada tingkat kepatuhan yang relatif lebih tinggi. Penggunaan pendekatan yang berbasis pada kondisi ilmiah masing–masing negara annex sebagai landasan penurunan emisi diharapkan memberikan sedikit harapan terkait penyelamatan iklim ke depan. Langkah optimalisasi yang berbasis kajian ilmiah masing–masing sektor yang berkontribusi pada peningkatan emisi diharapkan dapat menjadi langkah awal yang secara konvergensi menuju pada penyelamatan iklim dapat menjadi solusi yang lebih konkrit ke depan. Hal ini hendaknya menjadi renungan reflektif berbasis ekologis yang menggeser isu homo ethic menjadi eco ethic dari para negosiator dalam pertemuan perubahan iklim ke depan, sehingga bukan hanya menjadi agenda rutin tahunan semata, namun dapat menjadi tonggak evaluasi dari keberadaan rezim sebelumnya untuk anak cucu pada generasi selanjutnya.***


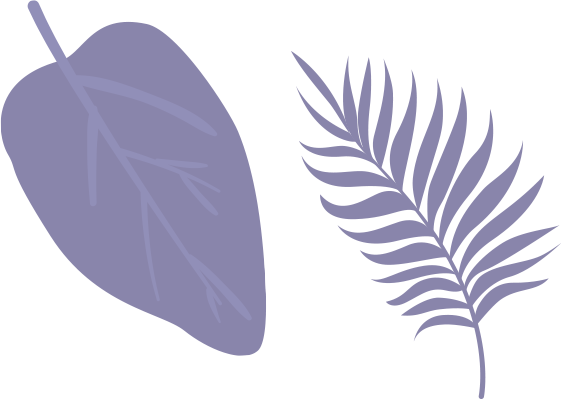
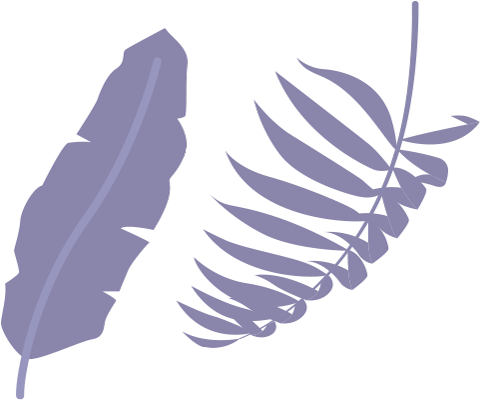
0 Komentar
Tinggalkan Balasan