Oleh Fahmi Al’amri
(Selasa, 28 oktober 2014), Perkumpulan Qbar bersama HuMa melangsungkan diskusi mengenai implementasi SRAP REDD+ Sumatra Barat dengan tema “Memastikan Aspek Tenurial Dalam SRAP Sumatra Barat Terkait Perubahan Iklim”, yang dilangsungkan selama dua hari (28-29 Oktober 2014) di Kota Padang, Sumatra Barat. Rencananya hasil dari diskusi ini akan diaudiensikan dengan Pemda Sumbar beserta dengan Pokja REDD+ dan Pokja Kehutanan Sosial.
Berbicara mengenai REDD+ maka tidak terlepas juga dari aspek tenurial, karena REDD+ akan selalu bersentuhan dengan tenure, dan REDD+ akan berhasil ketika wilayah yang masuk dalam skema REDD+ memiliki kejelasan status, karena jika tidak maka bukan keberhasilan yang akan terjadi, justru akan memunculkan konflik-konflik baru. Untuk itu kemudian, aspek hak tenur ini haruslah tertuang dalam SRAP REDD+. Hal ini sebagai bukti bahwa skema proyek yang ada di dalam REDD+ tidak akan membatasi atau mengurangi nilai-nilai hak, terutama berkaitan dengan hak atas akses terhadap wilayah kelola hutan oleh masyarakat.
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Barat melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat telah dan terus mendorong perluasan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam bentuk skema pembangunan Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat. Bila dilihat dari skema pengelolaan yang ditawarkan, kesemuanya masih menempatkan peran negara yang dominan di dalamnya. Sementara, skema Hutan Adat yang mengutamakan peran masyarakat hukum adat sebagai pemilik hak tenur dari hutan masih belum masuk dan belum didorong oleh Pemerintah Daerah Sumatra Barat. Inilah yang kemudian dilihat oleh HuMa dan Qbar, bahwa nomenklatur Hutan Adat perlu dimasukan di dalam SRAP REDD+ Sumbar.
Dari hasil diskusi yang dilakukan tersebut, ternyata skema Hutan Adat masih belum maksimal dikampanyekan kepada masyarakat. Selama ini model skema pengelolaan yang mereka kenal hanya tertitik pada dua model saja, yakni skema HKM dan Skema Hutan Desa/Nagari, sedangkan untuk skema Hutan Adat sendiri masih belum mendapatkan ruang di masyarakat. HuMa dan Qbar melihat bahwa perlunya mendorong skema Hutan Adat, hal ini juga sebagai salah satu bentuk implementasi dari hasil Putusan MK No.35/PUU-x/2012 Tentang pemisahan hutan adat dari hutan negara. Paling tidak masyarakat diperkenalkan terlebih dahulu mengenai skema Hutan Adat, nantinya model pilihan pengelolaan hutan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat akan tetap ditentukan oleh masyarakat, karena merekalah yang nantinya akan menggunakan skema pengelolaan tersebut.
Wilayah Sumatra Barat memiliki keunikan tersendiri di mana wilayah tanah minang ini dibagi berdasarkan nagari-nagari, dan masing-masing nagari pun memiliki ciri khasnya sendiri, termasuk mengenai skema pengelolaan hutan. Terkadang untuk pengelolaan hutannya pun beragam, ada yang menjadikan HKM sebagai unit pengelolaanya dan tak jarang pula yang lebih memilih skema Hutan Nagari. Untuk skema Hutan Adat sendiri, disamping belum banyaknya kampanye mendorong skema pengelolaan model ini, ditingkat tapak pun nampaknya masih terdapat beberapa permasalahan mengenai sistem pengelolaan Hutan Adat, terutama mengenai pola penguasaan wilayah yang berada dibawah para pemangku adat. Dalam diskusi tersebut, masyarakat secara jujur mengungkapkan bahwa dengan sistem pengelolaan hutan adat maka pemuka adat disinyalir akan memiliki kuasa lebih besar yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat dengan pemangku adat terkait dengan tata kelola hutan. Dari workshop kemarin disepakati juga bahwa untuk mencegah timbulnya konflik baru dari skema hutan adat, maka kekuasaan para pemuka adat ini perlu dikaji ulang sehingga kekuasaan tidak berpusat pada pemangku adat sebagai pengambil keputusan. Satu pilihan yang sempat dikemukakan adalah membongkar fungsi social tersebut, dan menyusunnya secara lebih adil. Misalnya pemuka adat menjadi “pengawas” dan bukan merupakan satu-satunya pengambil keputusan, sehingga dengan demikian pemuka adat tetap memiliki peran yang cukup penting dari pengelolaan hutan tersebut.
Kembali kepada nomenklatur Hutan Adat dalam SRAP REDD+ Sumatra Barat, di dalam SRAP REDD+ tersebut juga belum dijelaskan secara lebih mendetail mengenai skema pengelolaan Hutan Adat. Dan dari workshop ini juga coba dilakukan pemetaan terhadap model kelola hutan adat, diantaranya: Hutan adat harus berbasiskan pada kearifan lokal di masing-masing nagari. Karena pengelolaan hutan di masing-masing nagari memiliki keragaman yang berbeda, maka kemudian tidak bisa diterapkan skema pengelolaan yang bersifat universal di seluruh Nagari. Selain itu, skema hutan adat juga harus menjunjung prinsip-prinsip umum, yaitu berbasis ekologis, tidak eksploitatif, dan dapat mensejahterkan masyarakat.
Dikarenakan belum “terdengarnya” skema pengelolaan hutan adat, maka perlu dilakukan kampanye-kampanye yang bertujuan untuk mempromosikan skema hutan adat. Untuk itu sosialisasi kepada seluruh pihak harus dilakukan,serta perlu juga mendorong Pemda untuk memberikan apresiasi terhadap kearifan lokal masyarakat. Selain “sounding” mengenai skema hutan adat, diperlukan juga kebijakan yang mengatur mengenai tata kelola dari Hutan Adat itu sendiri, diantaranya adalah pengaturan yang mengatur mengenai; sanksi, mekanisme pengajuan permohonan, kelembagaan dan tata ruang, serta pengawasan dan evaluasi.
Untuk melakukan kampanye mendorong hutan adat, peran Pokja REDD+ dan Pokja Kehutanan Sosial sangat penting. Kedua Pokja ini perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong skema pengelolaan hutan adat. Harapannya adalah dengan menggunakan “tangan” Pokja maka didorongnya skema hutan adat serta kepastian tenurial di Provinsi Sumatra Barat bisa terealisasikan, baik pada tahap normative sebagai nomenklatur baru dalam SRAP REDD+ Sumatera Barat, maupun tahap implementasinya.


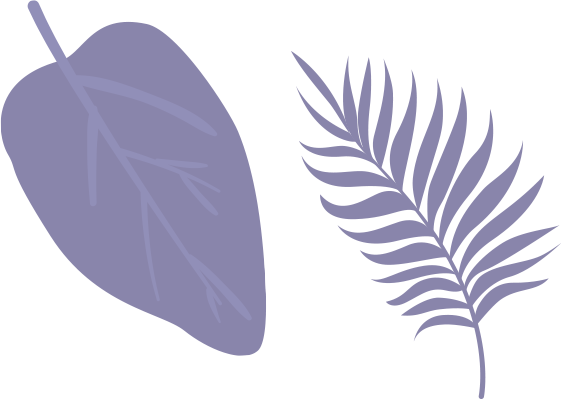
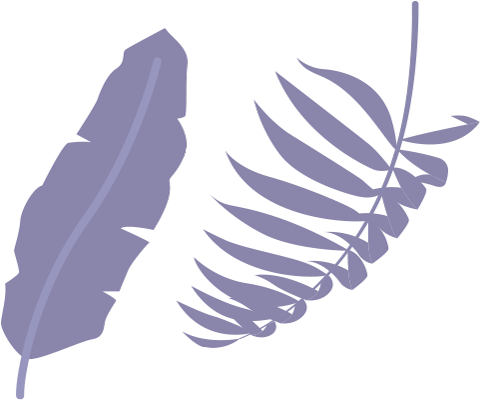
0 Komentar
Tinggalkan Balasan